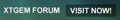CONTOH KETUJUH: Berusaha memprioritaskan dan memperhatikan dakwah dan penarikan hati orang-orang yang memiliki kedudukan di masyarakat, entah itu yang diulamakan atau penguasa.
Dalam al-Qur'an Allah ta'ala telah menghasung para nabi-Nya untuk mendakwahi golongan orang tersebut di atas dengan cara lemah lembut dan bertahap dalam menyampaikan al-haq terhadap mereka[71].
Allah ta’ala memerintahkan nabi Musa dan nabi Harun 'alaihimassalam,
]إذهبا إلى فرعون إنه طغا * فَقُولاَ لَهُ قَوْلاً لَّيِّناً لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى[.
Artinya: "Pergilah kalian berdua ke Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut". QS. Thaha: 43-44.
Allah memerintahkan nabi Musa dan Harun untuk mendakwahi Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut, agar lebih mudah diterima dan lebih membuahkan hasil[72], karena hal tersebut lebih berpengaruh untuk menarik seseorang. Sebab kata-kata yang kasar dan keras di awal mula dakwah merupakan faktor terbesar yang menyebabkan masyarakat lari menjauh dan tetap bersikeras dalam kekufuran mereka[73]. Apalagi jika yang didakwahi adalah orang-orang besar yang ghalibnya memiliki sikap sombong dan sok berkuasa, sehingga jika disikapi dengan keras mereka akan semakin menjauh[74].
Banyak praktek Rasulullah Shallallahu’alaihiwasallam dan para sahabatnya dalam menerapkan sikap hikmah di atas. Antara lain:
A. Perhatian ekstra Rasulullah Shallallahu’alaihiwasallam dalam mendakwahi para pembesar suku Quraisy[75].
B. Bahkan Rasulullah Shallallahu’alaihiwasallam terkadang memulai dakwahnya di suatu kaum dengan mendakwahi pembesar-pembesar mereka terlebih dahulu. Ibnu Ishaq rahimahullah bercerita, "Tatkala Rasulullah telah sampai di Tha'if, beliau menuju ke kediaman beberapa pembesar dan orang-orang terpandang Tsaqif ... kemudian beliau mendakwahi mereka"[76].
C. Mush'ab bin Umair salah satu sahabat yang diutus Rasul Shallallahu’alaihiwasallam untuk berdakwah di Madinah pun menerapkan metode tersebut di atas. Beliau amat memperhatikan pendekatan terhadap para pembesar suku-suku di Madinah saat itu, semisal: As'ad bin Zurarah, Usaid bin Khudhair dan Sa'ad bin Mu'adz[77].
Apa gerangan hikmah di balik besarnya perhatian Rasulullah Shallallahu’alaihiwasallam dan para sahabatnya dalam mendakwahi orang-orang yang memiliki kedudukan di masyarakat? Karena jika orang-orang penting tersebut masuk Islam, niscaya orang-orang di belakang mereka juga akan turut masuk Islam, karena "ekor sebuah ikan akan selalu mengikuti kepalanya".
Rasulullah Shallallahu’alaihiwasallam bersabda,
(لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن اليهود).
"Jikalau sepuluh orang Yahudi beriman padaku, niscaya seluruh orang Yahudi akan beriman"[78].
Al-Hafizh Ibn Hajar rahimahullah menjelaskan maksud hadits di atas, "Nampaknya sepuluh orang tersebut adalah para pembesar Yahudi, sedangkan yang lain adalah pengikut mereka"[79].
Imam Nawawi rahimahullah memetik suatu pelajaran berharga dari kisah besarnya perhatian Rasulullah Shallallahu’alaihiwasallam dalam mendakwahi Tsumamah bin Utsal; salah seorang pembesar Yamamah, "Perbuatan Rasulullah Shallallahu’alaihiwasallam ini termasuk metode penarikan hati dan sikap lemah lembut terhadap para pembesar, yang diharapkan -jika dia masuk Islam- maka akan masuk Islam pula di belakangnya orang banyak"[80].
Jadi yang melatarbelakangi perhatian kita yang besar terhadap orang-orang yang memiliki kedudukan di masyarakat adalah: harapan jika mereka mendapatkan hidayah, orang-orang yang berada di belakang mereka akan turut mendapatkan hidayah dengan izin Allah ta'ala.
Maka seyogyanya para da'i memprioritaskan dakwahnya terhadap golongan tersebut di atas, bukan malah sejak awal langsung berkonfrontasi dengan mereka. Karena hal itu justru akan lebih banyak merugikan dakwahnya; sebab dia adalah 'orang baru' sedangkan mereka adalah 'pemain lama' yang telah memiliki banyak pengikut.
Di antara metode yang digunakan oleh Rasulullah Shallallahu’alaihiwasallam dalam melakukan pendekatan terhadap strata masyarakat di atas: pemberian hadiah materi terhadap mereka. Sebab manusia diciptakan bertabiat mencintai orang yang berbuat baik padanya. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu’alaihiwasallam bersabda,
(تهادوا تحابوا).
"Saling berilah hadiah di antara kalian niscaya kalian akan saling mencintai"[81].
Di dalam al-Qur'an Allah menyebutkan bahwa salah satu dari delapan golongan yang berhak mendapatkan zakat adalah orang-orang yang diharapkan masuk Islam,
]إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم[ التوبة 60
Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk (jihad) di jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". QS. At-Taubah: 60.
Di antara contoh praktek nyata Rasulullah Shallallahu’alaihiwasallam dalam menerapkan metode ini adalah tatkala beliau memberi hadiah yang sangat besar kepada Shafwan bin Umayyah yang saat itu masih musyrik. Beliau Shallallahu’alaihiwasallam memberinya seratus onta, kemudian ditambah lagi seratus, dan ditambah lagi seratus[82], sehingga genap tiga ratus onta! Jika harga satu onta adalah 2,5 juta berarti sama saja Rasulullah Shallallahu’alaihiwasallam telah memberi Shafwan uang sebesar: 750 juta! Subhanallah, hanya untuk mengharapkan islamnya satu orang saja Rasulullah Shallallahu’alaihiwasallam rela mengeluarkan uang 750 juta!? Memang betul-betul Nabi kita Shallallahu’alaihiwasallam sebagaimana yang dikatakan Allah dalam al-Qur'an, "Sangat mengharapkan (keimanan dan keselamatan) bagi kalian". QS. At-Taubah: 128.
Lantas apakah gerangan hasil dari pendekatan yang dilakukan Rasulullah Shallallahu’alaihiwasallam tersebut? Kita persilahkan Shafwan bin Umayyah sendiri yang menceritakannya, dia berkata, "Demi Allah, tatkala Rasulullah (pertama kali) memberi hadiah padaku, saat itu dia adalah orang yang paling aku benci, namun tatkala beliau terus menerus memberiku hadiah, akhirnya beliau (berubah) menjadi orang yang paling aku cintai"[83].
Kita pun bisa menerapkan metode di atas, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Bisa dengan mengirimkan oleh-oleh ketika kita pulang dari bepergian jauh, bisa dengan mengirimkan masakan ketika kita sedang melakukan walimah aqiqah dan lain sebagainya.
Mungkin ada yang berkomentar, "Kalau kita menggunakan metode ini berarti kita telah melatih orang-orang untuk masuk Islam bukan karena Allah namun karena materi duniawi?!".
Jawabnya: tidak mengapa awalnya hal itu yang menjadi tujuan mereka untuk masuk Islam atau tertarik dengan dakwah salaf, namun dengan berjalannya waktu, kita akan menggembleng mereka guna mengikhlaskan niat lillahi ta'ala. Anas bin Malik bercerita, "Terkadang (di masa kami) ada orang yang masuk Islam hanya karena menginginkan materi duniawi, namun tatkala dia telah (mempelajari ajaran-ajaran) Islam, saat itu Islam menjadi lebih ia cintai dari dunia seisinya"[84].
-----
Footnote
[71] Lihat: At-Tadarruj fi Da'wah an-Nabi Shallallahu’alaihiwasallam (hal. 110).
[72] Tafsir Ibn Katsir (V/295).
[73] Fath al-Qadir karya Imam asy-Syaukani (V/1 -dalam al-Maktabah asy-Syamilah).
[74] At-Tafsir al-Kabir (X/411 -dalam al-Maktabah asy-Syamilah).
[75] Lihat: As-Sirah an-Nabawiyah karya Ibn Katsir (I/478-479).
[76] Lihat: Sirah Ibn Hisyam (hal. 415).
[77] Lihat: Sirah Ibn Hisyam (hal. 435).
[78] HR. Bukhari (no. 3941 hal. 810).
[79] Fath al-Bari (VII/344 -cet Darussalam).
[80] Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj (XI/309).
[81] HR. Bukhari dalam al-Adab al-Mufrad (I/306 no. 594) dan dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam Irwa' al-Ghalil (VI/44 no. 1601).
[82] HR. Muslim (IV/1806 no. 2313 -asy-syamilah).
[83] HR. Muslim (IV/1806 no. 2313 -asy-syamilah).
[84] Diriwayatkan oleh Muslim (IV/1086 no. 2312).
Naskah ini merupakan tulisan Ustadz Abdullah Zaen, Lc. hafidzahullahu yang menjelaskan empat belas contoh praktek hikmah dalam berdakwah.
Wednesday, September 1, 2010
CONTOH KEDELAPAN
CONTOH KEDELAPAN: Memperhatikan dakwah generasi muda dan anak-anak kecil, tanpa mengesampingkan orang-orang yang sudah lanjut usia.
Banyak sekali hadits-hadits Nabi Shallallahu’alaihiwasallam yang menggambarkan betapa besar perhatian beliau dalam mendakwahi generasi muda dan anak-anak kecil. Di antaranya:
Sabda Nabi Shallallahu’alaihiwasallam kepada Ibnu Abbas,
(يا غلام, إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك...).
"Wahai anak muda, aku akan mengajarimu beberapa hal: jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu ... dst"[85].
Juga sabda Rasulullah Shallallahu’alaihiwasallam kepada Umar bin Abu Salamah,
(يا غلام, سم الله وكل بيمينك ...).
"Wahai anak muda, bacalah basmalah (sebelum engkau makan) dan makanlah dengan tangan kanan ..."[86].
Memprioritaskan generasi muda dari tingkatan srata masyarakat yang lain dalam dakwah sangat penting; karena merekalah yang akan 'memegang' bangsa kelak. Jika mereka baik insyaAllah bangsa pun akan baik, namun jika sebaliknya, maka bangsa pun akan demikian keadaannya.
Di sisi lain, ghalibnya mereka yang masih muda lebih mudah untuk didakwahi. Lain halnya dengan mereka yang sudah tua-tua; sebab kebanyakan mereka telah merasa lebih banyak makan asam garam dan kekhawatiran akan dikucilkan oleh masyarakatnya lebih besar.
Dikisahkan bahwa Syaikh Muqbil rahimahullah memulai dakwahnya di negeri Yaman dengan mengajari anak-anak kecil ajaran Islam yang benar dengan penuh keikhlasan, ketekunan dan kesabaran. Alhamdulillah -berkat karunia Allah- saat ini buah manis dakwah beliau telah bisa dirasakan oleh kaum muslimin di berbagai penjuru dunia, melalui perantara para murid-muridnya yang tersebar di seantero dunia.
Berhubung 'dunia' anak muda berbeda dengan 'dunia' orang yang lanjut usia, maka hendaknya seorang da'i menyesuaikan cara dakwahnya dengan kondisi mereka. Mulai dari pemilihan kata-kata, cara penyampaian, hingga pemilihan sarana dakwah, dengan tetap mengindahkan norma-norma syari'at.
Contohnya: ketika kita mendakwahi anak kecil, maka kita perlu kita bumbui dengan permainan-permainan yang mendidik dan dongeng-dongeng nyata dari kisah para nabi maupun ulama salaf yang menarik[87].
-----
Footnote
[85] HR. At-Tirmidzi (no. 2516 hal. 409 -cet Baitul Afkar) dan beliau berkata, "Hadits ini hasan shahih". Adapun Syaikh al-Albani maka beliau menshahihkannya.
[86] HR. Bukhari (no. 5376 hal. 1166 -cet Darussalam) dan Muslim (III/1599 no. 2202 -asy-syamilah).
[87] Alhamdulillah, saat ini telah banyak beredar buku-buku yang berisi kisah-kisah nyata yang menarik untuk anak-anak, yang tentunya akan banyak membantu dakwah kita untuk menarik hati anak-anak. Antara lain: Kisah-Kisah Pilihan untuk Anak Muslim seri 1-5 karya Ummu Usamah 'Aliyyah dkk, Serial Kisah Para Shahabat Nabi Shallallahu’alaihiwasallam karya Dr. Abdurrahman Ra'fat Basya, Serial Kisah Para Nabi karya Abu Muhammad Miftah, dll.
Banyak sekali hadits-hadits Nabi Shallallahu’alaihiwasallam yang menggambarkan betapa besar perhatian beliau dalam mendakwahi generasi muda dan anak-anak kecil. Di antaranya:
Sabda Nabi Shallallahu’alaihiwasallam kepada Ibnu Abbas,
(يا غلام, إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك...).
"Wahai anak muda, aku akan mengajarimu beberapa hal: jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu ... dst"[85].
Juga sabda Rasulullah Shallallahu’alaihiwasallam kepada Umar bin Abu Salamah,
(يا غلام, سم الله وكل بيمينك ...).
"Wahai anak muda, bacalah basmalah (sebelum engkau makan) dan makanlah dengan tangan kanan ..."[86].
Memprioritaskan generasi muda dari tingkatan srata masyarakat yang lain dalam dakwah sangat penting; karena merekalah yang akan 'memegang' bangsa kelak. Jika mereka baik insyaAllah bangsa pun akan baik, namun jika sebaliknya, maka bangsa pun akan demikian keadaannya.
Di sisi lain, ghalibnya mereka yang masih muda lebih mudah untuk didakwahi. Lain halnya dengan mereka yang sudah tua-tua; sebab kebanyakan mereka telah merasa lebih banyak makan asam garam dan kekhawatiran akan dikucilkan oleh masyarakatnya lebih besar.
Dikisahkan bahwa Syaikh Muqbil rahimahullah memulai dakwahnya di negeri Yaman dengan mengajari anak-anak kecil ajaran Islam yang benar dengan penuh keikhlasan, ketekunan dan kesabaran. Alhamdulillah -berkat karunia Allah- saat ini buah manis dakwah beliau telah bisa dirasakan oleh kaum muslimin di berbagai penjuru dunia, melalui perantara para murid-muridnya yang tersebar di seantero dunia.
Berhubung 'dunia' anak muda berbeda dengan 'dunia' orang yang lanjut usia, maka hendaknya seorang da'i menyesuaikan cara dakwahnya dengan kondisi mereka. Mulai dari pemilihan kata-kata, cara penyampaian, hingga pemilihan sarana dakwah, dengan tetap mengindahkan norma-norma syari'at.
Contohnya: ketika kita mendakwahi anak kecil, maka kita perlu kita bumbui dengan permainan-permainan yang mendidik dan dongeng-dongeng nyata dari kisah para nabi maupun ulama salaf yang menarik[87].
-----
Footnote
[85] HR. At-Tirmidzi (no. 2516 hal. 409 -cet Baitul Afkar) dan beliau berkata, "Hadits ini hasan shahih". Adapun Syaikh al-Albani maka beliau menshahihkannya.
[86] HR. Bukhari (no. 5376 hal. 1166 -cet Darussalam) dan Muslim (III/1599 no. 2202 -asy-syamilah).
[87] Alhamdulillah, saat ini telah banyak beredar buku-buku yang berisi kisah-kisah nyata yang menarik untuk anak-anak, yang tentunya akan banyak membantu dakwah kita untuk menarik hati anak-anak. Antara lain: Kisah-Kisah Pilihan untuk Anak Muslim seri 1-5 karya Ummu Usamah 'Aliyyah dkk, Serial Kisah Para Shahabat Nabi Shallallahu’alaihiwasallam karya Dr. Abdurrahman Ra'fat Basya, Serial Kisah Para Nabi karya Abu Muhammad Miftah, dll.
CONTOH KESEMBILAN
CONTOH KESEMBILAN: Menerapkan skala prioritas dalam mengingkari kemungkaran; dimulai dari yang paling berat lalu yang lebih ringan.
Metode bertahap dalam mengingkari kemungkaran dan berdakwah ini disadur dari metode diturunkannya al-Qur’an secara bertahap. Aisyah radhiyallahu’anha bercerita,
(... إنما نزل ]أي: القرآن[ أول ما نزل منه: سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار, حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام, نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء: لا تشربوا الخمر, لقالوا: لا ندَع الخمر أبداً, ولو نزل: لا تزنوا, لقالوا: لا ندع الزنا أبداً ... ).
“… Sesungguhnya (surat al-Qur’an) yang pertama kali diturunkan adalah surat yang menceritakan tentang surga dan neraka. Tatkala orang-orang saat itu telah kembali kepada Islam, baru turun (ayat-ayat yang menjelaskan hukum) halal dan haram. Seandainya (ayat) yang pertama kali turun adalah “Janganlah kalian minum khamr”, niscaya orang-orang akan berkata, “Selamanya kami tidak mau meninggalkan khamr’. Begitu pula jika (ayat) yang pertama kali turun, “Janganlah kalian berzina”, niscaya mereka akan berkata, “Selamanya kami tidak akan meninggalkan zina”...”[88].
Al-Hafizh Ibn Hajar rahimahullah menjelaskan maksud dari perkataan di atas, “Aisyah menerangkan hikmah Allah di balik pengaturan susunan turunnya (ayat-ayat dan surat-surat al-Qur’an). (Surat atau ayat) al-Qur’an yang pertama kali turun adalah dakwah kepada tauhid dan pemberian kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan taat; bahwa mereka akan dimasukkan ke surga, juga ancaman bagi orang kafir; bahwa mereka akan dimasukkan ke neraka. Tatkala umat telah merasa mantap dengan hal itu, baru kemudian (ayat-ayat yang menjelaskan tentang) hukum-hukum (halal dan haram) diturunkan. Oleh karena itu Aisyah berkata, “Seandainya (ayat) yang pertama kali turun adalah "Janganlah kalian minum khamr dst”. Sebab rata-rata orang akan merasa berat untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang telah lama dia gemari”[89].
Syaikh al-‘Allamah Muhammad al-‘Utsaimin rahimahullah menjelaskan, "Sebagaimana yang telah kita ketahui semua, ajaran Islam diturunkan secara bertahap, sedikit demi sedikit[90]. Pada awalnya masyarakat dibiarkan melakukan hal-hal, yang kemudian pada akhirnya diharamkan oleh Islam; ini semua karena pertimbangan maslahat. Contohnya: tahapan pengharaman khamr (minuman keras). Pada awalnya, Allah ta’ala menjelaskan kepada para hamba-Nya bahwa khamr mengandung dosa besar dan beberapa manfaat, hanya saja dosanya lebih besar dari manfaatnya[91]. Maka (sebagian) umat Islam saat itu dibiarkan masih minum khamr. Hingga turun ayat terakhir yang mengharamkan khamr secara total[92].
Seandainya kita telah mempertimbangkan bahwa mendakwahi seorang (pelaku bid’ah atau maksiat) pada saat tertentu atau tempat tertentu tidak ada maslahatnya, dan kita memandang bahwa menunda penyampaian nasehat itu pada waktu atau tempat lain lebih mendatangkan maslahat dan lebih bermanfaat baginya; maka hal ini diperbolehkan[93].
Jadi jika kita hidup di masyarakat yang menjamur di dalamnya praktek-praktek kesyirikan dan bid’ah, maka yang kita prioritaskan untuk diingkari pertama kali -dengan norma-norma yang diajarkan syari’at- adalah kesyirikan-kesyirikan itu dan untuk sementara waktu kita tunda pengingkaran terhadap bid’ah-bid’ah yang ada. Contohnya: dahulukan memperingatkan umat dari praktek perdukunan sebelum memperingatkan mereka dari bid’ahnya perayaan isra’ dan mi’raj.
Begitu pula seandainya kita berada di komunitas yang membudaya di dalamnya maksiat-maksiat dan perbuatan-perbuatan kufur, maka yang kita prioritaskan untuk kita ingkari terlebih dahulu adalah perbuatan-perbuatan kufur, dan untuk sementara waktu kita tunda pengingkaran terhadap maksiat yang ada, jika memang masyarakat belum siap untuk menerima dakwah tersebut. Contoh kongkritnya: prioritaskan untuk memperingatkan umat dari percaya dengan ramalan bintang, sebelum memperingatkan mereka dari haramnya musik, isbal dan cukur jenggot.
Seharusnya kita senantiasa berusaha terlebih dahulu untuk ‘menyelamatkan’ seseorang dari perbuatan syirik dan kufur yang akan mengakibatkan dirinya kekal di neraka, sebelum menyelamatkan dia dari perbuatan bid’ah dan maksiat, yang meskipun mengakibatkan pelakunya masuk neraka, hanya saja masih ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah ta’ala[94].
Ada seorang sahabat penulis yang berlatar belakang organisasi Asy'ariyyah terbesar di Indonesia diberi hidayah oleh Allah untuk mengenal manhaj salaf. Dia ingin sekali saudara-saudarinya juga mengenal dakwah yang haq ini. Maka suatu hari dia mengajak saudarinya untuk mengikuti dauroh (kajian Islam intensif) di suatu pondok pesantren. Namun baru beberapa hari mengikuti dauroh itu, saudarinya sudah mengeluh tidak betah dan ingin segera pulang. Pasalnya dia yang kebetulan saat itu masih pakai jilbab warna warni, tanpa ba bi bu langsung ditegur, “Mba, jangan pakai jilbab warna warni, ini haram!”. Juga dia yang kalau waktu kosong memiliki kebiasaan nyanyi, tiba-tiba ditegur, “Mba, jangan nyanyi! Nyanyi itu haram!”. Akhirnya, belum sempat dia mempelajari dengan mendalam akidah dan cara beribadah yang benar, dia sudah terpental. Dan sampai saat ini dia kapok dan tidak mau lagi menginjakkan kaki di pondok-pondok salaf!
Suatu ketika Syaikh al-‘Allamah Muhammad al-‘Utsaimin rahimahullah pernah ditanya tentang seorang da’i yang melihat kemungkaran, namun dia diam saja; dengan tujuan untuk meluruskannya kelak pada waktu yang tepat. Syaikh menjawab, “Terkadang, menunda pengingkaran terhadap suatu kemungkaran, termasuk metode hikmah dalam berdakwah. Bisa jadi, bukan merupakan sikap yang tepat kita mengingkari pelaku kemungkaran itu pada waktu tersebut, namun kita telah berencana untuk mendakwahinya pada saat yang kira-kira lebih pas baginya. Ini sebenarnya adalah metode yang benar.
Sebagaimana yang telah kita ketahui semua, ajaran Islam diturunkan secara bertahap, sedikit demi sedikit. Pada awalnya masyarakat dibiarkan melakukan hal-hal yang kemudian pada akhirnya diharamkan oleh Islam; ini semua karena pertimbangan maslahat. Contohnya: tahapan pengharaman khamr (minuman keras). Pada awalnya, Allah ta’ala menjelaskan kepada para hamba-Nya bahwa khamr mengandung dosa besar dan beberapa manfaat, hanya saja dosanya lebih besar dari manfaatnya. Maka (sebagian) umat Islam saat itu dibiarkan masih minum khamr. Hingga turun ayat terakhir yang mengharamkan khamr secara total.
Seandainya kita telah mempertimbangkan bahwa mendakwahi seorang (pelaku bid’ah atau maksiat) pada saat tertentu atau tempat tertentu tidak ada maslahatnya, dan kita memandang bahwa menunda penyampaian nasehat itu pada waktu atau tempat lain lebih mendatangkan maslahat dan lebih bermanfaat baginya; maka hal ini diperbolehkan. Namun kalau kita merasa khawatir jika kita tunda dakwah itu, maka akan berdampak tidak bisa lagi kita untuk mendakwahinya pada waktu lain atau khawatir lupa, sehingga maslahat akan tersia-siakan; maka dalam kondisi seperti itu, hendaknya kita bersegera untuk menjelaskan al-haq dan mendakwahi orang tersebut. Ini semua jika kaitannya dengan dakwah terhadap perseorangan.
Namun jika kita ingin bicara di hadapan umum, misalnya kita berada di suatu pertemuan yang dihadiri orang banyak, lalu kita melihat ada sebagian hadirin melakukan suatu perbuatan yang harus kita ingatkan, maka saat itu kita wajib mengingatkan mereka dan hal itu tidak mengapa. Sebab pada kondisi seperti ini, kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan. Seandainya peringatan itu kita tunda, niscaya kelak kita tidak bisa lagi untuk mengumpulkan semua hadirin tersebut”[95].
Mungkin ada yang menyanggah, “Bagaimana mungkin kita melihat kemungkaran lalu, kita diam? Bukankah Rasul shallallahu’alaihiwasallam telah bersabda,
(من رأى منكم منكراً فليغيره بيده).
"Barang siapa yang melihat kemungkaran hendaklah ia mengingkarinya dengan tangannya"[96].
Kalau kita diam saja, sama saja kita meridhai kemungkaran tersebut!”.
Sanggahan tersebut dapat kita jawab dari dua sisi:
Pertama: Hadits di atas masih ada kelanjutannya, yaitu:
(فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه, وذلك أضعف الإيمان).
"Jika ia tidak mampu (untuk mengingkari dengan tangan); hendaknya ia mengingkari dengan lisannya, jika ia tidak mampu (untuk mengingkari dengan lisannya) hendaknya dia mengingkari dengan hatinya. Dan itu (cara pengingkaran dengan hati ini) merupakan tingkat keimanan yang paling lemah”.
Ketika kita diam, bukan kita meridhai kemungkaran tersebut, namun kita mengingkarinya dengan hati. Dan ini masih masuk dalam kerangka sikap yang masih diperbolehkan dalam Islam, meskipun dikatakan di dalam hadits di atas bahwa hal itu termasuk tingkat keimanan yang paling lemah.
Yang tidak diperbolehkan adalah diam dan ridha terhadap kemungkaran tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan Nabi shallallahu’alaihiwasallam dalam hadits lain,
(ومن أنكر سلم, ولكن من رضي وتابع).
"Barang siapa yang mengingkari maka dia selamat. Akan tetapi siapa yang ridha dan mengikuti (kemungkaran tersebut; maka orang seperti inilah yang dikatakan berdosa)”[97].
Oleh karena itu tatkala Syaikh al-‘Allamah Muhammad al-‘Utsaimin rahimahullah ditanya tentang metode sebagian da’i yang terkadang duduk-duduk bersama orang yang mendengarkan musik, namun da’i tadi tidak mengomentari maksiat tersebut; dengan tujuan dia akan menjelaskannya kelak pada saat yang tepat, jika orang tadi telah siap. Apakah metode ini dibenarkan syari’at? Syaikh Utsaimin menjawab, "Orang yang mengingkari kemungkaran ibarat seorang dokter. Jika ada dokter yang mengobati borok dengan cara langsung diiris untuk menghilangkan seluruh borok itu; mungkin akan mengakibatkan luka yang lebih parah. Namun jika dokter tadi mengobati borok tersebut sedikit demi sedikit, dengan penuh kesabaran dia menahan diri mencium bau tidak sedap yang menyeruak dari borok tadi, niscaya pasien tadi akan sembuh.
Tatkala kalian duduk-duduk bersama orang-orang yang berbuat kemungkaran, hal itu bukan karena kalian menyukai kemungkaran tersebut. Namun tujuan kalian duduk-duduk di sana adalah untuk berdakwah. Saya kira setiap orang memiliki perasaan dan akal sehat; jika ada orang alim yang duduk di sampingnya biasanya (dia akan merasa tidak enak) sehingga berhenti dari maksiat yang sedang dia kerjakan. Meskipun terkadang ada juga orang yang keras kepala dan terus saja berbuat maksiat atau malah semakin memperparah maksiat itu. Akan tetapi bersabarlah!
Namun jika kamu telah tahu bahwa orang tersebut sudah tidak lagi bisa diharapkan, maka saat itu jangan duduk-duduk bersama dia, dan kamu wajib untuk berpisah dengannya”[98].
Kedua: Diamnya kita saat itu bukannya tanpa tujuan. Namun kita telah mempertimbangkan bahwa seandainya kemungkaran tersebut diingkari saat itu juga, maka akan menimbulkan fitnah bagi si pelaku yang belum siap untuk menerima al-haq tersebut.
Di akhir pembahasan ini kami ingin mengingatkan para pembaca yang budiman, bahwa semua penjelasan di atas bukan berarti mengajak para da’i untuk turut meramaikan acara-acara bid’ah; ikut maulid, ikut isra’ mi’raj dst, dengan alasan dakwah. Bukan metode yang biasa diterapkan beberapa kelompok pergerakan ini yang kami maksud!.
Bedakan antara dua hal di atas: orang yang melihat kemungkaran lalu dia mengingkari dengan hati, dengan orang yang sengaja ikut hanyut dalam kemungkaran tersebut!. Yang kami maksud adalah hal yang pertama.
-----
Footnote
[88] R. Bukhari (hal. 1087 no. 4993).
[89] Fath al-Bari (IX/51 -cet Darussalam).
[90] Mungkin ada sebagian orang ketika membaca penjelasan ini akan mengaitkannya dengan pemahaman aliran Lembaga Kerasulan (LK) yang membagi kondisi saat ini menjadi periode Makkah dan Madinah. Sekarang kita masih periode Mekkah; sehingga belum wajib shalat, puasa haji serta belum diharamkan minuman yang memabukkan seperti khamar dan lain-lainnya. (Lihat: Aliran dan Paham Sesat di Indonesia karya Hartono Ahmad Jaiz: hal. 44).
Tentunya bukan keyakinan LK di atas yang kami maksud dengan penjelasan ini. Agama Islam telah sempurna dengan wafatnya Rasulullah shallallahu’alaihiwasallam. Maka kita harus meyakini bahwa apa yang diharamkan oleh Islam berarti hukumnya adalah haram dan apa yang diwajibkan berarti hukumnya wajib.
Lalu kenapa kita bertahap dalam menyampaikan ajaran Islam kepada umat? Ketika kita bertahap dalam menyampaikan ajaran Islam kepada umat, bukan berarti kita meyakini bahwa hal-hal yang belum disampaikan kepada mereka hukumnya tidak wajib, tidak! Namun kita bertahap dalam penyampaian karena:
1. Memperhatikan skala prioritas dalam ajaran Islam; mana yang lebih penting itu kita sampaikan sebelum yang penting dst.
2. Memperhatikan bertingkat-tingkatnya keimanan individu-individu umat Islam serta kesiapan mereka dalam menerima ajaran Islam; terkadang ada sebagian -atau bahkan banyak- individu umat Islam yang jika ajaran Islam disampaikan padanya seluruhnya dalam satu waktu; mungkin dia akan murtad karena merasa ajaran Islam amat sangat berat. Orang-orang seperti ini, sementara waktu dibiarkan meninggalkan beberapa kewajiban -dalam keadaan memeluk agama Islam- sambil kita menunggu saat yang tepat untuk menyampaikan kewajiban tersebut; lebih baik daripada dipaksa untuk mengamalkan kewajiban-kewajiban itu namun kemudian berdampak dia murtad dari agama Islam. Wallahua’lam. Lihat: At-Tadarruj fi Da'wah an-Nabi Shallallahu’alaihiwasallam (hal. 127 dst).
[91] QS. Al-Baqarah: 219.
[92] QS. Al-Maidah: 90.
[93] Ash-Shahwah al-Islamiyyah (hal. 200-201).
[94] Kami jadi ingat fenomena yang marak terjadi akhir-akhir ini di bumi pertiwi; berupa tindak perusakan tempat-tempat maksiyat yang dikoordinir oleh beberapa organisasi massa. Mereka berusaha untuk menghancurkan tempat-tempat maksiyat, misalnya pusat-pusat perjudian, tempat mabuk-mabukkan dan lokalisasi. Tapi anehnya mereka 'membiarkan' tempat-tempat kesyirikan seperti kuburan-kuburan para wali yang diagung-agungkan.
Bukankah Ahlus Sunnah wal Jama'ah telah berijma' bahwa judi, minum minuman keras dan berzina adalah dosa-dosa besar yang tidak mengeluarkan pelakunya dari lingkaran agama Islam, selama tidak menghalalkannya?. Sebaliknya, Ahlus Sunnah wal Jama'ah juga telah berijma' bahwa perbuatan syirik merupakan dosa terbesar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari lingkaran agama Islam, dan jika dia meninggal dalam keadaan belum bertaubat; maka dia akan disiksa di neraka selama-lamanya?!.
Mengapa usaha mereka lebih dipusatkan untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa yang masih berpeluang untuk diampuni Allah, lalu 'menutup mata' dari usaha menyelamatkan kaum muslimin dari dosa-dosa yang tidak diampuni oleh Allah?. Bukankah ini merupakan barometer yang terbalik dalam menilai prioritas dakwah?
Bukannya penulis menghasung mereka untuk main hakim sendiri bergerak merangsek menghancurkan tempat-tempat kesyirikan itu dengan tangan mereka sendiri!. Tidak! Karena yang berwenang untuk melakukan pengingkaran kemungkaran dengan tangan dalam hal-hal seperti itu adalah pemerintah kaum muslimin, bukan rakyat biasa. Sebagaimana kisah Ali bin Abi Thalib yang diutus oleh Rasulullah shallallahu’alaihiwasallam untuk meratakan kuburan-kuburan yang terlalu tinggi (HR. Muslim: II/666 no: 969), kisah Abu Hayyaj al-Asady yang diutus oleh khalifah Ali bin Abi Thalib untuk menunaikan tugas serupa. (R. Muslim: II/666 no: 969), dan juga kisah tindakan pemerintah Mekkah yang menghancurkan bangunan yang dibangun di atas kuburan di kota Mekah di zaman Imam Syafi'i (lihat: al-Umm: I/463). Ini semua menunjukkan bahwa tindakan-tindakan model seperti itu adalah hak prerogatif pemerintah kaum muslimin.
Tugas rakyat (para da'i) adalah berdakwah dengan lisan dengan menumbuhkan kesadaran bertauhid dalam diri masyarakat melalui media-media yang disyari'atkan, serta menyampaikan nasehat kepada pemerintah, dengan memperhatikan norma-norma syari'at dalam menasehati, menasehati mereka agar memberangus tempat-tempat kesyirikan; jika pemerintah menerima itulah yang diharapkan, tapi jika nasehat itu tidak diterima maka kita telah menunaikan kewajiban yang diperintahkan atas kita. (Sebagaimana dalam HR. Ahmad: III/403-404 dan Ibnu Abi 'Ashim dalam as-Sunnah: II/737 no: 1130, 1131. Al-Haitsami dalam Majma' az-Zawa'id: V/230 berkata, "Rijalnya (para perawinya) tsiqat (terpercaya) dan sanadnya muttashil (bersambung)". Dan hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani, dalam takhrij beliau atas Kitab as-Sunnah karya Ibnu Abi 'Ashim: II/521-522).
Kalau tugas menghancurkan tempat-tempat maksiyat dan kesyirikan dibuka untuk dilakukan oleh semua orang, yang akan terjadi adalah kekacauan, tindak anarkhis dan huru-hara, sebagaimana yang kerap terjadi di negeri kita.
Maksud kami dengan tulisan ini adalah menghasung para da'i agar lebih menitik beratkan dakwah mereka kepada pengajaran inti ajaran agama Islam yaitu tauhid, serta berusaha mengedepankan upaya untuk menyelamatkan umat dari dosa terbesar yaitu syirik. Tentunya tanpa mengesampingkan memperingatkan umat dari dosa-dosa besar lainnya seperti zina, judi, korupsi, suap dst, tapi masing-masing sesuai dengan porsinya. Jangan malah menitik beratkan upaya pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme dkk, lalu membiarkan perbuatan-perbuatan syirik marak di mana-mana, "yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil". QS. An-Najm: 22. Wallahu a'lam.
[95] Ash-Shahwah al-Islamiyyah (hal. 200-201).
[96] HR. Muslim: (I/69 no. 49).
[97] HR. Muslim: (III/1480 no. 1854). Lihat Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj (XI-XII/445-446).
[98] Liqa’ al-Bab al-Maftuh-2 (II/16 -dalam al-Maktabah asy-Syamilah).
Metode bertahap dalam mengingkari kemungkaran dan berdakwah ini disadur dari metode diturunkannya al-Qur’an secara bertahap. Aisyah radhiyallahu’anha bercerita,
(... إنما نزل ]أي: القرآن[ أول ما نزل منه: سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار, حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام, نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء: لا تشربوا الخمر, لقالوا: لا ندَع الخمر أبداً, ولو نزل: لا تزنوا, لقالوا: لا ندع الزنا أبداً ... ).
“… Sesungguhnya (surat al-Qur’an) yang pertama kali diturunkan adalah surat yang menceritakan tentang surga dan neraka. Tatkala orang-orang saat itu telah kembali kepada Islam, baru turun (ayat-ayat yang menjelaskan hukum) halal dan haram. Seandainya (ayat) yang pertama kali turun adalah “Janganlah kalian minum khamr”, niscaya orang-orang akan berkata, “Selamanya kami tidak mau meninggalkan khamr’. Begitu pula jika (ayat) yang pertama kali turun, “Janganlah kalian berzina”, niscaya mereka akan berkata, “Selamanya kami tidak akan meninggalkan zina”...”[88].
Al-Hafizh Ibn Hajar rahimahullah menjelaskan maksud dari perkataan di atas, “Aisyah menerangkan hikmah Allah di balik pengaturan susunan turunnya (ayat-ayat dan surat-surat al-Qur’an). (Surat atau ayat) al-Qur’an yang pertama kali turun adalah dakwah kepada tauhid dan pemberian kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan taat; bahwa mereka akan dimasukkan ke surga, juga ancaman bagi orang kafir; bahwa mereka akan dimasukkan ke neraka. Tatkala umat telah merasa mantap dengan hal itu, baru kemudian (ayat-ayat yang menjelaskan tentang) hukum-hukum (halal dan haram) diturunkan. Oleh karena itu Aisyah berkata, “Seandainya (ayat) yang pertama kali turun adalah "Janganlah kalian minum khamr dst”. Sebab rata-rata orang akan merasa berat untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang telah lama dia gemari”[89].
Syaikh al-‘Allamah Muhammad al-‘Utsaimin rahimahullah menjelaskan, "Sebagaimana yang telah kita ketahui semua, ajaran Islam diturunkan secara bertahap, sedikit demi sedikit[90]. Pada awalnya masyarakat dibiarkan melakukan hal-hal, yang kemudian pada akhirnya diharamkan oleh Islam; ini semua karena pertimbangan maslahat. Contohnya: tahapan pengharaman khamr (minuman keras). Pada awalnya, Allah ta’ala menjelaskan kepada para hamba-Nya bahwa khamr mengandung dosa besar dan beberapa manfaat, hanya saja dosanya lebih besar dari manfaatnya[91]. Maka (sebagian) umat Islam saat itu dibiarkan masih minum khamr. Hingga turun ayat terakhir yang mengharamkan khamr secara total[92].
Seandainya kita telah mempertimbangkan bahwa mendakwahi seorang (pelaku bid’ah atau maksiat) pada saat tertentu atau tempat tertentu tidak ada maslahatnya, dan kita memandang bahwa menunda penyampaian nasehat itu pada waktu atau tempat lain lebih mendatangkan maslahat dan lebih bermanfaat baginya; maka hal ini diperbolehkan[93].
Jadi jika kita hidup di masyarakat yang menjamur di dalamnya praktek-praktek kesyirikan dan bid’ah, maka yang kita prioritaskan untuk diingkari pertama kali -dengan norma-norma yang diajarkan syari’at- adalah kesyirikan-kesyirikan itu dan untuk sementara waktu kita tunda pengingkaran terhadap bid’ah-bid’ah yang ada. Contohnya: dahulukan memperingatkan umat dari praktek perdukunan sebelum memperingatkan mereka dari bid’ahnya perayaan isra’ dan mi’raj.
Begitu pula seandainya kita berada di komunitas yang membudaya di dalamnya maksiat-maksiat dan perbuatan-perbuatan kufur, maka yang kita prioritaskan untuk kita ingkari terlebih dahulu adalah perbuatan-perbuatan kufur, dan untuk sementara waktu kita tunda pengingkaran terhadap maksiat yang ada, jika memang masyarakat belum siap untuk menerima dakwah tersebut. Contoh kongkritnya: prioritaskan untuk memperingatkan umat dari percaya dengan ramalan bintang, sebelum memperingatkan mereka dari haramnya musik, isbal dan cukur jenggot.
Seharusnya kita senantiasa berusaha terlebih dahulu untuk ‘menyelamatkan’ seseorang dari perbuatan syirik dan kufur yang akan mengakibatkan dirinya kekal di neraka, sebelum menyelamatkan dia dari perbuatan bid’ah dan maksiat, yang meskipun mengakibatkan pelakunya masuk neraka, hanya saja masih ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah ta’ala[94].
Ada seorang sahabat penulis yang berlatar belakang organisasi Asy'ariyyah terbesar di Indonesia diberi hidayah oleh Allah untuk mengenal manhaj salaf. Dia ingin sekali saudara-saudarinya juga mengenal dakwah yang haq ini. Maka suatu hari dia mengajak saudarinya untuk mengikuti dauroh (kajian Islam intensif) di suatu pondok pesantren. Namun baru beberapa hari mengikuti dauroh itu, saudarinya sudah mengeluh tidak betah dan ingin segera pulang. Pasalnya dia yang kebetulan saat itu masih pakai jilbab warna warni, tanpa ba bi bu langsung ditegur, “Mba, jangan pakai jilbab warna warni, ini haram!”. Juga dia yang kalau waktu kosong memiliki kebiasaan nyanyi, tiba-tiba ditegur, “Mba, jangan nyanyi! Nyanyi itu haram!”. Akhirnya, belum sempat dia mempelajari dengan mendalam akidah dan cara beribadah yang benar, dia sudah terpental. Dan sampai saat ini dia kapok dan tidak mau lagi menginjakkan kaki di pondok-pondok salaf!
Suatu ketika Syaikh al-‘Allamah Muhammad al-‘Utsaimin rahimahullah pernah ditanya tentang seorang da’i yang melihat kemungkaran, namun dia diam saja; dengan tujuan untuk meluruskannya kelak pada waktu yang tepat. Syaikh menjawab, “Terkadang, menunda pengingkaran terhadap suatu kemungkaran, termasuk metode hikmah dalam berdakwah. Bisa jadi, bukan merupakan sikap yang tepat kita mengingkari pelaku kemungkaran itu pada waktu tersebut, namun kita telah berencana untuk mendakwahinya pada saat yang kira-kira lebih pas baginya. Ini sebenarnya adalah metode yang benar.
Sebagaimana yang telah kita ketahui semua, ajaran Islam diturunkan secara bertahap, sedikit demi sedikit. Pada awalnya masyarakat dibiarkan melakukan hal-hal yang kemudian pada akhirnya diharamkan oleh Islam; ini semua karena pertimbangan maslahat. Contohnya: tahapan pengharaman khamr (minuman keras). Pada awalnya, Allah ta’ala menjelaskan kepada para hamba-Nya bahwa khamr mengandung dosa besar dan beberapa manfaat, hanya saja dosanya lebih besar dari manfaatnya. Maka (sebagian) umat Islam saat itu dibiarkan masih minum khamr. Hingga turun ayat terakhir yang mengharamkan khamr secara total.
Seandainya kita telah mempertimbangkan bahwa mendakwahi seorang (pelaku bid’ah atau maksiat) pada saat tertentu atau tempat tertentu tidak ada maslahatnya, dan kita memandang bahwa menunda penyampaian nasehat itu pada waktu atau tempat lain lebih mendatangkan maslahat dan lebih bermanfaat baginya; maka hal ini diperbolehkan. Namun kalau kita merasa khawatir jika kita tunda dakwah itu, maka akan berdampak tidak bisa lagi kita untuk mendakwahinya pada waktu lain atau khawatir lupa, sehingga maslahat akan tersia-siakan; maka dalam kondisi seperti itu, hendaknya kita bersegera untuk menjelaskan al-haq dan mendakwahi orang tersebut. Ini semua jika kaitannya dengan dakwah terhadap perseorangan.
Namun jika kita ingin bicara di hadapan umum, misalnya kita berada di suatu pertemuan yang dihadiri orang banyak, lalu kita melihat ada sebagian hadirin melakukan suatu perbuatan yang harus kita ingatkan, maka saat itu kita wajib mengingatkan mereka dan hal itu tidak mengapa. Sebab pada kondisi seperti ini, kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan. Seandainya peringatan itu kita tunda, niscaya kelak kita tidak bisa lagi untuk mengumpulkan semua hadirin tersebut”[95].
Mungkin ada yang menyanggah, “Bagaimana mungkin kita melihat kemungkaran lalu, kita diam? Bukankah Rasul shallallahu’alaihiwasallam telah bersabda,
(من رأى منكم منكراً فليغيره بيده).
"Barang siapa yang melihat kemungkaran hendaklah ia mengingkarinya dengan tangannya"[96].
Kalau kita diam saja, sama saja kita meridhai kemungkaran tersebut!”.
Sanggahan tersebut dapat kita jawab dari dua sisi:
Pertama: Hadits di atas masih ada kelanjutannya, yaitu:
(فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه, وذلك أضعف الإيمان).
"Jika ia tidak mampu (untuk mengingkari dengan tangan); hendaknya ia mengingkari dengan lisannya, jika ia tidak mampu (untuk mengingkari dengan lisannya) hendaknya dia mengingkari dengan hatinya. Dan itu (cara pengingkaran dengan hati ini) merupakan tingkat keimanan yang paling lemah”.
Ketika kita diam, bukan kita meridhai kemungkaran tersebut, namun kita mengingkarinya dengan hati. Dan ini masih masuk dalam kerangka sikap yang masih diperbolehkan dalam Islam, meskipun dikatakan di dalam hadits di atas bahwa hal itu termasuk tingkat keimanan yang paling lemah.
Yang tidak diperbolehkan adalah diam dan ridha terhadap kemungkaran tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan Nabi shallallahu’alaihiwasallam dalam hadits lain,
(ومن أنكر سلم, ولكن من رضي وتابع).
"Barang siapa yang mengingkari maka dia selamat. Akan tetapi siapa yang ridha dan mengikuti (kemungkaran tersebut; maka orang seperti inilah yang dikatakan berdosa)”[97].
Oleh karena itu tatkala Syaikh al-‘Allamah Muhammad al-‘Utsaimin rahimahullah ditanya tentang metode sebagian da’i yang terkadang duduk-duduk bersama orang yang mendengarkan musik, namun da’i tadi tidak mengomentari maksiat tersebut; dengan tujuan dia akan menjelaskannya kelak pada saat yang tepat, jika orang tadi telah siap. Apakah metode ini dibenarkan syari’at? Syaikh Utsaimin menjawab, "Orang yang mengingkari kemungkaran ibarat seorang dokter. Jika ada dokter yang mengobati borok dengan cara langsung diiris untuk menghilangkan seluruh borok itu; mungkin akan mengakibatkan luka yang lebih parah. Namun jika dokter tadi mengobati borok tersebut sedikit demi sedikit, dengan penuh kesabaran dia menahan diri mencium bau tidak sedap yang menyeruak dari borok tadi, niscaya pasien tadi akan sembuh.
Tatkala kalian duduk-duduk bersama orang-orang yang berbuat kemungkaran, hal itu bukan karena kalian menyukai kemungkaran tersebut. Namun tujuan kalian duduk-duduk di sana adalah untuk berdakwah. Saya kira setiap orang memiliki perasaan dan akal sehat; jika ada orang alim yang duduk di sampingnya biasanya (dia akan merasa tidak enak) sehingga berhenti dari maksiat yang sedang dia kerjakan. Meskipun terkadang ada juga orang yang keras kepala dan terus saja berbuat maksiat atau malah semakin memperparah maksiat itu. Akan tetapi bersabarlah!
Namun jika kamu telah tahu bahwa orang tersebut sudah tidak lagi bisa diharapkan, maka saat itu jangan duduk-duduk bersama dia, dan kamu wajib untuk berpisah dengannya”[98].
Kedua: Diamnya kita saat itu bukannya tanpa tujuan. Namun kita telah mempertimbangkan bahwa seandainya kemungkaran tersebut diingkari saat itu juga, maka akan menimbulkan fitnah bagi si pelaku yang belum siap untuk menerima al-haq tersebut.
Di akhir pembahasan ini kami ingin mengingatkan para pembaca yang budiman, bahwa semua penjelasan di atas bukan berarti mengajak para da’i untuk turut meramaikan acara-acara bid’ah; ikut maulid, ikut isra’ mi’raj dst, dengan alasan dakwah. Bukan metode yang biasa diterapkan beberapa kelompok pergerakan ini yang kami maksud!.
Bedakan antara dua hal di atas: orang yang melihat kemungkaran lalu dia mengingkari dengan hati, dengan orang yang sengaja ikut hanyut dalam kemungkaran tersebut!. Yang kami maksud adalah hal yang pertama.
-----
Footnote
[88] R. Bukhari (hal. 1087 no. 4993).
[89] Fath al-Bari (IX/51 -cet Darussalam).
[90] Mungkin ada sebagian orang ketika membaca penjelasan ini akan mengaitkannya dengan pemahaman aliran Lembaga Kerasulan (LK) yang membagi kondisi saat ini menjadi periode Makkah dan Madinah. Sekarang kita masih periode Mekkah; sehingga belum wajib shalat, puasa haji serta belum diharamkan minuman yang memabukkan seperti khamar dan lain-lainnya. (Lihat: Aliran dan Paham Sesat di Indonesia karya Hartono Ahmad Jaiz: hal. 44).
Tentunya bukan keyakinan LK di atas yang kami maksud dengan penjelasan ini. Agama Islam telah sempurna dengan wafatnya Rasulullah shallallahu’alaihiwasallam. Maka kita harus meyakini bahwa apa yang diharamkan oleh Islam berarti hukumnya adalah haram dan apa yang diwajibkan berarti hukumnya wajib.
Lalu kenapa kita bertahap dalam menyampaikan ajaran Islam kepada umat? Ketika kita bertahap dalam menyampaikan ajaran Islam kepada umat, bukan berarti kita meyakini bahwa hal-hal yang belum disampaikan kepada mereka hukumnya tidak wajib, tidak! Namun kita bertahap dalam penyampaian karena:
1. Memperhatikan skala prioritas dalam ajaran Islam; mana yang lebih penting itu kita sampaikan sebelum yang penting dst.
2. Memperhatikan bertingkat-tingkatnya keimanan individu-individu umat Islam serta kesiapan mereka dalam menerima ajaran Islam; terkadang ada sebagian -atau bahkan banyak- individu umat Islam yang jika ajaran Islam disampaikan padanya seluruhnya dalam satu waktu; mungkin dia akan murtad karena merasa ajaran Islam amat sangat berat. Orang-orang seperti ini, sementara waktu dibiarkan meninggalkan beberapa kewajiban -dalam keadaan memeluk agama Islam- sambil kita menunggu saat yang tepat untuk menyampaikan kewajiban tersebut; lebih baik daripada dipaksa untuk mengamalkan kewajiban-kewajiban itu namun kemudian berdampak dia murtad dari agama Islam. Wallahua’lam. Lihat: At-Tadarruj fi Da'wah an-Nabi Shallallahu’alaihiwasallam (hal. 127 dst).
[91] QS. Al-Baqarah: 219.
[92] QS. Al-Maidah: 90.
[93] Ash-Shahwah al-Islamiyyah (hal. 200-201).
[94] Kami jadi ingat fenomena yang marak terjadi akhir-akhir ini di bumi pertiwi; berupa tindak perusakan tempat-tempat maksiyat yang dikoordinir oleh beberapa organisasi massa. Mereka berusaha untuk menghancurkan tempat-tempat maksiyat, misalnya pusat-pusat perjudian, tempat mabuk-mabukkan dan lokalisasi. Tapi anehnya mereka 'membiarkan' tempat-tempat kesyirikan seperti kuburan-kuburan para wali yang diagung-agungkan.
Bukankah Ahlus Sunnah wal Jama'ah telah berijma' bahwa judi, minum minuman keras dan berzina adalah dosa-dosa besar yang tidak mengeluarkan pelakunya dari lingkaran agama Islam, selama tidak menghalalkannya?. Sebaliknya, Ahlus Sunnah wal Jama'ah juga telah berijma' bahwa perbuatan syirik merupakan dosa terbesar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari lingkaran agama Islam, dan jika dia meninggal dalam keadaan belum bertaubat; maka dia akan disiksa di neraka selama-lamanya?!.
Mengapa usaha mereka lebih dipusatkan untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa yang masih berpeluang untuk diampuni Allah, lalu 'menutup mata' dari usaha menyelamatkan kaum muslimin dari dosa-dosa yang tidak diampuni oleh Allah?. Bukankah ini merupakan barometer yang terbalik dalam menilai prioritas dakwah?
Bukannya penulis menghasung mereka untuk main hakim sendiri bergerak merangsek menghancurkan tempat-tempat kesyirikan itu dengan tangan mereka sendiri!. Tidak! Karena yang berwenang untuk melakukan pengingkaran kemungkaran dengan tangan dalam hal-hal seperti itu adalah pemerintah kaum muslimin, bukan rakyat biasa. Sebagaimana kisah Ali bin Abi Thalib yang diutus oleh Rasulullah shallallahu’alaihiwasallam untuk meratakan kuburan-kuburan yang terlalu tinggi (HR. Muslim: II/666 no: 969), kisah Abu Hayyaj al-Asady yang diutus oleh khalifah Ali bin Abi Thalib untuk menunaikan tugas serupa. (R. Muslim: II/666 no: 969), dan juga kisah tindakan pemerintah Mekkah yang menghancurkan bangunan yang dibangun di atas kuburan di kota Mekah di zaman Imam Syafi'i (lihat: al-Umm: I/463). Ini semua menunjukkan bahwa tindakan-tindakan model seperti itu adalah hak prerogatif pemerintah kaum muslimin.
Tugas rakyat (para da'i) adalah berdakwah dengan lisan dengan menumbuhkan kesadaran bertauhid dalam diri masyarakat melalui media-media yang disyari'atkan, serta menyampaikan nasehat kepada pemerintah, dengan memperhatikan norma-norma syari'at dalam menasehati, menasehati mereka agar memberangus tempat-tempat kesyirikan; jika pemerintah menerima itulah yang diharapkan, tapi jika nasehat itu tidak diterima maka kita telah menunaikan kewajiban yang diperintahkan atas kita. (Sebagaimana dalam HR. Ahmad: III/403-404 dan Ibnu Abi 'Ashim dalam as-Sunnah: II/737 no: 1130, 1131. Al-Haitsami dalam Majma' az-Zawa'id: V/230 berkata, "Rijalnya (para perawinya) tsiqat (terpercaya) dan sanadnya muttashil (bersambung)". Dan hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani, dalam takhrij beliau atas Kitab as-Sunnah karya Ibnu Abi 'Ashim: II/521-522).
Kalau tugas menghancurkan tempat-tempat maksiyat dan kesyirikan dibuka untuk dilakukan oleh semua orang, yang akan terjadi adalah kekacauan, tindak anarkhis dan huru-hara, sebagaimana yang kerap terjadi di negeri kita.
Maksud kami dengan tulisan ini adalah menghasung para da'i agar lebih menitik beratkan dakwah mereka kepada pengajaran inti ajaran agama Islam yaitu tauhid, serta berusaha mengedepankan upaya untuk menyelamatkan umat dari dosa terbesar yaitu syirik. Tentunya tanpa mengesampingkan memperingatkan umat dari dosa-dosa besar lainnya seperti zina, judi, korupsi, suap dst, tapi masing-masing sesuai dengan porsinya. Jangan malah menitik beratkan upaya pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme dkk, lalu membiarkan perbuatan-perbuatan syirik marak di mana-mana, "yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil". QS. An-Najm: 22. Wallahu a'lam.
[95] Ash-Shahwah al-Islamiyyah (hal. 200-201).
[96] HR. Muslim: (I/69 no. 49).
[97] HR. Muslim: (III/1480 no. 1854). Lihat Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj (XI-XII/445-446).
[98] Liqa’ al-Bab al-Maftuh-2 (II/16 -dalam al-Maktabah asy-Syamilah).
CONTOH KESEPULUH
CONTOH KESEPULUH: Ketika membantah ahlul bid’ah, seharusnya kita menghiasi bantahan tersebut dengan ilmu dan dalil-dalil, sehingga umat merasa yakin akan benarnya hal yang disampaikan, serta merasa mantap ketika menerimanya.
Jangan sampai kita sekedar jago untuk memvonis sesat (tapi ketika ditanya di mana letak kesesatannya diam seribu bahasa) atau kita memilki hobi untuk memenuhi bantahannya dengan cacian serta makian, namun kosong dari ilmu dan dalil. Ketahuilah bahwa sikap seperti ini justru akan merugikan dakwah salafiyah, karena hal itu hanya akan membuat umat benci dan tidak simpati kepada dakwah salaf.
Allah ta'ala memerintahkan kita untuk berdakwah dengan ilmu dalam firman-Nya,
] قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني[.
Artinya: "Katakanlah: Ini jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku, aku mengajak (kalian) kepada Allah dengan ilmu". QS. Yusuf: 108.
Syaikh Dr. Ibrahim ar-Ruhaily hafizhahullah menjelaskan bahwa di antara etika membantah orang yang menyimpang adalah, "Hendaknya bantahan tersebut dilakukan oleh seorang alim yang telah mumpuni ilmunya; mengetahui secara detail segala sudut pandang dalam materi bantahan, entah yang berkaitan dengan dalil-dalil syari’at yang menjelaskannya serta keterangan para ulama, maupun tingkat kesalahan lawan, serta sumber munculnya syubhat dalam dirinya. Plus mengetahui keterangan-keterangan para ulama yang membantah syubhat tersebut.
Hendaklah orang yang membantah juga memiliki kriteria: kemampuan untuk mengemukakan dalil-dalil yang kuat, tatkala ia menerangkan kebenaran dan mematahkan syubhat. Memiliki ungkapan-ungkapan yang cermat; agar tidak dipahami dari perkataannya kesimpulan yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan.
(Atau bisa juga bantahan itu dilakukan oleh thalibul ‘ilm yang menukil perkataan para ulama, dan dia cermat dalam penukilan, serta memahami apa yang ia nukil)[99].
Jika tidak memenuhi kriteria-kriteria di atas, niscaya yang akan timbul adalah kerusakan yang besar"[100].
Salah satu contoh praktek nyata di zaman ini dari penerapan metode hikmah di atas dalam membantah ahlul bid’ah adalah: apa yang dipraktekkan oleh muhaddits ad-diyar al-yamaniyah di zamannya: Syaikh al-‘Allamah Abdurrahman bin Yahya al-Mu’allimi rahimahullah. Orang yang membaca bantahan-bantahan beliau terhadap ahlul bid’ah -seperti kitab “at-Tankil” yang berisi bantahan terhadap pembawa bendera Jahmiyah abad ini: al-Kautsari, atau kitab “al-Anwar al-Kasyifah” yang berisi bantahan terhadap salah satu tokoh utama penjaja pemikiran orientalisme: Abu Royyah-; niscaya dia akan mendapatkan bantahan-bantahan beliau senantiasa dipenuhi dengan ilmu yang amat dalam, dalil-dalil yang amat kuat, serta sangat jauh dari cacian dan makian. Ditambah semua keistimewaan tersebut beliau sampaikan dengan penuh ketawadhu’an. Maka tidak heran, jika beliau disegani kawan dan lawan. Buahnya: betapa banyak ahlul bid’ah yang mendapatkan hidayah setelah membaca bantahan-bantahan beliau yang memuaskan.
Jadi siapa saja yang berkehendak untuk mengarungi lautan ibadah membantah ahlul bid'ah, maka dia harus siap untuk membantah syubhat-syubhat yang mereka miliki dengan dalil-dalil dari kitab dan sunnah, serta perkataan para ulama salaf. Sehingga dia akan termasuk orang-orang yang membela agama Allah, bukan justru merugikannya, dikarenakan bantahannya yang tidak kuat; sehingga berakibat 'lawan' semakin yakin dengan kesesatannya dan tambah ragu dengan kebenaran ajaran Ahlus Sunnah. Ini semua bukan karena ajaran Ahlus Sunnah yang meragukan, namun karena ulah sebagian oknum Ahlus Sunnah yang telah "memaksakan diri untuk terbang, padahal bulu-bulu sayapnya belum tumbuh", wallahul musta'an!
-----
Footnote
[99] Kalimat yang berada di dalam tanda kurung merupakan tambahan dari kami dan telah kami konsultasikan kepada Syaikh Ibrahim, alhamdulillah beliau menyetujuinya.
[100] Nashihah li asy-Syabab (hal. 7).
Jangan sampai kita sekedar jago untuk memvonis sesat (tapi ketika ditanya di mana letak kesesatannya diam seribu bahasa) atau kita memilki hobi untuk memenuhi bantahannya dengan cacian serta makian, namun kosong dari ilmu dan dalil. Ketahuilah bahwa sikap seperti ini justru akan merugikan dakwah salafiyah, karena hal itu hanya akan membuat umat benci dan tidak simpati kepada dakwah salaf.
Allah ta'ala memerintahkan kita untuk berdakwah dengan ilmu dalam firman-Nya,
] قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني[.
Artinya: "Katakanlah: Ini jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku, aku mengajak (kalian) kepada Allah dengan ilmu". QS. Yusuf: 108.
Syaikh Dr. Ibrahim ar-Ruhaily hafizhahullah menjelaskan bahwa di antara etika membantah orang yang menyimpang adalah, "Hendaknya bantahan tersebut dilakukan oleh seorang alim yang telah mumpuni ilmunya; mengetahui secara detail segala sudut pandang dalam materi bantahan, entah yang berkaitan dengan dalil-dalil syari’at yang menjelaskannya serta keterangan para ulama, maupun tingkat kesalahan lawan, serta sumber munculnya syubhat dalam dirinya. Plus mengetahui keterangan-keterangan para ulama yang membantah syubhat tersebut.
Hendaklah orang yang membantah juga memiliki kriteria: kemampuan untuk mengemukakan dalil-dalil yang kuat, tatkala ia menerangkan kebenaran dan mematahkan syubhat. Memiliki ungkapan-ungkapan yang cermat; agar tidak dipahami dari perkataannya kesimpulan yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan.
(Atau bisa juga bantahan itu dilakukan oleh thalibul ‘ilm yang menukil perkataan para ulama, dan dia cermat dalam penukilan, serta memahami apa yang ia nukil)[99].
Jika tidak memenuhi kriteria-kriteria di atas, niscaya yang akan timbul adalah kerusakan yang besar"[100].
Salah satu contoh praktek nyata di zaman ini dari penerapan metode hikmah di atas dalam membantah ahlul bid’ah adalah: apa yang dipraktekkan oleh muhaddits ad-diyar al-yamaniyah di zamannya: Syaikh al-‘Allamah Abdurrahman bin Yahya al-Mu’allimi rahimahullah. Orang yang membaca bantahan-bantahan beliau terhadap ahlul bid’ah -seperti kitab “at-Tankil” yang berisi bantahan terhadap pembawa bendera Jahmiyah abad ini: al-Kautsari, atau kitab “al-Anwar al-Kasyifah” yang berisi bantahan terhadap salah satu tokoh utama penjaja pemikiran orientalisme: Abu Royyah-; niscaya dia akan mendapatkan bantahan-bantahan beliau senantiasa dipenuhi dengan ilmu yang amat dalam, dalil-dalil yang amat kuat, serta sangat jauh dari cacian dan makian. Ditambah semua keistimewaan tersebut beliau sampaikan dengan penuh ketawadhu’an. Maka tidak heran, jika beliau disegani kawan dan lawan. Buahnya: betapa banyak ahlul bid’ah yang mendapatkan hidayah setelah membaca bantahan-bantahan beliau yang memuaskan.
Jadi siapa saja yang berkehendak untuk mengarungi lautan ibadah membantah ahlul bid'ah, maka dia harus siap untuk membantah syubhat-syubhat yang mereka miliki dengan dalil-dalil dari kitab dan sunnah, serta perkataan para ulama salaf. Sehingga dia akan termasuk orang-orang yang membela agama Allah, bukan justru merugikannya, dikarenakan bantahannya yang tidak kuat; sehingga berakibat 'lawan' semakin yakin dengan kesesatannya dan tambah ragu dengan kebenaran ajaran Ahlus Sunnah. Ini semua bukan karena ajaran Ahlus Sunnah yang meragukan, namun karena ulah sebagian oknum Ahlus Sunnah yang telah "memaksakan diri untuk terbang, padahal bulu-bulu sayapnya belum tumbuh", wallahul musta'an!
-----
Footnote
[99] Kalimat yang berada di dalam tanda kurung merupakan tambahan dari kami dan telah kami konsultasikan kepada Syaikh Ibrahim, alhamdulillah beliau menyetujuinya.
[100] Nashihah li asy-Syabab (hal. 7).
CONTOH KESEBELAS
CONTOH KESEBELAS: Di saat mentahdzir (mengingatkan umat dari penyimpangan) ahlul bid’ah -baik mereka berbentuk kelompok maupun individu- seorang da’i Ahlus Sunnah tidak harus menyebutkan secara terang-terangan nama-nama kelompok dan individu tersebut, jika memang hal tersebut tidak dibutuhkan.
Mentahdzir dari ahlul bid'ah merupakan salah satu ibadah yang amat mulia di dalam agama Islam. Banyak sekali dalil-dalil -baik dari al-Qur’an maupun sunnah- yang menunjukkan disyari’atkannya metode tahdzir, jika dilakukan sesuai dengan norma-norma yang digariskan syari’at.
Di antaranya adalah firman Allah ta’ala,
]وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ[
Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”. QS. Ali-Imran: 104.
Ayat di atas menjelaskan disyariatkannya amar ma’ruf nahi munkar, dan para ulama telah menerangkan bahwa penerapan metode tahdzir adalah merupakan salah satu bentuk amar ma’ruf dan nahi munkar.
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, “Kalaupun dia (ahlul bid’ah tersebut) tidak berhak atau tidak memungkinkan untuk dihukum, maka kita harus menjelaskan bid’ahnya tersebut dan mentahdzir (umat) darinya, sesungguhnya hal ini termasuk bentuk amar ma’ruf dan nahi munkar yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya Shallallahu’alaihiwasallam”[101].
Senada dengan keterangan Ibnu Taimiyah di atas; penjelasan yang dibawakan oleh Imam al-Haramain al-Juwaini rahimahullah[102].
Di antara dalil disyari’atkannya tahdzir adalah sabda Nabi Shallallahu’alaihiwasallam,
(يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله؛ ينفون عنه تحريف الغالين, وانتحال المبطلين, وتأويل الجاهلين).
“Agama ini diemban di setiap zaman oleh para ulama; yang (bertugas untuk) menyisihkan penyimpangan golongan yang ekstrim, jalan orang-orang batil dan ta’wilnya orang-orang yang jahil”[103].
Dan masih banyak dalil lain yang menunjukkan disyari’atkannya penerapan metode tahdzir[104]. Bahkan nabi kita Shallallahu’alaihiwasallam pun mempraktekkan metode tahdzir dalam kehidupannya; entah itu tahdzir terhadap individu maupun tahdzir dari suatu kelompok tertentu.
Di antara contoh praktek beliau Shallallahu’alaihiwasallam dalam mentahdzir suatu individu; tatkala beliau mentahdzir umat dari ‘nenek moyang’ Khawarij: Abdullah bin Dzi al-Khuwaishirah. Beliau Shallallahu’alaihiwasallam bersabda,
(إنه سيخرج من ضئضئي هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية).
“Akan muncul dari keturunan orang ini; generasi yang rajin membaca al-Qur’an, namun bacaan mereka tidak melewati kerongkongan (tidak memahami apa yang mereka baca). Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah yang menancap di tubuh buruan, lalu melesat keluar dari tubuhnya“[105].
Adapun praktek beliau Shallallahu’alaihiwasallam dalam mentahdzir dari suatu kelompok yang menyimpang, antara lain: tatkala beliau Shallallahu’alaihiwasallam mentahdzir umat dari sekte Khawarij dalam sabdanya Shallallahu’alaihiwasallam,
(شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء وخير قتيل من قتلوا كلاب أهل النار).
“Mereka adalah seburuk-buruk orang yang dibunuh di muka bumi. Dan sebaik-baik orang yang terbunuh adalah orang yang terbunuh ketika memerangi anjing-anjing penghuni neraka“[106].
Para ulama Ahlus Sunnah pun dari dulu sampai sekarang telah menerapkan metode tahdzir ini, baik tahdzir terhadap individu maupun terhadap kelompok tertentu
Para ulama telah menjelaskan bahwa mentahdzir dari ahlul bid’ah dan membantah mereka merupakan amalan yang disyari’atkan di dalam agama Islam dalam rangka menjaga kemurnian agama Islam dan menasehati umat agar tidak terjerumus ke dalam kubang bid’ah tersebut.
Di antara keterangan tersebut, perkataan Imam al-Qarafi rahimahullah, “Hendaknya kerusakan dan aib ahlul bid’ah serta pengarang buku-buku yang menyesatkan dibeberkan kepada umat, dan dijelaskan bahwa mereka tidak berada di atas kebenaran; agar orang-orang yang lemah berhati-hati darinya sehingga tidak terjerumus ke dalamnya. Dan semampu mungkin umat dijauhkan dari kerusakan-kerusakan tersebut”[107].
Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya, “Mana yang lebih engkau sukai; seseorang berpuasa, shalat dan i’tikaf atau mengkritik ahlul bid’ah? Beliau menjawab, “Kalau dia shalat, puasa dan i’tikaf maka manfaatnya hanya untuk dia sendiri, namun jika dia mengkritik ahlul bid’ah maka manfaatnya bagi kaum muslimin, dan ini lebih afdhal!”[108].
Dan masih banyak perkataan-perkataan ulama Ahlus Sunnah yang senada[109].
Berikut kami bawakan beberapa contoh praktek nyata para ulama kita dari dulu sampai sekarang, dalam menerapkan metode tahdzir -baik tahdzir terhadap individu maupun terhadap kelompok tertentu-; supaya kita paham betul bahwa metode tahdzir adalah metode yang ashil ('orisinil') dan bukan metode bid’ah yang diada-adakan di zaman ini[110]:
1. Abdullah bin Umar radhiyallahu’anhuma (wafat thn 73 H) ketika beliau mentahdzir dari sekte Qadariyah dengan perkataannya, “Beritahukanlah kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka, dan mereka berlepas diri dariku”[111].
2. Imam al-Bukhari rahimahullah (w. 256 H) ketika beliau mentahdzir dari sekte Jahmiyyah dalam kitabnya: “Khalq Af’al al-‘Ibad wa ar-Radd ‘ala al-Jahmiyyah wa Ashab at-Ta’thil”[112].
3. Imam ad-Darimi rahimahullah (w. 280 H) ketika beliau mentahdzir dari Bisyr al-Mirrisi dalam kitabnya: “Naqdh Utsman ad-Darimi ‘ala al-Mirrisi al-Jahmi al-‘Anid fima Iftara ‘ala Allah fi at-Tauhid”[113].
4. Imam ad-Daruquthni rahimahullah (w. 385 H) ketika beliau mentahdzir dari ‘Amr bin ‘Ubaid -gembong sekte Mu’tazilah di zamannya- dalam kitabnya “Akhbar ‘Amr bin ‘Ubaid bin Bab al-Mu’tazili”[114].
5. Imam Abu Nu’aim al-Ashbahani rahimahullah (w. 430 H) ketika beliau mentahdzir dari sekte Rafidhah dalam kitabnya “Al-Imamah wa ar-Radd ‘ala ar-Rafidhah”[115].
6. Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah (w. 505 H) ketika beliau mentahdzir dari sekte al-Bathiniyyah dalam kitabnya “Fadha’ih al-Bathiniyyah”[116].
7. Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah (w. 620 H) ketika beliau mentahdzir dari Abu al-Wafa’ Ibnu ‘Aqil -salah seorang tokoh sekte Mu’tazilah- dalam kitabnya “Tahrim an-Nazhar fi Kutub al-Kalam”[117].
8. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah (w. 728 H) ketika beliau mentahdzir dari al-Bakri -salah seorang tokoh sufi di zaman itu- dalam kitabnya “Al-Istighatsah fi ar-Radd ‘ala al-Bakri”[118].
9. Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah (w. 751 H) ketika beliau mentahdzir dari sekte Jahmiyyah dan golongan Mu’athilah dalam kitabnya “Ash-Shawa’iq al-Mursalah ‘ala al-Jahmiyyah wa al-Mu’athilah”[119].
10. Ibnu Hajar al-Haitami rahimahullah (w. 974 H) ketika beliau mentahdzir dari sekte Rafidhah dan orang-orang Zindiq dalam kitabnya “Ash-Shawa’iq al-Muhriqah ‘ala Ahl ar-Rafdh wa adh-Dhalal wa az-Zandaqah”[120].
11. Imam Abdul Lathif bin Abdurrahman Alu Syaikh rahimahullah (w. 1292 H) ketika beliau mentahdzir dari Dawud bin Jarjis -salah satu pembesar sufi di zaman itu- dalam kitabnya “Minhaj at-Ta’sis wa at-Taqdis fi Kasyf Syubuhat Dawud bin Jarjis”[121].
12. Imam Abu al-Ma’ali al-Alusi rahimahullah (w. 1342 H) ketika beliau mentahdzir dari an-Nabhani -salah satu tokoh sufi di zaman itu- dalam kitabnya “Ghayah al-Amani fi ar-Radd ‘ala an-Nabhani”[122].
13. Al-‘Allamah Abdurrahman as-Sa’di rahimahullah (w. 1376 H) ketika beliau mentahdzir dari Abdullah al-Qashimi -salah satu tokoh yang terpengaruh pemikiran sekuler di zaman itu- dalam kitabnya “Tanzih ad-Din wa Hamalatih wa Rijalih mimma Iftarah al-Qashimi fi Aghlalih”[123].
14. Al-‘Allamah al-Albani rahimahullah (w. 1420 H) ketika beliau mentahdzir dari Hasan Abdul Mannan dalam kitabnya “An-Nashihah bi at-Tahdzir min Takhrib Ibn Abdil Mannan li Kutub al-A’immah ar-Rajiihah wa Tadh’ifih li Mi’aat al-Ahadits ash-Shahihah”[124].
15. Al-‘Allamah Abdul Muhsin al-‘Abbad hafizhahullah ketika beliau mentahdzir dari ar-Rifa’i dan al-Buthi -tokoh-tokoh yang membenci dakwah salafiyah- dalam kitabnya “Ar-Radd ‘ala ar-Rifa’i wa al-Buthi fi Kadzibihima ‘ala Ahl as-Sunnah wa Da’watihima Ila al-Bida’ wa adh-Dhalal”[125],
16. Syaikh Dr. Bakr Abu Zaid hafizhahullah ketika beliau mentahdzir dari Muhammad bin Ali ash-Shabuni -salah satu tokoh sekte Asy’ariyyah abad ini- dalam kitabnya “At-Tahdzir min Mukhtasharat Muhammad bi Ali ash-Shabuni fi at-Tafsir”[126].
17. Syaikh Dr. Rabi’ bin Hadi al-Madkhali hafizhahullah ketika beliau mentahdzir dari Sayyid Quthb -salah satu tokoh pergerakan Islam yang mengusung pemikiran takfiri- dalam kitabnya “Matha’in Sayyid Quthb fi Ashab Rasulillah Shallallahu’alaihiwasallam”[127] dan kitab-kitab beliau lainnya.
18. Syaikh Prof. Dr. Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin al-Badr hafizhahullah ketika beliau mentahdzir dari Hasan as-Segaf -salah satu tokoh sekte Jahmiyah abad ini- dalam kitabnya “Al-Qaul as-Sadid fi ar-Radd ‘ala Man Ankara Taqsim at-Tauhid”[128].
19. Syaikh Salim bin ‘Ied al-Hilali hafizhahullah ketika beliau mentahdzir dari kelompok-kelompok pergerakan abad ini yang memiliki penyimpangan-penyimpangan, dalam kitabnya “Al-Jama’at al-Islamiyyah fi Dhau’i al-Kitab wa as-Sunnah bi Fahm Salaf al-Ummah”[129].
Dan masih ada puluhan bahkan mungkin ratusan contoh praktek nyata para ulama kita -tempo dulu maupun di zaman ini- dalam menerapkan metode tahdzir ini.
Hanya saja perlu diketahui bahwasanya tatkala agama Islam telah menjelaskan disyari’atkannya penerapan metode tahdzir, agama kita pun juga telah menjelaskan norma-normanya[130].
Di antara norma yang perlu diperhatikan ketika menerapkan metode ini: membedakan antara kondisi di mana kita dituntut untuk terang-terangan mengidentifikasikan individu atau kelompok yang ditahdzir, dengan kondisi di saat kita dituntut untuk tidak terang-terangan mengidentifikasikannya.
Di antara faktor yang mendorong seorang da’i untuk terang-terangan menyebutkan nama kelompok atau individu yang ditahdzir, adalah jika umat yang dihadapinya tidak mengerti dan tidak paham apa yang dimaksud, jika sang da’i tidak terang-terangan.
Namun jika umat sudah mengerti siapa sebenarnya yang dimaksud dalam bantahan tersebut, dan justru jika metode ini diterapkan akan berakibat umat tidak menerima al-haq yang disampaikan, maka saat itu cukup bagi seorang da’i untuk menyampaikan kesalahan kelompok atau individu yang dimaksud beserta bantahannya, tanpa terang-terangan menyebutkan nama kelompok atau individu tersebut.
Dan memang hukum asal cara mentahdzir adalah dengan tidak menyebutkan terang-terangan nama yang ditahdzir. Sebagaimana praktek Rasulullah Shallallahu’alaihiwasallam ketika akan menjelaskan kesalahan sebagian orang, dengan perkataannya,
(ما بال أقوام قالوا كذا وكذا).
“Mengapa ada sebagian orang berkata ini dan itu”[131].
Ini adalah hukum asalnya, namun jika dibutuhkan untuk terang-terangan menyebutkan nama yang ditahdzir, itupun tidak mengapa, sebagaimana praktek Rasulullah Shallallahu’alaihiwasallam,
(أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه, وأما معاوية فصعلوك لا مال له).
“Adapun Abu Jahm maka dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya (suka memukul) sedangkan Mu'awiyah maka dia adalah orang yang miskin yang tidak punya harta"[132].
Syaikh al-‘Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menjelaskan, “Hendaknya yang menjadi tujuan adalah menjelaskan kebenaran dan kebathilan tanpa perlu menyebutkan nama orang yang dinukil kecuali dalam kondisi darurat yang mengharuskan penyebutan orang tersebut”[133].
Syaikh al-‘Allamah Muhammad al-‘Utsaimin rahimahullah memberikan keterangan serupa, “Jadi, menyebutkan individu hukumnya boleh dalam kondisi darurat, jika tidak, maka yang penting adalah membantah perkataan yang batil (bukan pelakunya -pen)”[134].
Syaikh Abdul Malik Ramadhani hafizhahullah dalam salah satu ceramahnya menegaskan bahwa metode inilah yang diterapkan oleh Rasulullah shallallahu’alaihiwasallam di dalam kebanyakan sikapnya, “Petunjuk Nabi shallallahu’alaihiwasallam dalam hal itu [yakni dalam hal menjelaskan kesalahan orang lain] beliau mencukupkan diri dengan penjelasan secara global tanpa merincikan (pelakunya), ini hukum asalnya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Shahih Muslim bahwa Rasulullah shallallahu’alaihiwasallam bersabda, “Mengapa sebagian orang melakukan ini dan itu”. Ini (sudah cukup) jika tujuan telah tercapai, namun jika (tujuan untuk memperingati seseorang tidak tercapai dengan peringatan secara global) maka perlu disebutkan secara terang-terangan siapa pelakunya. Inilah hukum asal yang selalu (diterapkan).
Engkau pun juga bisa mengatakan, “Mengapa fulan atau sebagian orang berkata ini dan itu”, tanpa menyebutkan namanya. Jika orang yang bersalah itu telah paham dan kembali (kepada al-haq), maka ini sudah cukup bagimu dan bersyukurlah kepada Allah ‘azza wa jalla”[135].
Syaikh Dr. Rabi’ bin Hadi al-Madkhali hafizhahullah menasehatkan, “Termasuk pula (metode dalam berdakwah yang esensial) adalah janganlah engkau mencerca atau mencaci-maki firqah mereka. (Hal ini berdasarkan firman Allah), “Dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan”. QS. Al-An’am: 108”[136].
Beliau menambahkan, “Wahai para penuntut ilmu, kalian jangan menyangka bahwa termasuk dari bentuk kesempurnaan manhaj yang benar ini adalah keharusan mencaci-maki tokoh-tokoh mereka. Tidak! Sesungguhnya Allah subhanah berfirman (yang artinya): “Dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan”. QS. Al-An’am: 108. Kalau kalian mencerca syaikh fulan atau kau katakan, “Fulan sesat!” Atau julukan-julukan lainnya atau kalian katakan, “Tarekat fulan sesat!” justru yang demikian ini hanya akan membuat umat lari menjauh darimu. Akhirnya kalian berdosa lantaran kalian telah menjauhkan manusia dari dakwah yang benar, kalian munaffirun (membuat orang lari)”. Padahal Rasulullah shallallahu’alaihiwasallam tatkala mengutus Mu’adz dan Abu Musa radhiyallahu’anhuma ke Yaman beliau berpesan kepada keduanya: “Hendaklah kalian mempermudah dan jangan mempersulit, gembirakan mereka dan jangan kalian membuat mereka lari”[137].
Beliau kembali menegaskan, “Jika ada yang datang berdakwah kepada mereka kemudian membodoh-bodohkan pengikut aliran Tijani, boleh jadi mereka akan menyembelihnya, tidak cukup hanya diusir! Tapi jika kalian datang berdakwah kepada mereka dengan hikmah dan lemah lembut -baarakallahu fik- maka Allah akan memberikan manfaat kepada mereka dengan sebab perangai tersebut”[138].
Berikut akan kami bawakan contoh nyata keberhasilan dakwah seorang da'i dan ulama, tatkala beliau tidak memulai dakwahnya dengan mengidentifikasi secara terang-terangan 'lawan-lawannya'.
Syaikh Rabi' al-Madkhali hafizahullah mengisahkan pengalaman dakwah beliau di negeri Sudan, "Sesampainya saya di bandara Sudan, saya disambut oleh para pemuda Jama'ah Anshar as-Sunah. Mereka memberi masukan, "Ya Syaikh, bolehkah kami menyampaikan beberapa saran kepada anda?".
"Silahkan" kataku.
Mereka berkata, "Wahai Syaikh, silahkan anda berceramah sekehendak anda dengan (mengutip) firman Allah dan sabda Nabi-Nya Shallallahu’alaihiwasallam, tidak mengapa engkau sebutkan berbagai jenis bid'ah dan kesesatannya, baik kaitannya dengan doa kepada selain Allah, menyembelih, nadzar atau istighatsah kepada selain-Nya. Namun sebaiknya engkau tidak menyinggung tarekat tertentu atau syaikh fulan! Jangan sampai engkau mengatakan bahwa tarekat Tijaniyah atau Bathiniyyah sesat. Jangan pula engkau mencaci tokoh-tokohnya. Cukup engkau sebutkan perkara-perkara akidah (secara umum), niscaya engkau akan dapati mereka menerima al-haq yang engkau sampaikan".
Saya katakan padanya, "Baiklah".
Akhirnya saya ikuti anjuran mereka. Ternyata saya menyaksikan sambutan yang sangat besar dari kaum muslimin terhadap dakwah ini…
Demi Allah, tidaklah aku masuk suatu masjid melainkan aku melihat wajah mereka berseri-seri, sehingga aku tidak bisa keluar dari kerumunan masa yang berebut berjabat tangan serta mendoakan kebaikan untukku.
Ternyata para pentolan tarekat sufi melihat cara dakwah yang saya tempuh sebagai suatu ancaman yang berbahaya. Akhirnya tokoh-tokoh tersebut berkumpul dan berunding untuk merumuskan bantahan-bantahan terhadap ceramah saya.
Mereka memintaku untuk memberikan ceramah di suatu lapangan. Maka saya penuhi permintaan mereka. Akupun ceramah hingga selesai. Giliran pembesar mereka bangkit (setelahku) dan mengomentari ceramahku tadi. Mulailah orang ini mengutarakan pendapatnya tentang bolehnya beristighatsah kepada selain Allah, bertawassul dengan mayit, mengingkari sifat-sifat Allah dan ucapan-ucapan batil lainnya. Mereka kemas semua ucapan batil itu dengan takwil-takwil yang menyimpang dan keji.
Usai dia berbicara -namun ia tidak menyertakan dasar dalilnya, yang ada hanyalah hadits-hadits dha'if dan palsu atau nukilan dari ucapan Socrattes- maka aku katakana kepada hadirin, "Apakah hadirin sekalian telah mendengar ceramahku? Bukankah yang aku sampaikan adalah semata-mata firman Allah dan sabda Rasulullah Shallallahu’alaihiwasallam? Tapi lihatlah orang ini! Yang ia sebutkan adalah hadits-hadits palsu belaka. Padahal al-Qur'an lebih berhak untuk disebutkan di sini. Pernahkah kalian mendengar firman Allah yang membolehkan istighatsah kepada selain-Nya?! Bolehnya tawassul (dengan mayit)?! Atau pernahkah kalian mendengar ucapan para imam terkemuka dalam hal ini semua?! Tidak sama sekali tidak! Kalian hanya mendengar hadits-hadits palsu dan dha'if atau tak lebih dari sekedar omongan segelintir manusia yang sangat masyhur di antara kalian sebagai pengusung khurafat?!"
Tidak lama kemudian orang tersebut bangkit sambil memaki-maki. Namun aku hanya tersenyum dan sama sekali tidak menanggapi caciannya. Aku hanya mengucapkan, "Jazakallahu khairan, barakallah fik, barakallah fik, jazakallah khairan!" Tidak lebih dari itu.
Bubarlah acara tersebut. Maka demi Allah, ternyata keesokan harinya banyak orang yang memperbincangkan kejadian ini baik di masjid-masjid maupun di pasar-pasar. Mereka berkomentar bahwa orang-orang Sufi telah kalah…
Kemudian kami melanjutkan perjalanan ke Kasala, masih wilayah Sudan. MasyaAllah, dakwah Ahlus Sunnah mendapatkan kemudahan dan tanggapan bagus. Kami diberi kesempatan untuk berkhutbah dan kita bersyukur dengan keadaan ini …
Kemudian kami pergi ke kota Ghatharif, sebuah kota kecil di sana. Kami menyempatkan diri untuk mengelilingi masjid-masjid di kota itu. Ada sebagian dari Jama'ah Anshar as-Sunnah mengatakan, "Ya Syaikh, hanya tinggal satu masjid di kota ini yang belum terjamah dakwah kita, sebab masjid ini adalah basis tarekat tijaniyah, lantaran itu kita belum bisa masuk ke sana".
"Lho kenapa?".
"Sebab mereka sangat fanatik".
"Baiklah, kalau demikian kita pergi ke sana. Kita akan minta izin; kalau diizinkan untuk bicara, maka kita bicara. Tapi kalau mereka melarang, maka udzur kita di sisi Allah. Dan ingat! Jangan kita memaksakan diri untuk berbicara".
Sampailah kami di masjid mereka. Kami shalat bersama mereka sebagai makmum. Usai shalat, kami ucapkan salam kepada sang imam. Aku berkata, "Bolehkah aku berbicara di hadapan saudara-saudara kami di sini?"
"Silahkan" jawab sang imam.
Mulailah aku berceramah, aku ajak mereka untuk mentauhidkan Allah dan melaksanakan sunnah dan perkara-perkara lain dari agama. Sesekali aku menyinggung beberapa kesalahan serta berbagai kesesatan yang ada. Di sela-sela itu aku mengutip hadits Aisyah yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim yang berbunyi, "Ada tiga hal, barang siapa yang mengatakan tiga perkara ini maka ia telah melakukan kedustaan besar di sisi Allah: (1) Barang siapa yang meyakini bahwa Nabi Muhammad Shallallahu’alaihiwasallam telah melihat Rabb-nya (di dunia) maka ia telah melakukan kedustaan yang besar di sisi Allah. (2) Barang siapa meyakini bahwa Nabi Muhammad Shallallahu’alaihiwasallam mengetahui kejadian-kejadian yang akan datang maka ia telah melakukan kedustaan yang besar di sisi Allah. Dan saya sebutkan pula berbagai dalil yang mendukung hadits ini. (3) Barang siapa meyakini bahwa Nabi Muhammad Shallallahu’alaihiwasallam tidak menyampaikan risalah dari Allah secara sempurna maka ia telah melakukan kedustaan yang besar di sisi Allah".
Lalu sang imam berkomentar (ia terlihat gusar dan gelisah), "Demi Allah, sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu’alaihiwasallam telah melihat Allah di dunia dengan kedua mata kepalanya".
Namun aku hanya menyambut komentar si imam dengan ucapan, "Jazakallah khairan. (Tentunya kita tahu) bahwa Aisyah sebagai istri Rasul Shallallahu’alaihiwasallam tentu lebih tahu akan keadaan beliau. Kalaulah Rasulullah Shallallahu’alaihiwasallam benar-benar telah melihat Rabb-nya di dunia tentu Aisyah akan mengabarkannya, tapi kenapa ia tidak mengabarkannya?".
Lalu ia mendesakku dengan pertanyaan bertubi-tubi.
Aku katakan, "Ya akhi, tunggulah sebentar, beri kesempatan kepadaku agar aku selesaikan jawabanku satu persatu. Setelah itu silahkan engkau lanjutkan dengan pertanyaan lain sekehendakmu. Apa yang aku ketahui akan aku jawab, dan apa yang tidak aku ketahui akan aku katakan padamu, "Wallahu a'lam".
Lalu aku abaikan orang itu dan aku teruskan ceramahku. Aku tidak tahu apakah ia tetap duduk di situ atau pergi meninggalkan majelis, karena akupun sengaja tidak menoleh kepadanya.
Terdengar olehku bisikan orang, "Benar juga ucapan orang ini" Terdengar juga dari selain dia kata-kata lain, "Demi Allah, lelaki ini tidak menyampaikan melainkan firman Allah dan sabda Rasul-Nya Shallallahu’alaihiwasallam".
Adzan Isya dikumandangkan, maka berakhirlah acara tersebut, lantas jama'ah masjid melaksanakan shalat Isya. Tiba-tiba mereka mendorongku untuk menjadi imam Isya". Aku katakan, "Sama sekali aku tidak mau menjadi imam".
Mereka malah menjawab, "Demi Allah, shalatlah mengimami kami, demi Allah, shalatlah mengimami kami". Akhirnya aku katakan, "Baiklah kalau begitu".
Akhirnya akupun shalat mengimami mereka. Usai shalat aku menunggu sejenak, kemudian aku pulang bersama para pemuda Anshar as-Sunnah.
Aku bertanya kepada mereka, "Kemana sang imam pergi?". Mereka menjawab, "Telah diusir!". "Lho siapa yang mengusirnya?" tanyaku lagi. "Demi Allah, jama'ahnya yang mengusir dia!" tandas mereka.
Itulah yang terjadi wahai saudara-saudaraku. Singkatnya jika ada yang datang berdakwah kepada mereka kemudian membodoh-bodohkan pengikut aliran tijani, boleh jadi mereka akan mememenggal lehermu, tidak cukup hanya diusir! Tapi jika kalian datang berdakwah kepada mereka dengan hikmah dan lemah lembut, maka Allah akan memberikan manfaat kepada mereka dengan lantaran perangai tersebut.
Hendaknya engkau berbekal dengan ilmu yang bermanfaat, argumentasi yang kokoh, senantiasa memprioritaskan hikmah di dalam dakwah kalian. Wajib atas kalian untuk berhias diri dengan akhlak mulia yang telah dianjurkan Allah dalam kitab-Nya dan Rasulullah Shallallahu’alaihiwasallam. Sesungguhnya itu merupakan (salah satu) sarana (terbesar) untuk mendapatkan pertolongan dan kesuksesan".[139]
Sekali lagi kami ingin mengingatkan, bahwa kami di sini tidak sedang mengingkari disyariatkannya pengidentifikasian terang-terangan nama individu atau kelompok yang ditahdzir jika memang diperlukan; karena memang ada dalil yang menunjukkan akan hal itu.
Masalah ini perlu kami tekankan kembali; karena akhir-akhir ini ada sebagian orang yang sama sekali melarang hal tersebut di atas, berlandaskan sebagian dalil yang menunjukkan akan hal itu, sayangnya ia tidak tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa di sana juga ada dalil shahih dan praktek para ulama salaf yang menunjukkan bolehnya pengidentifikasian nama individu atau kelompok yang ditahdzir, jika memang diperlukan. Wallahua'lam.
Mentahdzir dari ahlul bid'ah merupakan salah satu ibadah yang amat mulia di dalam agama Islam. Banyak sekali dalil-dalil -baik dari al-Qur’an maupun sunnah- yang menunjukkan disyari’atkannya metode tahdzir, jika dilakukan sesuai dengan norma-norma yang digariskan syari’at.
Di antaranya adalah firman Allah ta’ala,
]وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ[
Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”. QS. Ali-Imran: 104.
Ayat di atas menjelaskan disyariatkannya amar ma’ruf nahi munkar, dan para ulama telah menerangkan bahwa penerapan metode tahdzir adalah merupakan salah satu bentuk amar ma’ruf dan nahi munkar.
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, “Kalaupun dia (ahlul bid’ah tersebut) tidak berhak atau tidak memungkinkan untuk dihukum, maka kita harus menjelaskan bid’ahnya tersebut dan mentahdzir (umat) darinya, sesungguhnya hal ini termasuk bentuk amar ma’ruf dan nahi munkar yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya Shallallahu’alaihiwasallam”[101].
Senada dengan keterangan Ibnu Taimiyah di atas; penjelasan yang dibawakan oleh Imam al-Haramain al-Juwaini rahimahullah[102].
Di antara dalil disyari’atkannya tahdzir adalah sabda Nabi Shallallahu’alaihiwasallam,
(يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله؛ ينفون عنه تحريف الغالين, وانتحال المبطلين, وتأويل الجاهلين).
“Agama ini diemban di setiap zaman oleh para ulama; yang (bertugas untuk) menyisihkan penyimpangan golongan yang ekstrim, jalan orang-orang batil dan ta’wilnya orang-orang yang jahil”[103].
Dan masih banyak dalil lain yang menunjukkan disyari’atkannya penerapan metode tahdzir[104]. Bahkan nabi kita Shallallahu’alaihiwasallam pun mempraktekkan metode tahdzir dalam kehidupannya; entah itu tahdzir terhadap individu maupun tahdzir dari suatu kelompok tertentu.
Di antara contoh praktek beliau Shallallahu’alaihiwasallam dalam mentahdzir suatu individu; tatkala beliau mentahdzir umat dari ‘nenek moyang’ Khawarij: Abdullah bin Dzi al-Khuwaishirah. Beliau Shallallahu’alaihiwasallam bersabda,
(إنه سيخرج من ضئضئي هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية).
“Akan muncul dari keturunan orang ini; generasi yang rajin membaca al-Qur’an, namun bacaan mereka tidak melewati kerongkongan (tidak memahami apa yang mereka baca). Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah yang menancap di tubuh buruan, lalu melesat keluar dari tubuhnya“[105].
Adapun praktek beliau Shallallahu’alaihiwasallam dalam mentahdzir dari suatu kelompok yang menyimpang, antara lain: tatkala beliau Shallallahu’alaihiwasallam mentahdzir umat dari sekte Khawarij dalam sabdanya Shallallahu’alaihiwasallam,
(شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء وخير قتيل من قتلوا كلاب أهل النار).
“Mereka adalah seburuk-buruk orang yang dibunuh di muka bumi. Dan sebaik-baik orang yang terbunuh adalah orang yang terbunuh ketika memerangi anjing-anjing penghuni neraka“[106].
Para ulama Ahlus Sunnah pun dari dulu sampai sekarang telah menerapkan metode tahdzir ini, baik tahdzir terhadap individu maupun terhadap kelompok tertentu
Para ulama telah menjelaskan bahwa mentahdzir dari ahlul bid’ah dan membantah mereka merupakan amalan yang disyari’atkan di dalam agama Islam dalam rangka menjaga kemurnian agama Islam dan menasehati umat agar tidak terjerumus ke dalam kubang bid’ah tersebut.
Di antara keterangan tersebut, perkataan Imam al-Qarafi rahimahullah, “Hendaknya kerusakan dan aib ahlul bid’ah serta pengarang buku-buku yang menyesatkan dibeberkan kepada umat, dan dijelaskan bahwa mereka tidak berada di atas kebenaran; agar orang-orang yang lemah berhati-hati darinya sehingga tidak terjerumus ke dalamnya. Dan semampu mungkin umat dijauhkan dari kerusakan-kerusakan tersebut”[107].
Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya, “Mana yang lebih engkau sukai; seseorang berpuasa, shalat dan i’tikaf atau mengkritik ahlul bid’ah? Beliau menjawab, “Kalau dia shalat, puasa dan i’tikaf maka manfaatnya hanya untuk dia sendiri, namun jika dia mengkritik ahlul bid’ah maka manfaatnya bagi kaum muslimin, dan ini lebih afdhal!”[108].
Dan masih banyak perkataan-perkataan ulama Ahlus Sunnah yang senada[109].
Berikut kami bawakan beberapa contoh praktek nyata para ulama kita dari dulu sampai sekarang, dalam menerapkan metode tahdzir -baik tahdzir terhadap individu maupun terhadap kelompok tertentu-; supaya kita paham betul bahwa metode tahdzir adalah metode yang ashil ('orisinil') dan bukan metode bid’ah yang diada-adakan di zaman ini[110]:
1. Abdullah bin Umar radhiyallahu’anhuma (wafat thn 73 H) ketika beliau mentahdzir dari sekte Qadariyah dengan perkataannya, “Beritahukanlah kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka, dan mereka berlepas diri dariku”[111].
2. Imam al-Bukhari rahimahullah (w. 256 H) ketika beliau mentahdzir dari sekte Jahmiyyah dalam kitabnya: “Khalq Af’al al-‘Ibad wa ar-Radd ‘ala al-Jahmiyyah wa Ashab at-Ta’thil”[112].
3. Imam ad-Darimi rahimahullah (w. 280 H) ketika beliau mentahdzir dari Bisyr al-Mirrisi dalam kitabnya: “Naqdh Utsman ad-Darimi ‘ala al-Mirrisi al-Jahmi al-‘Anid fima Iftara ‘ala Allah fi at-Tauhid”[113].
4. Imam ad-Daruquthni rahimahullah (w. 385 H) ketika beliau mentahdzir dari ‘Amr bin ‘Ubaid -gembong sekte Mu’tazilah di zamannya- dalam kitabnya “Akhbar ‘Amr bin ‘Ubaid bin Bab al-Mu’tazili”[114].
5. Imam Abu Nu’aim al-Ashbahani rahimahullah (w. 430 H) ketika beliau mentahdzir dari sekte Rafidhah dalam kitabnya “Al-Imamah wa ar-Radd ‘ala ar-Rafidhah”[115].
6. Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah (w. 505 H) ketika beliau mentahdzir dari sekte al-Bathiniyyah dalam kitabnya “Fadha’ih al-Bathiniyyah”[116].
7. Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah (w. 620 H) ketika beliau mentahdzir dari Abu al-Wafa’ Ibnu ‘Aqil -salah seorang tokoh sekte Mu’tazilah- dalam kitabnya “Tahrim an-Nazhar fi Kutub al-Kalam”[117].
8. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah (w. 728 H) ketika beliau mentahdzir dari al-Bakri -salah seorang tokoh sufi di zaman itu- dalam kitabnya “Al-Istighatsah fi ar-Radd ‘ala al-Bakri”[118].
9. Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah (w. 751 H) ketika beliau mentahdzir dari sekte Jahmiyyah dan golongan Mu’athilah dalam kitabnya “Ash-Shawa’iq al-Mursalah ‘ala al-Jahmiyyah wa al-Mu’athilah”[119].
10. Ibnu Hajar al-Haitami rahimahullah (w. 974 H) ketika beliau mentahdzir dari sekte Rafidhah dan orang-orang Zindiq dalam kitabnya “Ash-Shawa’iq al-Muhriqah ‘ala Ahl ar-Rafdh wa adh-Dhalal wa az-Zandaqah”[120].
11. Imam Abdul Lathif bin Abdurrahman Alu Syaikh rahimahullah (w. 1292 H) ketika beliau mentahdzir dari Dawud bin Jarjis -salah satu pembesar sufi di zaman itu- dalam kitabnya “Minhaj at-Ta’sis wa at-Taqdis fi Kasyf Syubuhat Dawud bin Jarjis”[121].
12. Imam Abu al-Ma’ali al-Alusi rahimahullah (w. 1342 H) ketika beliau mentahdzir dari an-Nabhani -salah satu tokoh sufi di zaman itu- dalam kitabnya “Ghayah al-Amani fi ar-Radd ‘ala an-Nabhani”[122].
13. Al-‘Allamah Abdurrahman as-Sa’di rahimahullah (w. 1376 H) ketika beliau mentahdzir dari Abdullah al-Qashimi -salah satu tokoh yang terpengaruh pemikiran sekuler di zaman itu- dalam kitabnya “Tanzih ad-Din wa Hamalatih wa Rijalih mimma Iftarah al-Qashimi fi Aghlalih”[123].
14. Al-‘Allamah al-Albani rahimahullah (w. 1420 H) ketika beliau mentahdzir dari Hasan Abdul Mannan dalam kitabnya “An-Nashihah bi at-Tahdzir min Takhrib Ibn Abdil Mannan li Kutub al-A’immah ar-Rajiihah wa Tadh’ifih li Mi’aat al-Ahadits ash-Shahihah”[124].
15. Al-‘Allamah Abdul Muhsin al-‘Abbad hafizhahullah ketika beliau mentahdzir dari ar-Rifa’i dan al-Buthi -tokoh-tokoh yang membenci dakwah salafiyah- dalam kitabnya “Ar-Radd ‘ala ar-Rifa’i wa al-Buthi fi Kadzibihima ‘ala Ahl as-Sunnah wa Da’watihima Ila al-Bida’ wa adh-Dhalal”[125],
16. Syaikh Dr. Bakr Abu Zaid hafizhahullah ketika beliau mentahdzir dari Muhammad bin Ali ash-Shabuni -salah satu tokoh sekte Asy’ariyyah abad ini- dalam kitabnya “At-Tahdzir min Mukhtasharat Muhammad bi Ali ash-Shabuni fi at-Tafsir”[126].
17. Syaikh Dr. Rabi’ bin Hadi al-Madkhali hafizhahullah ketika beliau mentahdzir dari Sayyid Quthb -salah satu tokoh pergerakan Islam yang mengusung pemikiran takfiri- dalam kitabnya “Matha’in Sayyid Quthb fi Ashab Rasulillah Shallallahu’alaihiwasallam”[127] dan kitab-kitab beliau lainnya.
18. Syaikh Prof. Dr. Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin al-Badr hafizhahullah ketika beliau mentahdzir dari Hasan as-Segaf -salah satu tokoh sekte Jahmiyah abad ini- dalam kitabnya “Al-Qaul as-Sadid fi ar-Radd ‘ala Man Ankara Taqsim at-Tauhid”[128].
19. Syaikh Salim bin ‘Ied al-Hilali hafizhahullah ketika beliau mentahdzir dari kelompok-kelompok pergerakan abad ini yang memiliki penyimpangan-penyimpangan, dalam kitabnya “Al-Jama’at al-Islamiyyah fi Dhau’i al-Kitab wa as-Sunnah bi Fahm Salaf al-Ummah”[129].
Dan masih ada puluhan bahkan mungkin ratusan contoh praktek nyata para ulama kita -tempo dulu maupun di zaman ini- dalam menerapkan metode tahdzir ini.
Hanya saja perlu diketahui bahwasanya tatkala agama Islam telah menjelaskan disyari’atkannya penerapan metode tahdzir, agama kita pun juga telah menjelaskan norma-normanya[130].
Di antara norma yang perlu diperhatikan ketika menerapkan metode ini: membedakan antara kondisi di mana kita dituntut untuk terang-terangan mengidentifikasikan individu atau kelompok yang ditahdzir, dengan kondisi di saat kita dituntut untuk tidak terang-terangan mengidentifikasikannya.
Di antara faktor yang mendorong seorang da’i untuk terang-terangan menyebutkan nama kelompok atau individu yang ditahdzir, adalah jika umat yang dihadapinya tidak mengerti dan tidak paham apa yang dimaksud, jika sang da’i tidak terang-terangan.
Namun jika umat sudah mengerti siapa sebenarnya yang dimaksud dalam bantahan tersebut, dan justru jika metode ini diterapkan akan berakibat umat tidak menerima al-haq yang disampaikan, maka saat itu cukup bagi seorang da’i untuk menyampaikan kesalahan kelompok atau individu yang dimaksud beserta bantahannya, tanpa terang-terangan menyebutkan nama kelompok atau individu tersebut.
Dan memang hukum asal cara mentahdzir adalah dengan tidak menyebutkan terang-terangan nama yang ditahdzir. Sebagaimana praktek Rasulullah Shallallahu’alaihiwasallam ketika akan menjelaskan kesalahan sebagian orang, dengan perkataannya,
(ما بال أقوام قالوا كذا وكذا).
“Mengapa ada sebagian orang berkata ini dan itu”[131].
Ini adalah hukum asalnya, namun jika dibutuhkan untuk terang-terangan menyebutkan nama yang ditahdzir, itupun tidak mengapa, sebagaimana praktek Rasulullah Shallallahu’alaihiwasallam,
(أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه, وأما معاوية فصعلوك لا مال له).
“Adapun Abu Jahm maka dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya (suka memukul) sedangkan Mu'awiyah maka dia adalah orang yang miskin yang tidak punya harta"[132].
Syaikh al-‘Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menjelaskan, “Hendaknya yang menjadi tujuan adalah menjelaskan kebenaran dan kebathilan tanpa perlu menyebutkan nama orang yang dinukil kecuali dalam kondisi darurat yang mengharuskan penyebutan orang tersebut”[133].
Syaikh al-‘Allamah Muhammad al-‘Utsaimin rahimahullah memberikan keterangan serupa, “Jadi, menyebutkan individu hukumnya boleh dalam kondisi darurat, jika tidak, maka yang penting adalah membantah perkataan yang batil (bukan pelakunya -pen)”[134].
Syaikh Abdul Malik Ramadhani hafizhahullah dalam salah satu ceramahnya menegaskan bahwa metode inilah yang diterapkan oleh Rasulullah shallallahu’alaihiwasallam di dalam kebanyakan sikapnya, “Petunjuk Nabi shallallahu’alaihiwasallam dalam hal itu [yakni dalam hal menjelaskan kesalahan orang lain] beliau mencukupkan diri dengan penjelasan secara global tanpa merincikan (pelakunya), ini hukum asalnya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Shahih Muslim bahwa Rasulullah shallallahu’alaihiwasallam bersabda, “Mengapa sebagian orang melakukan ini dan itu”. Ini (sudah cukup) jika tujuan telah tercapai, namun jika (tujuan untuk memperingati seseorang tidak tercapai dengan peringatan secara global) maka perlu disebutkan secara terang-terangan siapa pelakunya. Inilah hukum asal yang selalu (diterapkan).
Engkau pun juga bisa mengatakan, “Mengapa fulan atau sebagian orang berkata ini dan itu”, tanpa menyebutkan namanya. Jika orang yang bersalah itu telah paham dan kembali (kepada al-haq), maka ini sudah cukup bagimu dan bersyukurlah kepada Allah ‘azza wa jalla”[135].
Syaikh Dr. Rabi’ bin Hadi al-Madkhali hafizhahullah menasehatkan, “Termasuk pula (metode dalam berdakwah yang esensial) adalah janganlah engkau mencerca atau mencaci-maki firqah mereka. (Hal ini berdasarkan firman Allah), “Dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan”. QS. Al-An’am: 108”[136].
Beliau menambahkan, “Wahai para penuntut ilmu, kalian jangan menyangka bahwa termasuk dari bentuk kesempurnaan manhaj yang benar ini adalah keharusan mencaci-maki tokoh-tokoh mereka. Tidak! Sesungguhnya Allah subhanah berfirman (yang artinya): “Dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan”. QS. Al-An’am: 108. Kalau kalian mencerca syaikh fulan atau kau katakan, “Fulan sesat!” Atau julukan-julukan lainnya atau kalian katakan, “Tarekat fulan sesat!” justru yang demikian ini hanya akan membuat umat lari menjauh darimu. Akhirnya kalian berdosa lantaran kalian telah menjauhkan manusia dari dakwah yang benar, kalian munaffirun (membuat orang lari)”. Padahal Rasulullah shallallahu’alaihiwasallam tatkala mengutus Mu’adz dan Abu Musa radhiyallahu’anhuma ke Yaman beliau berpesan kepada keduanya: “Hendaklah kalian mempermudah dan jangan mempersulit, gembirakan mereka dan jangan kalian membuat mereka lari”[137].
Beliau kembali menegaskan, “Jika ada yang datang berdakwah kepada mereka kemudian membodoh-bodohkan pengikut aliran Tijani, boleh jadi mereka akan menyembelihnya, tidak cukup hanya diusir! Tapi jika kalian datang berdakwah kepada mereka dengan hikmah dan lemah lembut -baarakallahu fik- maka Allah akan memberikan manfaat kepada mereka dengan sebab perangai tersebut”[138].
Berikut akan kami bawakan contoh nyata keberhasilan dakwah seorang da'i dan ulama, tatkala beliau tidak memulai dakwahnya dengan mengidentifikasi secara terang-terangan 'lawan-lawannya'.
Syaikh Rabi' al-Madkhali hafizahullah mengisahkan pengalaman dakwah beliau di negeri Sudan, "Sesampainya saya di bandara Sudan, saya disambut oleh para pemuda Jama'ah Anshar as-Sunah. Mereka memberi masukan, "Ya Syaikh, bolehkah kami menyampaikan beberapa saran kepada anda?".
"Silahkan" kataku.
Mereka berkata, "Wahai Syaikh, silahkan anda berceramah sekehendak anda dengan (mengutip) firman Allah dan sabda Nabi-Nya Shallallahu’alaihiwasallam, tidak mengapa engkau sebutkan berbagai jenis bid'ah dan kesesatannya, baik kaitannya dengan doa kepada selain Allah, menyembelih, nadzar atau istighatsah kepada selain-Nya. Namun sebaiknya engkau tidak menyinggung tarekat tertentu atau syaikh fulan! Jangan sampai engkau mengatakan bahwa tarekat Tijaniyah atau Bathiniyyah sesat. Jangan pula engkau mencaci tokoh-tokohnya. Cukup engkau sebutkan perkara-perkara akidah (secara umum), niscaya engkau akan dapati mereka menerima al-haq yang engkau sampaikan".
Saya katakan padanya, "Baiklah".
Akhirnya saya ikuti anjuran mereka. Ternyata saya menyaksikan sambutan yang sangat besar dari kaum muslimin terhadap dakwah ini…
Demi Allah, tidaklah aku masuk suatu masjid melainkan aku melihat wajah mereka berseri-seri, sehingga aku tidak bisa keluar dari kerumunan masa yang berebut berjabat tangan serta mendoakan kebaikan untukku.
Ternyata para pentolan tarekat sufi melihat cara dakwah yang saya tempuh sebagai suatu ancaman yang berbahaya. Akhirnya tokoh-tokoh tersebut berkumpul dan berunding untuk merumuskan bantahan-bantahan terhadap ceramah saya.
Mereka memintaku untuk memberikan ceramah di suatu lapangan. Maka saya penuhi permintaan mereka. Akupun ceramah hingga selesai. Giliran pembesar mereka bangkit (setelahku) dan mengomentari ceramahku tadi. Mulailah orang ini mengutarakan pendapatnya tentang bolehnya beristighatsah kepada selain Allah, bertawassul dengan mayit, mengingkari sifat-sifat Allah dan ucapan-ucapan batil lainnya. Mereka kemas semua ucapan batil itu dengan takwil-takwil yang menyimpang dan keji.
Usai dia berbicara -namun ia tidak menyertakan dasar dalilnya, yang ada hanyalah hadits-hadits dha'if dan palsu atau nukilan dari ucapan Socrattes- maka aku katakana kepada hadirin, "Apakah hadirin sekalian telah mendengar ceramahku? Bukankah yang aku sampaikan adalah semata-mata firman Allah dan sabda Rasulullah Shallallahu’alaihiwasallam? Tapi lihatlah orang ini! Yang ia sebutkan adalah hadits-hadits palsu belaka. Padahal al-Qur'an lebih berhak untuk disebutkan di sini. Pernahkah kalian mendengar firman Allah yang membolehkan istighatsah kepada selain-Nya?! Bolehnya tawassul (dengan mayit)?! Atau pernahkah kalian mendengar ucapan para imam terkemuka dalam hal ini semua?! Tidak sama sekali tidak! Kalian hanya mendengar hadits-hadits palsu dan dha'if atau tak lebih dari sekedar omongan segelintir manusia yang sangat masyhur di antara kalian sebagai pengusung khurafat?!"
Tidak lama kemudian orang tersebut bangkit sambil memaki-maki. Namun aku hanya tersenyum dan sama sekali tidak menanggapi caciannya. Aku hanya mengucapkan, "Jazakallahu khairan, barakallah fik, barakallah fik, jazakallah khairan!" Tidak lebih dari itu.
Bubarlah acara tersebut. Maka demi Allah, ternyata keesokan harinya banyak orang yang memperbincangkan kejadian ini baik di masjid-masjid maupun di pasar-pasar. Mereka berkomentar bahwa orang-orang Sufi telah kalah…
Kemudian kami melanjutkan perjalanan ke Kasala, masih wilayah Sudan. MasyaAllah, dakwah Ahlus Sunnah mendapatkan kemudahan dan tanggapan bagus. Kami diberi kesempatan untuk berkhutbah dan kita bersyukur dengan keadaan ini …
Kemudian kami pergi ke kota Ghatharif, sebuah kota kecil di sana. Kami menyempatkan diri untuk mengelilingi masjid-masjid di kota itu. Ada sebagian dari Jama'ah Anshar as-Sunnah mengatakan, "Ya Syaikh, hanya tinggal satu masjid di kota ini yang belum terjamah dakwah kita, sebab masjid ini adalah basis tarekat tijaniyah, lantaran itu kita belum bisa masuk ke sana".
"Lho kenapa?".
"Sebab mereka sangat fanatik".
"Baiklah, kalau demikian kita pergi ke sana. Kita akan minta izin; kalau diizinkan untuk bicara, maka kita bicara. Tapi kalau mereka melarang, maka udzur kita di sisi Allah. Dan ingat! Jangan kita memaksakan diri untuk berbicara".
Sampailah kami di masjid mereka. Kami shalat bersama mereka sebagai makmum. Usai shalat, kami ucapkan salam kepada sang imam. Aku berkata, "Bolehkah aku berbicara di hadapan saudara-saudara kami di sini?"
"Silahkan" jawab sang imam.
Mulailah aku berceramah, aku ajak mereka untuk mentauhidkan Allah dan melaksanakan sunnah dan perkara-perkara lain dari agama. Sesekali aku menyinggung beberapa kesalahan serta berbagai kesesatan yang ada. Di sela-sela itu aku mengutip hadits Aisyah yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim yang berbunyi, "Ada tiga hal, barang siapa yang mengatakan tiga perkara ini maka ia telah melakukan kedustaan besar di sisi Allah: (1) Barang siapa yang meyakini bahwa Nabi Muhammad Shallallahu’alaihiwasallam telah melihat Rabb-nya (di dunia) maka ia telah melakukan kedustaan yang besar di sisi Allah. (2) Barang siapa meyakini bahwa Nabi Muhammad Shallallahu’alaihiwasallam mengetahui kejadian-kejadian yang akan datang maka ia telah melakukan kedustaan yang besar di sisi Allah. Dan saya sebutkan pula berbagai dalil yang mendukung hadits ini. (3) Barang siapa meyakini bahwa Nabi Muhammad Shallallahu’alaihiwasallam tidak menyampaikan risalah dari Allah secara sempurna maka ia telah melakukan kedustaan yang besar di sisi Allah".
Lalu sang imam berkomentar (ia terlihat gusar dan gelisah), "Demi Allah, sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu’alaihiwasallam telah melihat Allah di dunia dengan kedua mata kepalanya".
Namun aku hanya menyambut komentar si imam dengan ucapan, "Jazakallah khairan. (Tentunya kita tahu) bahwa Aisyah sebagai istri Rasul Shallallahu’alaihiwasallam tentu lebih tahu akan keadaan beliau. Kalaulah Rasulullah Shallallahu’alaihiwasallam benar-benar telah melihat Rabb-nya di dunia tentu Aisyah akan mengabarkannya, tapi kenapa ia tidak mengabarkannya?".
Lalu ia mendesakku dengan pertanyaan bertubi-tubi.
Aku katakan, "Ya akhi, tunggulah sebentar, beri kesempatan kepadaku agar aku selesaikan jawabanku satu persatu. Setelah itu silahkan engkau lanjutkan dengan pertanyaan lain sekehendakmu. Apa yang aku ketahui akan aku jawab, dan apa yang tidak aku ketahui akan aku katakan padamu, "Wallahu a'lam".
Lalu aku abaikan orang itu dan aku teruskan ceramahku. Aku tidak tahu apakah ia tetap duduk di situ atau pergi meninggalkan majelis, karena akupun sengaja tidak menoleh kepadanya.
Terdengar olehku bisikan orang, "Benar juga ucapan orang ini" Terdengar juga dari selain dia kata-kata lain, "Demi Allah, lelaki ini tidak menyampaikan melainkan firman Allah dan sabda Rasul-Nya Shallallahu’alaihiwasallam".
Adzan Isya dikumandangkan, maka berakhirlah acara tersebut, lantas jama'ah masjid melaksanakan shalat Isya. Tiba-tiba mereka mendorongku untuk menjadi imam Isya". Aku katakan, "Sama sekali aku tidak mau menjadi imam".
Mereka malah menjawab, "Demi Allah, shalatlah mengimami kami, demi Allah, shalatlah mengimami kami". Akhirnya aku katakan, "Baiklah kalau begitu".
Akhirnya akupun shalat mengimami mereka. Usai shalat aku menunggu sejenak, kemudian aku pulang bersama para pemuda Anshar as-Sunnah.
Aku bertanya kepada mereka, "Kemana sang imam pergi?". Mereka menjawab, "Telah diusir!". "Lho siapa yang mengusirnya?" tanyaku lagi. "Demi Allah, jama'ahnya yang mengusir dia!" tandas mereka.
Itulah yang terjadi wahai saudara-saudaraku. Singkatnya jika ada yang datang berdakwah kepada mereka kemudian membodoh-bodohkan pengikut aliran tijani, boleh jadi mereka akan mememenggal lehermu, tidak cukup hanya diusir! Tapi jika kalian datang berdakwah kepada mereka dengan hikmah dan lemah lembut, maka Allah akan memberikan manfaat kepada mereka dengan lantaran perangai tersebut.
Hendaknya engkau berbekal dengan ilmu yang bermanfaat, argumentasi yang kokoh, senantiasa memprioritaskan hikmah di dalam dakwah kalian. Wajib atas kalian untuk berhias diri dengan akhlak mulia yang telah dianjurkan Allah dalam kitab-Nya dan Rasulullah Shallallahu’alaihiwasallam. Sesungguhnya itu merupakan (salah satu) sarana (terbesar) untuk mendapatkan pertolongan dan kesuksesan".[139]
Sekali lagi kami ingin mengingatkan, bahwa kami di sini tidak sedang mengingkari disyariatkannya pengidentifikasian terang-terangan nama individu atau kelompok yang ditahdzir jika memang diperlukan; karena memang ada dalil yang menunjukkan akan hal itu.
Masalah ini perlu kami tekankan kembali; karena akhir-akhir ini ada sebagian orang yang sama sekali melarang hal tersebut di atas, berlandaskan sebagian dalil yang menunjukkan akan hal itu, sayangnya ia tidak tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa di sana juga ada dalil shahih dan praktek para ulama salaf yang menunjukkan bolehnya pengidentifikasian nama individu atau kelompok yang ditahdzir, jika memang diperlukan. Wallahua'lam.
CONTOH KESEBELAS
CONTOH KESEBELAS: Di saat mentahdzir (mengingatkan umat dari penyimpangan) ahlul bid’ah -baik mereka berbentuk kelompok maupun individu- seorang da’i Ahlus Sunnah tidak harus menyebutkan secara terang-terangan nama-nama kelompok dan individu tersebut, jika memang hal tersebut tidak dibutuhkan.
Mentahdzir dari ahlul bid'ah merupakan salah satu ibadah yang amat mulia di dalam agama Islam. Banyak sekali dalil-dalil -baik dari al-Qur’an maupun sunnah- yang menunjukkan disyari’atkannya metode tahdzir, jika dilakukan sesuai dengan norma-norma yang digariskan syari’at.
Di antaranya adalah firman Allah ta’ala,
]وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ[
Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”. QS. Ali-Imran: 104.
Ayat di atas menjelaskan disyariatkannya amar ma’ruf nahi munkar, dan para ulama telah menerangkan bahwa penerapan metode tahdzir adalah merupakan salah satu bentuk amar ma’ruf dan nahi munkar.
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, “Kalaupun dia (ahlul bid’ah tersebut) tidak berhak atau tidak memungkinkan untuk dihukum, maka kita harus menjelaskan bid’ahnya tersebut dan mentahdzir (umat) darinya, sesungguhnya hal ini termasuk bentuk amar ma’ruf dan nahi munkar yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya Shallallahu’alaihiwasallam”[101].
Senada dengan keterangan Ibnu Taimiyah di atas; penjelasan yang dibawakan oleh Imam al-Haramain al-Juwaini rahimahullah[102].
Di antara dalil disyari’atkannya tahdzir adalah sabda Nabi Shallallahu’alaihiwasallam,
(يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله؛ ينفون عنه تحريف الغالين, وانتحال المبطلين, وتأويل الجاهلين).
“Agama ini diemban di setiap zaman oleh para ulama; yang (bertugas untuk) menyisihkan penyimpangan golongan yang ekstrim, jalan orang-orang batil dan ta’wilnya orang-orang yang jahil”[103].
Dan masih banyak dalil lain yang menunjukkan disyari’atkannya penerapan metode tahdzir[104]. Bahkan nabi kita Shallallahu’alaihiwasallam pun mempraktekkan metode tahdzir dalam kehidupannya; entah itu tahdzir terhadap individu maupun tahdzir dari suatu kelompok tertentu.
Di antara contoh praktek beliau Shallallahu’alaihiwasallam dalam mentahdzir suatu individu; tatkala beliau mentahdzir umat dari ‘nenek moyang’ Khawarij: Abdullah bin Dzi al-Khuwaishirah. Beliau Shallallahu’alaihiwasallam bersabda,
(إنه سيخرج من ضئضئي هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية).
“Akan muncul dari keturunan orang ini; generasi yang rajin membaca al-Qur’an, namun bacaan mereka tidak melewati kerongkongan (tidak memahami apa yang mereka baca). Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah yang menancap di tubuh buruan, lalu melesat keluar dari tubuhnya“[105].
Adapun praktek beliau Shallallahu’alaihiwasallam dalam mentahdzir dari suatu kelompok yang menyimpang, antara lain: tatkala beliau Shallallahu’alaihiwasallam mentahdzir umat dari sekte Khawarij dalam sabdanya Shallallahu’alaihiwasallam,
(شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء وخير قتيل من قتلوا كلاب أهل النار).
“Mereka adalah seburuk-buruk orang yang dibunuh di muka bumi. Dan sebaik-baik orang yang terbunuh adalah orang yang terbunuh ketika memerangi anjing-anjing penghuni neraka“[106].
Para ulama Ahlus Sunnah pun dari dulu sampai sekarang telah menerapkan metode tahdzir ini, baik tahdzir terhadap individu maupun terhadap kelompok tertentu
Para ulama telah menjelaskan bahwa mentahdzir dari ahlul bid’ah dan membantah mereka merupakan amalan yang disyari’atkan di dalam agama Islam dalam rangka menjaga kemurnian agama Islam dan menasehati umat agar tidak terjerumus ke dalam kubang bid’ah tersebut.
Di antara keterangan tersebut, perkataan Imam al-Qarafi rahimahullah, “Hendaknya kerusakan dan aib ahlul bid’ah serta pengarang buku-buku yang menyesatkan dibeberkan kepada umat, dan dijelaskan bahwa mereka tidak berada di atas kebenaran; agar orang-orang yang lemah berhati-hati darinya sehingga tidak terjerumus ke dalamnya. Dan semampu mungkin umat dijauhkan dari kerusakan-kerusakan tersebut”[107].
Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya, “Mana yang lebih engkau sukai; seseorang berpuasa, shalat dan i’tikaf atau mengkritik ahlul bid’ah? Beliau menjawab, “Kalau dia shalat, puasa dan i’tikaf maka manfaatnya hanya untuk dia sendiri, namun jika dia mengkritik ahlul bid’ah maka manfaatnya bagi kaum muslimin, dan ini lebih afdhal!”[108].
Dan masih banyak perkataan-perkataan ulama Ahlus Sunnah yang senada[109].
Berikut kami bawakan beberapa contoh praktek nyata para ulama kita dari dulu sampai sekarang, dalam menerapkan metode tahdzir -baik tahdzir terhadap individu maupun terhadap kelompok tertentu-; supaya kita paham betul bahwa metode tahdzir adalah metode yang ashil ('orisinil') dan bukan metode bid’ah yang diada-adakan di zaman ini[110]:
1. Abdullah bin Umar radhiyallahu’anhuma (wafat thn 73 H) ketika beliau mentahdzir dari sekte Qadariyah dengan perkataannya, “Beritahukanlah kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka, dan mereka berlepas diri dariku”[111].
2. Imam al-Bukhari rahimahullah (w. 256 H) ketika beliau mentahdzir dari sekte Jahmiyyah dalam kitabnya: “Khalq Af’al al-‘Ibad wa ar-Radd ‘ala al-Jahmiyyah wa Ashab at-Ta’thil”[112].
3. Imam ad-Darimi rahimahullah (w. 280 H) ketika beliau mentahdzir dari Bisyr al-Mirrisi dalam kitabnya: “Naqdh Utsman ad-Darimi ‘ala al-Mirrisi al-Jahmi al-‘Anid fima Iftara ‘ala Allah fi at-Tauhid”[113].
4. Imam ad-Daruquthni rahimahullah (w. 385 H) ketika beliau mentahdzir dari ‘Amr bin ‘Ubaid -gembong sekte Mu’tazilah di zamannya- dalam kitabnya “Akhbar ‘Amr bin ‘Ubaid bin Bab al-Mu’tazili”[114].
5. Imam Abu Nu’aim al-Ashbahani rahimahullah (w. 430 H) ketika beliau mentahdzir dari sekte Rafidhah dalam kitabnya “Al-Imamah wa ar-Radd ‘ala ar-Rafidhah”[115].
6. Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah (w. 505 H) ketika beliau mentahdzir dari sekte al-Bathiniyyah dalam kitabnya “Fadha’ih al-Bathiniyyah”[116].
7. Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah (w. 620 H) ketika beliau mentahdzir dari Abu al-Wafa’ Ibnu ‘Aqil -salah seorang tokoh sekte Mu’tazilah- dalam kitabnya “Tahrim an-Nazhar fi Kutub al-Kalam”[117].
8. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah (w. 728 H) ketika beliau mentahdzir dari al-Bakri -salah seorang tokoh sufi di zaman itu- dalam kitabnya “Al-Istighatsah fi ar-Radd ‘ala al-Bakri”[118].
9. Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah (w. 751 H) ketika beliau mentahdzir dari sekte Jahmiyyah dan golongan Mu’athilah dalam kitabnya “Ash-Shawa’iq al-Mursalah ‘ala al-Jahmiyyah wa al-Mu’athilah”[119].
10. Ibnu Hajar al-Haitami rahimahullah (w. 974 H) ketika beliau mentahdzir dari sekte Rafidhah dan orang-orang Zindiq dalam kitabnya “Ash-Shawa’iq al-Muhriqah ‘ala Ahl ar-Rafdh wa adh-Dhalal wa az-Zandaqah”[120].
11. Imam Abdul Lathif bin Abdurrahman Alu Syaikh rahimahullah (w. 1292 H) ketika beliau mentahdzir dari Dawud bin Jarjis -salah satu pembesar sufi di zaman itu- dalam kitabnya “Minhaj at-Ta’sis wa at-Taqdis fi Kasyf Syubuhat Dawud bin Jarjis”[121].
12. Imam Abu al-Ma’ali al-Alusi rahimahullah (w. 1342 H) ketika beliau mentahdzir dari an-Nabhani -salah satu tokoh sufi di zaman itu- dalam kitabnya “Ghayah al-Amani fi ar-Radd ‘ala an-Nabhani”[122].
13. Al-‘Allamah Abdurrahman as-Sa’di rahimahullah (w. 1376 H) ketika beliau mentahdzir dari Abdullah al-Qashimi -salah satu tokoh yang terpengaruh pemikiran sekuler di zaman itu- dalam kitabnya “Tanzih ad-Din wa Hamalatih wa Rijalih mimma Iftarah al-Qashimi fi Aghlalih”[123].
14. Al-‘Allamah al-Albani rahimahullah (w. 1420 H) ketika beliau mentahdzir dari Hasan Abdul Mannan dalam kitabnya “An-Nashihah bi at-Tahdzir min Takhrib Ibn Abdil Mannan li Kutub al-A’immah ar-Rajiihah wa Tadh’ifih li Mi’aat al-Ahadits ash-Shahihah”[124].
15. Al-‘Allamah Abdul Muhsin al-‘Abbad hafizhahullah ketika beliau mentahdzir dari ar-Rifa’i dan al-Buthi -tokoh-tokoh yang membenci dakwah salafiyah- dalam kitabnya “Ar-Radd ‘ala ar-Rifa’i wa al-Buthi fi Kadzibihima ‘ala Ahl as-Sunnah wa Da’watihima Ila al-Bida’ wa adh-Dhalal”[125],
16. Syaikh Dr. Bakr Abu Zaid hafizhahullah ketika beliau mentahdzir dari Muhammad bin Ali ash-Shabuni -salah satu tokoh sekte Asy’ariyyah abad ini- dalam kitabnya “At-Tahdzir min Mukhtasharat Muhammad bi Ali ash-Shabuni fi at-Tafsir”[126].
17. Syaikh Dr. Rabi’ bin Hadi al-Madkhali hafizhahullah ketika beliau mentahdzir dari Sayyid Quthb -salah satu tokoh pergerakan Islam yang mengusung pemikiran takfiri- dalam kitabnya “Matha’in Sayyid Quthb fi Ashab Rasulillah Shallallahu’alaihiwasallam”[127] dan kitab-kitab beliau lainnya.
18. Syaikh Prof. Dr. Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin al-Badr hafizhahullah ketika beliau mentahdzir dari Hasan as-Segaf -salah satu tokoh sekte Jahmiyah abad ini- dalam kitabnya “Al-Qaul as-Sadid fi ar-Radd ‘ala Man Ankara Taqsim at-Tauhid”[128].
19. Syaikh Salim bin ‘Ied al-Hilali hafizhahullah ketika beliau mentahdzir dari kelompok-kelompok pergerakan abad ini yang memiliki penyimpangan-penyimpangan, dalam kitabnya “Al-Jama’at al-Islamiyyah fi Dhau’i al-Kitab wa as-Sunnah bi Fahm Salaf al-Ummah”[129].
Dan masih ada puluhan bahkan mungkin ratusan contoh praktek nyata para ulama kita -tempo dulu maupun di zaman ini- dalam menerapkan metode tahdzir ini.
Hanya saja perlu diketahui bahwasanya tatkala agama Islam telah menjelaskan disyari’atkannya penerapan metode tahdzir, agama kita pun juga telah menjelaskan norma-normanya[130].
Di antara norma yang perlu diperhatikan ketika menerapkan metode ini: membedakan antara kondisi di mana kita dituntut untuk terang-terangan mengidentifikasikan individu atau kelompok yang ditahdzir, dengan kondisi di saat kita dituntut untuk tidak terang-terangan mengidentifikasikannya.
Di antara faktor yang mendorong seorang da’i untuk terang-terangan menyebutkan nama kelompok atau individu yang ditahdzir, adalah jika umat yang dihadapinya tidak mengerti dan tidak paham apa yang dimaksud, jika sang da’i tidak terang-terangan.
Namun jika umat sudah mengerti siapa sebenarnya yang dimaksud dalam bantahan tersebut, dan justru jika metode ini diterapkan akan berakibat umat tidak menerima al-haq yang disampaikan, maka saat itu cukup bagi seorang da’i untuk menyampaikan kesalahan kelompok atau individu yang dimaksud beserta bantahannya, tanpa terang-terangan menyebutkan nama kelompok atau individu tersebut.
Dan memang hukum asal cara mentahdzir adalah dengan tidak menyebutkan terang-terangan nama yang ditahdzir. Sebagaimana praktek Rasulullah Shallallahu’alaihiwasallam ketika akan menjelaskan kesalahan sebagian orang, dengan perkataannya,
(ما بال أقوام قالوا كذا وكذا).
“Mengapa ada sebagian orang berkata ini dan itu”[131].
Ini adalah hukum asalnya, namun jika dibutuhkan untuk terang-terangan menyebutkan nama yang ditahdzir, itupun tidak mengapa, sebagaimana praktek Rasulullah Shallallahu’alaihiwasallam,
(أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه, وأما معاوية فصعلوك لا مال له).
“Adapun Abu Jahm maka dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya (suka memukul) sedangkan Mu'awiyah maka dia adalah orang yang miskin yang tidak punya harta"[132].
Syaikh al-‘Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menjelaskan, “Hendaknya yang menjadi tujuan adalah menjelaskan kebenaran dan kebathilan tanpa perlu menyebutkan nama orang yang dinukil kecuali dalam kondisi darurat yang mengharuskan penyebutan orang tersebut”[133].
Syaikh al-‘Allamah Muhammad al-‘Utsaimin rahimahullah memberikan keterangan serupa, “Jadi, menyebutkan individu hukumnya boleh dalam kondisi darurat, jika tidak, maka yang penting adalah membantah perkataan yang batil (bukan pelakunya -pen)”[134].
Syaikh Abdul Malik Ramadhani hafizhahullah dalam salah satu ceramahnya menegaskan bahwa metode inilah yang diterapkan oleh Rasulullah shallallahu’alaihiwasallam di dalam kebanyakan sikapnya, “Petunjuk Nabi shallallahu’alaihiwasallam dalam hal itu [yakni dalam hal menjelaskan kesalahan orang lain] beliau mencukupkan diri dengan penjelasan secara global tanpa merincikan (pelakunya), ini hukum asalnya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Shahih Muslim bahwa Rasulullah shallallahu’alaihiwasallam bersabda, “Mengapa sebagian orang melakukan ini dan itu”. Ini (sudah cukup) jika tujuan telah tercapai, namun jika (tujuan untuk memperingati seseorang tidak tercapai dengan peringatan secara global) maka perlu disebutkan secara terang-terangan siapa pelakunya. Inilah hukum asal yang selalu (diterapkan).
Engkau pun juga bisa mengatakan, “Mengapa fulan atau sebagian orang berkata ini dan itu”, tanpa menyebutkan namanya. Jika orang yang bersalah itu telah paham dan kembali (kepada al-haq), maka ini sudah cukup bagimu dan bersyukurlah kepada Allah ‘azza wa jalla”[135].
Syaikh Dr. Rabi’ bin Hadi al-Madkhali hafizhahullah menasehatkan, “Termasuk pula (metode dalam berdakwah yang esensial) adalah janganlah engkau mencerca atau mencaci-maki firqah mereka. (Hal ini berdasarkan firman Allah), “Dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan”. QS. Al-An’am: 108”[136].
Beliau menambahkan, “Wahai para penuntut ilmu, kalian jangan menyangka bahwa termasuk dari bentuk kesempurnaan manhaj yang benar ini adalah keharusan mencaci-maki tokoh-tokoh mereka. Tidak! Sesungguhnya Allah subhanah berfirman (yang artinya): “Dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan”. QS. Al-An’am: 108. Kalau kalian mencerca syaikh fulan atau kau katakan, “Fulan sesat!” Atau julukan-julukan lainnya atau kalian katakan, “Tarekat fulan sesat!” justru yang demikian ini hanya akan membuat umat lari menjauh darimu. Akhirnya kalian berdosa lantaran kalian telah menjauhkan manusia dari dakwah yang benar, kalian munaffirun (membuat orang lari)”. Padahal Rasulullah shallallahu’alaihiwasallam tatkala mengutus Mu’adz dan Abu Musa radhiyallahu’anhuma ke Yaman beliau berpesan kepada keduanya: “Hendaklah kalian mempermudah dan jangan mempersulit, gembirakan mereka dan jangan kalian membuat mereka lari”[137].
Beliau kembali menegaskan, “Jika ada yang datang berdakwah kepada mereka kemudian membodoh-bodohkan pengikut aliran Tijani, boleh jadi mereka akan menyembelihnya, tidak cukup hanya diusir! Tapi jika kalian datang berdakwah kepada mereka dengan hikmah dan lemah lembut -baarakallahu fik- maka Allah akan memberikan manfaat kepada mereka dengan sebab perangai tersebut”[138].
Berikut akan kami bawakan contoh nyata keberhasilan dakwah seorang da'i dan ulama, tatkala beliau tidak memulai dakwahnya dengan mengidentifikasi secara terang-terangan 'lawan-lawannya'.
Syaikh Rabi' al-Madkhali hafizahullah mengisahkan pengalaman dakwah beliau di negeri Sudan, "Sesampainya saya di bandara Sudan, saya disambut oleh para pemuda Jama'ah Anshar as-Sunah. Mereka memberi masukan, "Ya Syaikh, bolehkah kami menyampaikan beberapa saran kepada anda?".
"Silahkan" kataku.
Mereka berkata, "Wahai Syaikh, silahkan anda berceramah sekehendak anda dengan (mengutip) firman Allah dan sabda Nabi-Nya Shallallahu’alaihiwasallam, tidak mengapa engkau sebutkan berbagai jenis bid'ah dan kesesatannya, baik kaitannya dengan doa kepada selain Allah, menyembelih, nadzar atau istighatsah kepada selain-Nya. Namun sebaiknya engkau tidak menyinggung tarekat tertentu atau syaikh fulan! Jangan sampai engkau mengatakan bahwa tarekat Tijaniyah atau Bathiniyyah sesat. Jangan pula engkau mencaci tokoh-tokohnya. Cukup engkau sebutkan perkara-perkara akidah (secara umum), niscaya engkau akan dapati mereka menerima al-haq yang engkau sampaikan".
Saya katakan padanya, "Baiklah".
Akhirnya saya ikuti anjuran mereka. Ternyata saya menyaksikan sambutan yang sangat besar dari kaum muslimin terhadap dakwah ini…
Demi Allah, tidaklah aku masuk suatu masjid melainkan aku melihat wajah mereka berseri-seri, sehingga aku tidak bisa keluar dari kerumunan masa yang berebut berjabat tangan serta mendoakan kebaikan untukku.
Ternyata para pentolan tarekat sufi melihat cara dakwah yang saya tempuh sebagai suatu ancaman yang berbahaya. Akhirnya tokoh-tokoh tersebut berkumpul dan berunding untuk merumuskan bantahan-bantahan terhadap ceramah saya.
Mereka memintaku untuk memberikan ceramah di suatu lapangan. Maka saya penuhi permintaan mereka. Akupun ceramah hingga selesai. Giliran pembesar mereka bangkit (setelahku) dan mengomentari ceramahku tadi. Mulailah orang ini mengutarakan pendapatnya tentang bolehnya beristighatsah kepada selain Allah, bertawassul dengan mayit, mengingkari sifat-sifat Allah dan ucapan-ucapan batil lainnya. Mereka kemas semua ucapan batil itu dengan takwil-takwil yang menyimpang dan keji.
Usai dia berbicara -namun ia tidak menyertakan dasar dalilnya, yang ada hanyalah hadits-hadits dha'if dan palsu atau nukilan dari ucapan Socrattes- maka aku katakana kepada hadirin, "Apakah hadirin sekalian telah mendengar ceramahku? Bukankah yang aku sampaikan adalah semata-mata firman Allah dan sabda Rasulullah Shallallahu’alaihiwasallam? Tapi lihatlah orang ini! Yang ia sebutkan adalah hadits-hadits palsu belaka. Padahal al-Qur'an lebih berhak untuk disebutkan di sini. Pernahkah kalian mendengar firman Allah yang membolehkan istighatsah kepada selain-Nya?! Bolehnya tawassul (dengan mayit)?! Atau pernahkah kalian mendengar ucapan para imam terkemuka dalam hal ini semua?! Tidak sama sekali tidak! Kalian hanya mendengar hadits-hadits palsu dan dha'if atau tak lebih dari sekedar omongan segelintir manusia yang sangat masyhur di antara kalian sebagai pengusung khurafat?!"
Tidak lama kemudian orang tersebut bangkit sambil memaki-maki. Namun aku hanya tersenyum dan sama sekali tidak menanggapi caciannya. Aku hanya mengucapkan, "Jazakallahu khairan, barakallah fik, barakallah fik, jazakallah khairan!" Tidak lebih dari itu.
Bubarlah acara tersebut. Maka demi Allah, ternyata keesokan harinya banyak orang yang memperbincangkan kejadian ini baik di masjid-masjid maupun di pasar-pasar. Mereka berkomentar bahwa orang-orang Sufi telah kalah…
Kemudian kami melanjutkan perjalanan ke Kasala, masih wilayah Sudan. MasyaAllah, dakwah Ahlus Sunnah mendapatkan kemudahan dan tanggapan bagus. Kami diberi kesempatan untuk berkhutbah dan kita bersyukur dengan keadaan ini …
Kemudian kami pergi ke kota Ghatharif, sebuah kota kecil di sana. Kami menyempatkan diri untuk mengelilingi masjid-masjid di kota itu. Ada sebagian dari Jama'ah Anshar as-Sunnah mengatakan, "Ya Syaikh, hanya tinggal satu masjid di kota ini yang belum terjamah dakwah kita, sebab masjid ini adalah basis tarekat tijaniyah, lantaran itu kita belum bisa masuk ke sana".
"Lho kenapa?".
"Sebab mereka sangat fanatik".
"Baiklah, kalau demikian kita pergi ke sana. Kita akan minta izin; kalau diizinkan untuk bicara, maka kita bicara. Tapi kalau mereka melarang, maka udzur kita di sisi Allah. Dan ingat! Jangan kita memaksakan diri untuk berbicara".
Sampailah kami di masjid mereka. Kami shalat bersama mereka sebagai makmum. Usai shalat, kami ucapkan salam kepada sang imam. Aku berkata, "Bolehkah aku berbicara di hadapan saudara-saudara kami di sini?"
"Silahkan" jawab sang imam.
Mulailah aku berceramah, aku ajak mereka untuk mentauhidkan Allah dan melaksanakan sunnah dan perkara-perkara lain dari agama. Sesekali aku menyinggung beberapa kesalahan serta berbagai kesesatan yang ada. Di sela-sela itu aku mengutip hadits Aisyah yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim yang berbunyi, "Ada tiga hal, barang siapa yang mengatakan tiga perkara ini maka ia telah melakukan kedustaan besar di sisi Allah: (1) Barang siapa yang meyakini bahwa Nabi Muhammad Shallallahu’alaihiwasallam telah melihat Rabb-nya (di dunia) maka ia telah melakukan kedustaan yang besar di sisi Allah. (2) Barang siapa meyakini bahwa Nabi Muhammad Shallallahu’alaihiwasallam mengetahui kejadian-kejadian yang akan datang maka ia telah melakukan kedustaan yang besar di sisi Allah. Dan saya sebutkan pula berbagai dalil yang mendukung hadits ini. (3) Barang siapa meyakini bahwa Nabi Muhammad Shallallahu’alaihiwasallam tidak menyampaikan risalah dari Allah secara sempurna maka ia telah melakukan kedustaan yang besar di sisi Allah".
Lalu sang imam berkomentar (ia terlihat gusar dan gelisah), "Demi Allah, sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu’alaihiwasallam telah melihat Allah di dunia dengan kedua mata kepalanya".
Namun aku hanya menyambut komentar si imam dengan ucapan, "Jazakallah khairan. (Tentunya kita tahu) bahwa Aisyah sebagai istri Rasul Shallallahu’alaihiwasallam tentu lebih tahu akan keadaan beliau. Kalaulah Rasulullah Shallallahu’alaihiwasallam benar-benar telah melihat Rabb-nya di dunia tentu Aisyah akan mengabarkannya, tapi kenapa ia tidak mengabarkannya?".
Lalu ia mendesakku dengan pertanyaan bertubi-tubi.
Aku katakan, "Ya akhi, tunggulah sebentar, beri kesempatan kepadaku agar aku selesaikan jawabanku satu persatu. Setelah itu silahkan engkau lanjutkan dengan pertanyaan lain sekehendakmu. Apa yang aku ketahui akan aku jawab, dan apa yang tidak aku ketahui akan aku katakan padamu, "Wallahu a'lam".
Lalu aku abaikan orang itu dan aku teruskan ceramahku. Aku tidak tahu apakah ia tetap duduk di situ atau pergi meninggalkan majelis, karena akupun sengaja tidak menoleh kepadanya.
Terdengar olehku bisikan orang, "Benar juga ucapan orang ini" Terdengar juga dari selain dia kata-kata lain, "Demi Allah, lelaki ini tidak menyampaikan melainkan firman Allah dan sabda Rasul-Nya Shallallahu’alaihiwasallam".
Adzan Isya dikumandangkan, maka berakhirlah acara tersebut, lantas jama'ah masjid melaksanakan shalat Isya. Tiba-tiba mereka mendorongku untuk menjadi imam Isya". Aku katakan, "Sama sekali aku tidak mau menjadi imam".
Mereka malah menjawab, "Demi Allah, shalatlah mengimami kami, demi Allah, shalatlah mengimami kami". Akhirnya aku katakan, "Baiklah kalau begitu".
Akhirnya akupun shalat mengimami mereka. Usai shalat aku menunggu sejenak, kemudian aku pulang bersama para pemuda Anshar as-Sunnah.
Aku bertanya kepada mereka, "Kemana sang imam pergi?". Mereka menjawab, "Telah diusir!". "Lho siapa yang mengusirnya?" tanyaku lagi. "Demi Allah, jama'ahnya yang mengusir dia!" tandas mereka.
Itulah yang terjadi wahai saudara-saudaraku. Singkatnya jika ada yang datang berdakwah kepada mereka kemudian membodoh-bodohkan pengikut aliran tijani, boleh jadi mereka akan mememenggal lehermu, tidak cukup hanya diusir! Tapi jika kalian datang berdakwah kepada mereka dengan hikmah dan lemah lembut, maka Allah akan memberikan manfaat kepada mereka dengan lantaran perangai tersebut.
Hendaknya engkau berbekal dengan ilmu yang bermanfaat, argumentasi yang kokoh, senantiasa memprioritaskan hikmah di dalam dakwah kalian. Wajib atas kalian untuk berhias diri dengan akhlak mulia yang telah dianjurkan Allah dalam kitab-Nya dan Rasulullah Shallallahu’alaihiwasallam. Sesungguhnya itu merupakan (salah satu) sarana (terbesar) untuk mendapatkan pertolongan dan kesuksesan".[139]
Sekali lagi kami ingin mengingatkan, bahwa kami di sini tidak sedang mengingkari disyariatkannya pengidentifikasian terang-terangan nama individu atau kelompok yang ditahdzir jika memang diperlukan; karena memang ada dalil yang menunjukkan akan hal itu.
Masalah ini perlu kami tekankan kembali; karena akhir-akhir ini ada sebagian orang yang sama sekali melarang hal tersebut di atas, berlandaskan sebagian dalil yang menunjukkan akan hal itu, sayangnya ia tidak tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa di sana juga ada dalil shahih dan praktek para ulama salaf yang menunjukkan bolehnya pengidentifikasian nama individu atau kelompok yang ditahdzir, jika memang diperlukan. Wallahua'lam.
-----
Footnote
[101] Majmu’ al-Fatawa (XXXV/414). Lihat pula: Sittu Durar min Ushul Ahl al-Atsar karya Syaikh Abdul Malik Ramadhani (hal. 109-112).
[102] Lihat: Al-Kafiah fi al-Jadal (hal. 20-21).
[103] HR. Al-Khathib al-Baghdady dalam Syaraf Ashab al-Hadits (hal.65 no.51) dan yang lainnya. Hadits ini dishahihkan oleh Imam Ahmad sebagaimana dalam Syaraf Ashab al-Hadits (hal.65). Al-‘Ala’i dalam Bughyah al-Multamis (hal.34) berkata “Hasan shahih gharib”. Ibn al-Qayyim dalam Thariq al-Hijratain (hal.578) berkata, “Hadits ini diriwayatkan dari banyak jalan yang saling menguatkan”. Senada dengan perkataan Ibn al-Qayyim: penjelasan al-Qashthallani dalam Irsyad as-Sari (I/7). Syaikh Salim al-Hilaly telah mentakhrij hadits ini secara riwayah dan dirayah dalam kitabnya Irsyad al-Fuhul ila Tahrir an-Nuqul fi Tashih Hadits al-‘Udul, dan beliau menyimpulkan bahwa derajat hadits ini adalah hasan.
[104] Lihat dalil-dalil tersebut dalam kitab: Mauqif Ahl as-Sunnah (II/482-488), al-Mahajjah al-Baidha’ (hal. 55-74), ar-Radd ‘ala al-Mukhalif (hal. 22-29), dan Munazharat A’immah as-Salaf (hal.14-19).
[105] HR. Ahmad (III/4-5). Para muhaqqiq Musnad (XVII/47) menshahihkan isnadnya. Hadits ini aslinya dalam Bukhari (hal. 1454 no. 6933) dan Muslim (II/744 no. 1064).
[106] HR. Ibnu Majah (I/62 no. 176). Syaikh al-Albani dalam Shahih Sunan Ibn Majah (I/76) berkata, “Hasan shahih”.
[107] Al-Furuq (IV/207),
[108] Majmu’ Fatawa Syaikhil Islam (XXVIII/231).
[109] Lihat: Mathla’ al-Fajr fi Fiqh az-Zajr bi al-Hajr karya Syaikh Salim aHilali (hal. 62-77) dan Ijma’ al-‘Ulama’ ‘ala al-Hajr wa at-Tahdzir min Ahl al-Ahwa’ karya Syaikh Khalid azh-Zhufairi (hal. 89-153).
[110] Tidak semua tokoh yang kami sebutkan di sini berakidah Ahlus Sunnah dalam setiap permasalahan, namun ada sebagian kecil dari mereka yang berseberangan dengan Ahlus Sunnah dalam berbagai permasalahan. Sengaja mereka kami sebutkan pula, agar umat tahu bahwa metode tahdzir ini juga diterapkan oleh para ahli ilmu di luar lingkaran Ahlus Sunnah, maka amat keliru jikalau Ahlus Sunnah selalu dipojokkan akibat mereka menerapkan metode ini, wallahu a’lam.
[111] R. Muslim (no. 1).
[112] Dicetak di Riyadh: Dar Athlas al-Khadhra’, dengan tahqiq Dr. Fahd al-Fuhaid.
[113] Dicetak di Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, dengan tahqiq Dr. Rasyid al-Alma’i.
[114] Dicetak di Riyadh; Dar at-Tauhid, dengan tahqiq Muhammad Alu ‘Amir.
[115] Dicetak di Madinah: Maktabah al-‘Ulum wa al-Hikam, dengan tahqiq Prof. Dr. Ali al-Faqihi.
[116] Dicetak di Kuwait: Dar al-Kutub ats-Tsaqafiyyah, dengan tahqiq Abdurrahman Badawi.
[117] Dicetak di Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub, dengan tahqiq Abdurrahman Dimasyqiyyah.
[118] Dicetak di Riyadh: Maktabah Dar al-Minhaj, dengan tahqiq Dr. Abdullah as-Sahli.
[119] Dicetak di Riyadh: Adhwa’ as-Salaf, dengan tahqiq Dr. Al-Hasan al-‘Alawi.
[120] Dicetak di Beirut: Mu’assasah ar-Risalah, dengan tahqiq Abdurrahman at-Turki dan Kamil al-Kharrath.
[121] Dicetak di Riyadh: Dar al-Hidayah.
[122] Dicetak di Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, dengan ‘inayah ad-Dani Zahwi.
[123] Dicetak di Damam: Dar Ibn al-Jauzi, dengan tahqiq Abdurrahman ar-Rahmah.
[124] Dicetak di Damam: Dar Ibn al-Qayyim.
[125] Dicetak di Kairo: Dar al-Imam Ahmad.
[126] Dicetak di Damam: Dar Ibn al-Jauzi.
[127] Dicetak di Emirat: Maktabah al-Furqan.
[128] Dicetak di Damam: Dar Ibn al-Qayyim.
[129] Dicetak di Kairo; Dar al-Imam Ahmad.
[130] Lihat makalah yang kami tulis dengan judul: "Upaya Menjaga Kemurnian Islam Menyoal Tahdzir dan Norma-Normanya" (hal. 4-5).
[131] HR. Muslim (II/1020 no. 1401 -asy-syamilah).
[132] HR. Muslim (II/1114 no. 1480 -asy-syamilah). Nabi Shallallahu’alaihiwasallam mengeluarkan pernyataan ini tatkala dimintai pendapat oleh Fathimah binti Qais tentang siapa di antara dua sahabat tadi yang akan dia terima pinangannya, lalu Nabi Shallallahu’alaihiwasallam menunjukkan kekurangan masing-masing dari keduanya dan menasehatkan Fathimah mau dinikahi Usamah bin Zaid. Seandainya menyebutkan aib dua orang sahabat Nabi Shallallahu’alaihiwasallam untuk kepentingan duniawi seorang wanita diperbolehkan, tentunya menyebutkan aib ahlul bid'ah untuk kepentingan akherat kaum muslimin lebih diperbolehkan. Lihat: Mauqif Ahl as-Sunnah (II/488) dan Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam (XXVIII/230).
[133] Majmu’ Fataawa wa Maqaalaat Mutanawwi’ah (VIII/242). Lihat pula: Ar-Radd ‘ala al-Mukhalif (hal. 60).
[134] Syarh al-Arba’in an-Nawawiyyah (hal. 317).
[135] Sebagaimana dalam kaset beliau yang berjudul "Tsimar Murrah min Ghiras at-Tajrih bi Ghairi Haq".
[136] Al-Hats ‘ala al-Mawaddah (hal. 24).
[137] Op Cit (hal. 25).
[138] Op Cit (hal. 30).
[139] Diringkas dari al-Hats 'ala al-Mawaddah (hal. 24-30). Dalam menerjemahkan kisah ini penulis banyak terbantu dengan edisi Indonesia buku ini "Dakwah Salafiyah Dakwah Penuh Hikmah, Sepenggal Kisah Perjalanan Dakwah asy-Syaikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali" (hal. 36-45) terjemahan ustadz Abu Affan Asasuddin.
Mentahdzir dari ahlul bid'ah merupakan salah satu ibadah yang amat mulia di dalam agama Islam. Banyak sekali dalil-dalil -baik dari al-Qur’an maupun sunnah- yang menunjukkan disyari’atkannya metode tahdzir, jika dilakukan sesuai dengan norma-norma yang digariskan syari’at.
Di antaranya adalah firman Allah ta’ala,
]وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ[
Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”. QS. Ali-Imran: 104.
Ayat di atas menjelaskan disyariatkannya amar ma’ruf nahi munkar, dan para ulama telah menerangkan bahwa penerapan metode tahdzir adalah merupakan salah satu bentuk amar ma’ruf dan nahi munkar.
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, “Kalaupun dia (ahlul bid’ah tersebut) tidak berhak atau tidak memungkinkan untuk dihukum, maka kita harus menjelaskan bid’ahnya tersebut dan mentahdzir (umat) darinya, sesungguhnya hal ini termasuk bentuk amar ma’ruf dan nahi munkar yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya Shallallahu’alaihiwasallam”[101].
Senada dengan keterangan Ibnu Taimiyah di atas; penjelasan yang dibawakan oleh Imam al-Haramain al-Juwaini rahimahullah[102].
Di antara dalil disyari’atkannya tahdzir adalah sabda Nabi Shallallahu’alaihiwasallam,
(يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله؛ ينفون عنه تحريف الغالين, وانتحال المبطلين, وتأويل الجاهلين).
“Agama ini diemban di setiap zaman oleh para ulama; yang (bertugas untuk) menyisihkan penyimpangan golongan yang ekstrim, jalan orang-orang batil dan ta’wilnya orang-orang yang jahil”[103].
Dan masih banyak dalil lain yang menunjukkan disyari’atkannya penerapan metode tahdzir[104]. Bahkan nabi kita Shallallahu’alaihiwasallam pun mempraktekkan metode tahdzir dalam kehidupannya; entah itu tahdzir terhadap individu maupun tahdzir dari suatu kelompok tertentu.
Di antara contoh praktek beliau Shallallahu’alaihiwasallam dalam mentahdzir suatu individu; tatkala beliau mentahdzir umat dari ‘nenek moyang’ Khawarij: Abdullah bin Dzi al-Khuwaishirah. Beliau Shallallahu’alaihiwasallam bersabda,
(إنه سيخرج من ضئضئي هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية).
“Akan muncul dari keturunan orang ini; generasi yang rajin membaca al-Qur’an, namun bacaan mereka tidak melewati kerongkongan (tidak memahami apa yang mereka baca). Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah yang menancap di tubuh buruan, lalu melesat keluar dari tubuhnya“[105].
Adapun praktek beliau Shallallahu’alaihiwasallam dalam mentahdzir dari suatu kelompok yang menyimpang, antara lain: tatkala beliau Shallallahu’alaihiwasallam mentahdzir umat dari sekte Khawarij dalam sabdanya Shallallahu’alaihiwasallam,
(شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء وخير قتيل من قتلوا كلاب أهل النار).
“Mereka adalah seburuk-buruk orang yang dibunuh di muka bumi. Dan sebaik-baik orang yang terbunuh adalah orang yang terbunuh ketika memerangi anjing-anjing penghuni neraka“[106].
Para ulama Ahlus Sunnah pun dari dulu sampai sekarang telah menerapkan metode tahdzir ini, baik tahdzir terhadap individu maupun terhadap kelompok tertentu
Para ulama telah menjelaskan bahwa mentahdzir dari ahlul bid’ah dan membantah mereka merupakan amalan yang disyari’atkan di dalam agama Islam dalam rangka menjaga kemurnian agama Islam dan menasehati umat agar tidak terjerumus ke dalam kubang bid’ah tersebut.
Di antara keterangan tersebut, perkataan Imam al-Qarafi rahimahullah, “Hendaknya kerusakan dan aib ahlul bid’ah serta pengarang buku-buku yang menyesatkan dibeberkan kepada umat, dan dijelaskan bahwa mereka tidak berada di atas kebenaran; agar orang-orang yang lemah berhati-hati darinya sehingga tidak terjerumus ke dalamnya. Dan semampu mungkin umat dijauhkan dari kerusakan-kerusakan tersebut”[107].
Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya, “Mana yang lebih engkau sukai; seseorang berpuasa, shalat dan i’tikaf atau mengkritik ahlul bid’ah? Beliau menjawab, “Kalau dia shalat, puasa dan i’tikaf maka manfaatnya hanya untuk dia sendiri, namun jika dia mengkritik ahlul bid’ah maka manfaatnya bagi kaum muslimin, dan ini lebih afdhal!”[108].
Dan masih banyak perkataan-perkataan ulama Ahlus Sunnah yang senada[109].
Berikut kami bawakan beberapa contoh praktek nyata para ulama kita dari dulu sampai sekarang, dalam menerapkan metode tahdzir -baik tahdzir terhadap individu maupun terhadap kelompok tertentu-; supaya kita paham betul bahwa metode tahdzir adalah metode yang ashil ('orisinil') dan bukan metode bid’ah yang diada-adakan di zaman ini[110]:
1. Abdullah bin Umar radhiyallahu’anhuma (wafat thn 73 H) ketika beliau mentahdzir dari sekte Qadariyah dengan perkataannya, “Beritahukanlah kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka, dan mereka berlepas diri dariku”[111].
2. Imam al-Bukhari rahimahullah (w. 256 H) ketika beliau mentahdzir dari sekte Jahmiyyah dalam kitabnya: “Khalq Af’al al-‘Ibad wa ar-Radd ‘ala al-Jahmiyyah wa Ashab at-Ta’thil”[112].
3. Imam ad-Darimi rahimahullah (w. 280 H) ketika beliau mentahdzir dari Bisyr al-Mirrisi dalam kitabnya: “Naqdh Utsman ad-Darimi ‘ala al-Mirrisi al-Jahmi al-‘Anid fima Iftara ‘ala Allah fi at-Tauhid”[113].
4. Imam ad-Daruquthni rahimahullah (w. 385 H) ketika beliau mentahdzir dari ‘Amr bin ‘Ubaid -gembong sekte Mu’tazilah di zamannya- dalam kitabnya “Akhbar ‘Amr bin ‘Ubaid bin Bab al-Mu’tazili”[114].
5. Imam Abu Nu’aim al-Ashbahani rahimahullah (w. 430 H) ketika beliau mentahdzir dari sekte Rafidhah dalam kitabnya “Al-Imamah wa ar-Radd ‘ala ar-Rafidhah”[115].
6. Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah (w. 505 H) ketika beliau mentahdzir dari sekte al-Bathiniyyah dalam kitabnya “Fadha’ih al-Bathiniyyah”[116].
7. Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah (w. 620 H) ketika beliau mentahdzir dari Abu al-Wafa’ Ibnu ‘Aqil -salah seorang tokoh sekte Mu’tazilah- dalam kitabnya “Tahrim an-Nazhar fi Kutub al-Kalam”[117].
8. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah (w. 728 H) ketika beliau mentahdzir dari al-Bakri -salah seorang tokoh sufi di zaman itu- dalam kitabnya “Al-Istighatsah fi ar-Radd ‘ala al-Bakri”[118].
9. Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah (w. 751 H) ketika beliau mentahdzir dari sekte Jahmiyyah dan golongan Mu’athilah dalam kitabnya “Ash-Shawa’iq al-Mursalah ‘ala al-Jahmiyyah wa al-Mu’athilah”[119].
10. Ibnu Hajar al-Haitami rahimahullah (w. 974 H) ketika beliau mentahdzir dari sekte Rafidhah dan orang-orang Zindiq dalam kitabnya “Ash-Shawa’iq al-Muhriqah ‘ala Ahl ar-Rafdh wa adh-Dhalal wa az-Zandaqah”[120].
11. Imam Abdul Lathif bin Abdurrahman Alu Syaikh rahimahullah (w. 1292 H) ketika beliau mentahdzir dari Dawud bin Jarjis -salah satu pembesar sufi di zaman itu- dalam kitabnya “Minhaj at-Ta’sis wa at-Taqdis fi Kasyf Syubuhat Dawud bin Jarjis”[121].
12. Imam Abu al-Ma’ali al-Alusi rahimahullah (w. 1342 H) ketika beliau mentahdzir dari an-Nabhani -salah satu tokoh sufi di zaman itu- dalam kitabnya “Ghayah al-Amani fi ar-Radd ‘ala an-Nabhani”[122].
13. Al-‘Allamah Abdurrahman as-Sa’di rahimahullah (w. 1376 H) ketika beliau mentahdzir dari Abdullah al-Qashimi -salah satu tokoh yang terpengaruh pemikiran sekuler di zaman itu- dalam kitabnya “Tanzih ad-Din wa Hamalatih wa Rijalih mimma Iftarah al-Qashimi fi Aghlalih”[123].
14. Al-‘Allamah al-Albani rahimahullah (w. 1420 H) ketika beliau mentahdzir dari Hasan Abdul Mannan dalam kitabnya “An-Nashihah bi at-Tahdzir min Takhrib Ibn Abdil Mannan li Kutub al-A’immah ar-Rajiihah wa Tadh’ifih li Mi’aat al-Ahadits ash-Shahihah”[124].
15. Al-‘Allamah Abdul Muhsin al-‘Abbad hafizhahullah ketika beliau mentahdzir dari ar-Rifa’i dan al-Buthi -tokoh-tokoh yang membenci dakwah salafiyah- dalam kitabnya “Ar-Radd ‘ala ar-Rifa’i wa al-Buthi fi Kadzibihima ‘ala Ahl as-Sunnah wa Da’watihima Ila al-Bida’ wa adh-Dhalal”[125],
16. Syaikh Dr. Bakr Abu Zaid hafizhahullah ketika beliau mentahdzir dari Muhammad bin Ali ash-Shabuni -salah satu tokoh sekte Asy’ariyyah abad ini- dalam kitabnya “At-Tahdzir min Mukhtasharat Muhammad bi Ali ash-Shabuni fi at-Tafsir”[126].
17. Syaikh Dr. Rabi’ bin Hadi al-Madkhali hafizhahullah ketika beliau mentahdzir dari Sayyid Quthb -salah satu tokoh pergerakan Islam yang mengusung pemikiran takfiri- dalam kitabnya “Matha’in Sayyid Quthb fi Ashab Rasulillah Shallallahu’alaihiwasallam”[127] dan kitab-kitab beliau lainnya.
18. Syaikh Prof. Dr. Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin al-Badr hafizhahullah ketika beliau mentahdzir dari Hasan as-Segaf -salah satu tokoh sekte Jahmiyah abad ini- dalam kitabnya “Al-Qaul as-Sadid fi ar-Radd ‘ala Man Ankara Taqsim at-Tauhid”[128].
19. Syaikh Salim bin ‘Ied al-Hilali hafizhahullah ketika beliau mentahdzir dari kelompok-kelompok pergerakan abad ini yang memiliki penyimpangan-penyimpangan, dalam kitabnya “Al-Jama’at al-Islamiyyah fi Dhau’i al-Kitab wa as-Sunnah bi Fahm Salaf al-Ummah”[129].
Dan masih ada puluhan bahkan mungkin ratusan contoh praktek nyata para ulama kita -tempo dulu maupun di zaman ini- dalam menerapkan metode tahdzir ini.
Hanya saja perlu diketahui bahwasanya tatkala agama Islam telah menjelaskan disyari’atkannya penerapan metode tahdzir, agama kita pun juga telah menjelaskan norma-normanya[130].
Di antara norma yang perlu diperhatikan ketika menerapkan metode ini: membedakan antara kondisi di mana kita dituntut untuk terang-terangan mengidentifikasikan individu atau kelompok yang ditahdzir, dengan kondisi di saat kita dituntut untuk tidak terang-terangan mengidentifikasikannya.
Di antara faktor yang mendorong seorang da’i untuk terang-terangan menyebutkan nama kelompok atau individu yang ditahdzir, adalah jika umat yang dihadapinya tidak mengerti dan tidak paham apa yang dimaksud, jika sang da’i tidak terang-terangan.
Namun jika umat sudah mengerti siapa sebenarnya yang dimaksud dalam bantahan tersebut, dan justru jika metode ini diterapkan akan berakibat umat tidak menerima al-haq yang disampaikan, maka saat itu cukup bagi seorang da’i untuk menyampaikan kesalahan kelompok atau individu yang dimaksud beserta bantahannya, tanpa terang-terangan menyebutkan nama kelompok atau individu tersebut.
Dan memang hukum asal cara mentahdzir adalah dengan tidak menyebutkan terang-terangan nama yang ditahdzir. Sebagaimana praktek Rasulullah Shallallahu’alaihiwasallam ketika akan menjelaskan kesalahan sebagian orang, dengan perkataannya,
(ما بال أقوام قالوا كذا وكذا).
“Mengapa ada sebagian orang berkata ini dan itu”[131].
Ini adalah hukum asalnya, namun jika dibutuhkan untuk terang-terangan menyebutkan nama yang ditahdzir, itupun tidak mengapa, sebagaimana praktek Rasulullah Shallallahu’alaihiwasallam,
(أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه, وأما معاوية فصعلوك لا مال له).
“Adapun Abu Jahm maka dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya (suka memukul) sedangkan Mu'awiyah maka dia adalah orang yang miskin yang tidak punya harta"[132].
Syaikh al-‘Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menjelaskan, “Hendaknya yang menjadi tujuan adalah menjelaskan kebenaran dan kebathilan tanpa perlu menyebutkan nama orang yang dinukil kecuali dalam kondisi darurat yang mengharuskan penyebutan orang tersebut”[133].
Syaikh al-‘Allamah Muhammad al-‘Utsaimin rahimahullah memberikan keterangan serupa, “Jadi, menyebutkan individu hukumnya boleh dalam kondisi darurat, jika tidak, maka yang penting adalah membantah perkataan yang batil (bukan pelakunya -pen)”[134].
Syaikh Abdul Malik Ramadhani hafizhahullah dalam salah satu ceramahnya menegaskan bahwa metode inilah yang diterapkan oleh Rasulullah shallallahu’alaihiwasallam di dalam kebanyakan sikapnya, “Petunjuk Nabi shallallahu’alaihiwasallam dalam hal itu [yakni dalam hal menjelaskan kesalahan orang lain] beliau mencukupkan diri dengan penjelasan secara global tanpa merincikan (pelakunya), ini hukum asalnya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Shahih Muslim bahwa Rasulullah shallallahu’alaihiwasallam bersabda, “Mengapa sebagian orang melakukan ini dan itu”. Ini (sudah cukup) jika tujuan telah tercapai, namun jika (tujuan untuk memperingati seseorang tidak tercapai dengan peringatan secara global) maka perlu disebutkan secara terang-terangan siapa pelakunya. Inilah hukum asal yang selalu (diterapkan).
Engkau pun juga bisa mengatakan, “Mengapa fulan atau sebagian orang berkata ini dan itu”, tanpa menyebutkan namanya. Jika orang yang bersalah itu telah paham dan kembali (kepada al-haq), maka ini sudah cukup bagimu dan bersyukurlah kepada Allah ‘azza wa jalla”[135].
Syaikh Dr. Rabi’ bin Hadi al-Madkhali hafizhahullah menasehatkan, “Termasuk pula (metode dalam berdakwah yang esensial) adalah janganlah engkau mencerca atau mencaci-maki firqah mereka. (Hal ini berdasarkan firman Allah), “Dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan”. QS. Al-An’am: 108”[136].
Beliau menambahkan, “Wahai para penuntut ilmu, kalian jangan menyangka bahwa termasuk dari bentuk kesempurnaan manhaj yang benar ini adalah keharusan mencaci-maki tokoh-tokoh mereka. Tidak! Sesungguhnya Allah subhanah berfirman (yang artinya): “Dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan”. QS. Al-An’am: 108. Kalau kalian mencerca syaikh fulan atau kau katakan, “Fulan sesat!” Atau julukan-julukan lainnya atau kalian katakan, “Tarekat fulan sesat!” justru yang demikian ini hanya akan membuat umat lari menjauh darimu. Akhirnya kalian berdosa lantaran kalian telah menjauhkan manusia dari dakwah yang benar, kalian munaffirun (membuat orang lari)”. Padahal Rasulullah shallallahu’alaihiwasallam tatkala mengutus Mu’adz dan Abu Musa radhiyallahu’anhuma ke Yaman beliau berpesan kepada keduanya: “Hendaklah kalian mempermudah dan jangan mempersulit, gembirakan mereka dan jangan kalian membuat mereka lari”[137].
Beliau kembali menegaskan, “Jika ada yang datang berdakwah kepada mereka kemudian membodoh-bodohkan pengikut aliran Tijani, boleh jadi mereka akan menyembelihnya, tidak cukup hanya diusir! Tapi jika kalian datang berdakwah kepada mereka dengan hikmah dan lemah lembut -baarakallahu fik- maka Allah akan memberikan manfaat kepada mereka dengan sebab perangai tersebut”[138].
Berikut akan kami bawakan contoh nyata keberhasilan dakwah seorang da'i dan ulama, tatkala beliau tidak memulai dakwahnya dengan mengidentifikasi secara terang-terangan 'lawan-lawannya'.
Syaikh Rabi' al-Madkhali hafizahullah mengisahkan pengalaman dakwah beliau di negeri Sudan, "Sesampainya saya di bandara Sudan, saya disambut oleh para pemuda Jama'ah Anshar as-Sunah. Mereka memberi masukan, "Ya Syaikh, bolehkah kami menyampaikan beberapa saran kepada anda?".
"Silahkan" kataku.
Mereka berkata, "Wahai Syaikh, silahkan anda berceramah sekehendak anda dengan (mengutip) firman Allah dan sabda Nabi-Nya Shallallahu’alaihiwasallam, tidak mengapa engkau sebutkan berbagai jenis bid'ah dan kesesatannya, baik kaitannya dengan doa kepada selain Allah, menyembelih, nadzar atau istighatsah kepada selain-Nya. Namun sebaiknya engkau tidak menyinggung tarekat tertentu atau syaikh fulan! Jangan sampai engkau mengatakan bahwa tarekat Tijaniyah atau Bathiniyyah sesat. Jangan pula engkau mencaci tokoh-tokohnya. Cukup engkau sebutkan perkara-perkara akidah (secara umum), niscaya engkau akan dapati mereka menerima al-haq yang engkau sampaikan".
Saya katakan padanya, "Baiklah".
Akhirnya saya ikuti anjuran mereka. Ternyata saya menyaksikan sambutan yang sangat besar dari kaum muslimin terhadap dakwah ini…
Demi Allah, tidaklah aku masuk suatu masjid melainkan aku melihat wajah mereka berseri-seri, sehingga aku tidak bisa keluar dari kerumunan masa yang berebut berjabat tangan serta mendoakan kebaikan untukku.
Ternyata para pentolan tarekat sufi melihat cara dakwah yang saya tempuh sebagai suatu ancaman yang berbahaya. Akhirnya tokoh-tokoh tersebut berkumpul dan berunding untuk merumuskan bantahan-bantahan terhadap ceramah saya.
Mereka memintaku untuk memberikan ceramah di suatu lapangan. Maka saya penuhi permintaan mereka. Akupun ceramah hingga selesai. Giliran pembesar mereka bangkit (setelahku) dan mengomentari ceramahku tadi. Mulailah orang ini mengutarakan pendapatnya tentang bolehnya beristighatsah kepada selain Allah, bertawassul dengan mayit, mengingkari sifat-sifat Allah dan ucapan-ucapan batil lainnya. Mereka kemas semua ucapan batil itu dengan takwil-takwil yang menyimpang dan keji.
Usai dia berbicara -namun ia tidak menyertakan dasar dalilnya, yang ada hanyalah hadits-hadits dha'if dan palsu atau nukilan dari ucapan Socrattes- maka aku katakana kepada hadirin, "Apakah hadirin sekalian telah mendengar ceramahku? Bukankah yang aku sampaikan adalah semata-mata firman Allah dan sabda Rasulullah Shallallahu’alaihiwasallam? Tapi lihatlah orang ini! Yang ia sebutkan adalah hadits-hadits palsu belaka. Padahal al-Qur'an lebih berhak untuk disebutkan di sini. Pernahkah kalian mendengar firman Allah yang membolehkan istighatsah kepada selain-Nya?! Bolehnya tawassul (dengan mayit)?! Atau pernahkah kalian mendengar ucapan para imam terkemuka dalam hal ini semua?! Tidak sama sekali tidak! Kalian hanya mendengar hadits-hadits palsu dan dha'if atau tak lebih dari sekedar omongan segelintir manusia yang sangat masyhur di antara kalian sebagai pengusung khurafat?!"
Tidak lama kemudian orang tersebut bangkit sambil memaki-maki. Namun aku hanya tersenyum dan sama sekali tidak menanggapi caciannya. Aku hanya mengucapkan, "Jazakallahu khairan, barakallah fik, barakallah fik, jazakallah khairan!" Tidak lebih dari itu.
Bubarlah acara tersebut. Maka demi Allah, ternyata keesokan harinya banyak orang yang memperbincangkan kejadian ini baik di masjid-masjid maupun di pasar-pasar. Mereka berkomentar bahwa orang-orang Sufi telah kalah…
Kemudian kami melanjutkan perjalanan ke Kasala, masih wilayah Sudan. MasyaAllah, dakwah Ahlus Sunnah mendapatkan kemudahan dan tanggapan bagus. Kami diberi kesempatan untuk berkhutbah dan kita bersyukur dengan keadaan ini …
Kemudian kami pergi ke kota Ghatharif, sebuah kota kecil di sana. Kami menyempatkan diri untuk mengelilingi masjid-masjid di kota itu. Ada sebagian dari Jama'ah Anshar as-Sunnah mengatakan, "Ya Syaikh, hanya tinggal satu masjid di kota ini yang belum terjamah dakwah kita, sebab masjid ini adalah basis tarekat tijaniyah, lantaran itu kita belum bisa masuk ke sana".
"Lho kenapa?".
"Sebab mereka sangat fanatik".
"Baiklah, kalau demikian kita pergi ke sana. Kita akan minta izin; kalau diizinkan untuk bicara, maka kita bicara. Tapi kalau mereka melarang, maka udzur kita di sisi Allah. Dan ingat! Jangan kita memaksakan diri untuk berbicara".
Sampailah kami di masjid mereka. Kami shalat bersama mereka sebagai makmum. Usai shalat, kami ucapkan salam kepada sang imam. Aku berkata, "Bolehkah aku berbicara di hadapan saudara-saudara kami di sini?"
"Silahkan" jawab sang imam.
Mulailah aku berceramah, aku ajak mereka untuk mentauhidkan Allah dan melaksanakan sunnah dan perkara-perkara lain dari agama. Sesekali aku menyinggung beberapa kesalahan serta berbagai kesesatan yang ada. Di sela-sela itu aku mengutip hadits Aisyah yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim yang berbunyi, "Ada tiga hal, barang siapa yang mengatakan tiga perkara ini maka ia telah melakukan kedustaan besar di sisi Allah: (1) Barang siapa yang meyakini bahwa Nabi Muhammad Shallallahu’alaihiwasallam telah melihat Rabb-nya (di dunia) maka ia telah melakukan kedustaan yang besar di sisi Allah. (2) Barang siapa meyakini bahwa Nabi Muhammad Shallallahu’alaihiwasallam mengetahui kejadian-kejadian yang akan datang maka ia telah melakukan kedustaan yang besar di sisi Allah. Dan saya sebutkan pula berbagai dalil yang mendukung hadits ini. (3) Barang siapa meyakini bahwa Nabi Muhammad Shallallahu’alaihiwasallam tidak menyampaikan risalah dari Allah secara sempurna maka ia telah melakukan kedustaan yang besar di sisi Allah".
Lalu sang imam berkomentar (ia terlihat gusar dan gelisah), "Demi Allah, sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu’alaihiwasallam telah melihat Allah di dunia dengan kedua mata kepalanya".
Namun aku hanya menyambut komentar si imam dengan ucapan, "Jazakallah khairan. (Tentunya kita tahu) bahwa Aisyah sebagai istri Rasul Shallallahu’alaihiwasallam tentu lebih tahu akan keadaan beliau. Kalaulah Rasulullah Shallallahu’alaihiwasallam benar-benar telah melihat Rabb-nya di dunia tentu Aisyah akan mengabarkannya, tapi kenapa ia tidak mengabarkannya?".
Lalu ia mendesakku dengan pertanyaan bertubi-tubi.
Aku katakan, "Ya akhi, tunggulah sebentar, beri kesempatan kepadaku agar aku selesaikan jawabanku satu persatu. Setelah itu silahkan engkau lanjutkan dengan pertanyaan lain sekehendakmu. Apa yang aku ketahui akan aku jawab, dan apa yang tidak aku ketahui akan aku katakan padamu, "Wallahu a'lam".
Lalu aku abaikan orang itu dan aku teruskan ceramahku. Aku tidak tahu apakah ia tetap duduk di situ atau pergi meninggalkan majelis, karena akupun sengaja tidak menoleh kepadanya.
Terdengar olehku bisikan orang, "Benar juga ucapan orang ini" Terdengar juga dari selain dia kata-kata lain, "Demi Allah, lelaki ini tidak menyampaikan melainkan firman Allah dan sabda Rasul-Nya Shallallahu’alaihiwasallam".
Adzan Isya dikumandangkan, maka berakhirlah acara tersebut, lantas jama'ah masjid melaksanakan shalat Isya. Tiba-tiba mereka mendorongku untuk menjadi imam Isya". Aku katakan, "Sama sekali aku tidak mau menjadi imam".
Mereka malah menjawab, "Demi Allah, shalatlah mengimami kami, demi Allah, shalatlah mengimami kami". Akhirnya aku katakan, "Baiklah kalau begitu".
Akhirnya akupun shalat mengimami mereka. Usai shalat aku menunggu sejenak, kemudian aku pulang bersama para pemuda Anshar as-Sunnah.
Aku bertanya kepada mereka, "Kemana sang imam pergi?". Mereka menjawab, "Telah diusir!". "Lho siapa yang mengusirnya?" tanyaku lagi. "Demi Allah, jama'ahnya yang mengusir dia!" tandas mereka.
Itulah yang terjadi wahai saudara-saudaraku. Singkatnya jika ada yang datang berdakwah kepada mereka kemudian membodoh-bodohkan pengikut aliran tijani, boleh jadi mereka akan mememenggal lehermu, tidak cukup hanya diusir! Tapi jika kalian datang berdakwah kepada mereka dengan hikmah dan lemah lembut, maka Allah akan memberikan manfaat kepada mereka dengan lantaran perangai tersebut.
Hendaknya engkau berbekal dengan ilmu yang bermanfaat, argumentasi yang kokoh, senantiasa memprioritaskan hikmah di dalam dakwah kalian. Wajib atas kalian untuk berhias diri dengan akhlak mulia yang telah dianjurkan Allah dalam kitab-Nya dan Rasulullah Shallallahu’alaihiwasallam. Sesungguhnya itu merupakan (salah satu) sarana (terbesar) untuk mendapatkan pertolongan dan kesuksesan".[139]
Sekali lagi kami ingin mengingatkan, bahwa kami di sini tidak sedang mengingkari disyariatkannya pengidentifikasian terang-terangan nama individu atau kelompok yang ditahdzir jika memang diperlukan; karena memang ada dalil yang menunjukkan akan hal itu.
Masalah ini perlu kami tekankan kembali; karena akhir-akhir ini ada sebagian orang yang sama sekali melarang hal tersebut di atas, berlandaskan sebagian dalil yang menunjukkan akan hal itu, sayangnya ia tidak tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa di sana juga ada dalil shahih dan praktek para ulama salaf yang menunjukkan bolehnya pengidentifikasian nama individu atau kelompok yang ditahdzir, jika memang diperlukan. Wallahua'lam.
-----
Footnote
[101] Majmu’ al-Fatawa (XXXV/414). Lihat pula: Sittu Durar min Ushul Ahl al-Atsar karya Syaikh Abdul Malik Ramadhani (hal. 109-112).
[102] Lihat: Al-Kafiah fi al-Jadal (hal. 20-21).
[103] HR. Al-Khathib al-Baghdady dalam Syaraf Ashab al-Hadits (hal.65 no.51) dan yang lainnya. Hadits ini dishahihkan oleh Imam Ahmad sebagaimana dalam Syaraf Ashab al-Hadits (hal.65). Al-‘Ala’i dalam Bughyah al-Multamis (hal.34) berkata “Hasan shahih gharib”. Ibn al-Qayyim dalam Thariq al-Hijratain (hal.578) berkata, “Hadits ini diriwayatkan dari banyak jalan yang saling menguatkan”. Senada dengan perkataan Ibn al-Qayyim: penjelasan al-Qashthallani dalam Irsyad as-Sari (I/7). Syaikh Salim al-Hilaly telah mentakhrij hadits ini secara riwayah dan dirayah dalam kitabnya Irsyad al-Fuhul ila Tahrir an-Nuqul fi Tashih Hadits al-‘Udul, dan beliau menyimpulkan bahwa derajat hadits ini adalah hasan.
[104] Lihat dalil-dalil tersebut dalam kitab: Mauqif Ahl as-Sunnah (II/482-488), al-Mahajjah al-Baidha’ (hal. 55-74), ar-Radd ‘ala al-Mukhalif (hal. 22-29), dan Munazharat A’immah as-Salaf (hal.14-19).
[105] HR. Ahmad (III/4-5). Para muhaqqiq Musnad (XVII/47) menshahihkan isnadnya. Hadits ini aslinya dalam Bukhari (hal. 1454 no. 6933) dan Muslim (II/744 no. 1064).
[106] HR. Ibnu Majah (I/62 no. 176). Syaikh al-Albani dalam Shahih Sunan Ibn Majah (I/76) berkata, “Hasan shahih”.
[107] Al-Furuq (IV/207),
[108] Majmu’ Fatawa Syaikhil Islam (XXVIII/231).
[109] Lihat: Mathla’ al-Fajr fi Fiqh az-Zajr bi al-Hajr karya Syaikh Salim aHilali (hal. 62-77) dan Ijma’ al-‘Ulama’ ‘ala al-Hajr wa at-Tahdzir min Ahl al-Ahwa’ karya Syaikh Khalid azh-Zhufairi (hal. 89-153).
[110] Tidak semua tokoh yang kami sebutkan di sini berakidah Ahlus Sunnah dalam setiap permasalahan, namun ada sebagian kecil dari mereka yang berseberangan dengan Ahlus Sunnah dalam berbagai permasalahan. Sengaja mereka kami sebutkan pula, agar umat tahu bahwa metode tahdzir ini juga diterapkan oleh para ahli ilmu di luar lingkaran Ahlus Sunnah, maka amat keliru jikalau Ahlus Sunnah selalu dipojokkan akibat mereka menerapkan metode ini, wallahu a’lam.
[111] R. Muslim (no. 1).
[112] Dicetak di Riyadh: Dar Athlas al-Khadhra’, dengan tahqiq Dr. Fahd al-Fuhaid.
[113] Dicetak di Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, dengan tahqiq Dr. Rasyid al-Alma’i.
[114] Dicetak di Riyadh; Dar at-Tauhid, dengan tahqiq Muhammad Alu ‘Amir.
[115] Dicetak di Madinah: Maktabah al-‘Ulum wa al-Hikam, dengan tahqiq Prof. Dr. Ali al-Faqihi.
[116] Dicetak di Kuwait: Dar al-Kutub ats-Tsaqafiyyah, dengan tahqiq Abdurrahman Badawi.
[117] Dicetak di Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub, dengan tahqiq Abdurrahman Dimasyqiyyah.
[118] Dicetak di Riyadh: Maktabah Dar al-Minhaj, dengan tahqiq Dr. Abdullah as-Sahli.
[119] Dicetak di Riyadh: Adhwa’ as-Salaf, dengan tahqiq Dr. Al-Hasan al-‘Alawi.
[120] Dicetak di Beirut: Mu’assasah ar-Risalah, dengan tahqiq Abdurrahman at-Turki dan Kamil al-Kharrath.
[121] Dicetak di Riyadh: Dar al-Hidayah.
[122] Dicetak di Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, dengan ‘inayah ad-Dani Zahwi.
[123] Dicetak di Damam: Dar Ibn al-Jauzi, dengan tahqiq Abdurrahman ar-Rahmah.
[124] Dicetak di Damam: Dar Ibn al-Qayyim.
[125] Dicetak di Kairo: Dar al-Imam Ahmad.
[126] Dicetak di Damam: Dar Ibn al-Jauzi.
[127] Dicetak di Emirat: Maktabah al-Furqan.
[128] Dicetak di Damam: Dar Ibn al-Qayyim.
[129] Dicetak di Kairo; Dar al-Imam Ahmad.
[130] Lihat makalah yang kami tulis dengan judul: "Upaya Menjaga Kemurnian Islam Menyoal Tahdzir dan Norma-Normanya" (hal. 4-5).
[131] HR. Muslim (II/1020 no. 1401 -asy-syamilah).
[132] HR. Muslim (II/1114 no. 1480 -asy-syamilah). Nabi Shallallahu’alaihiwasallam mengeluarkan pernyataan ini tatkala dimintai pendapat oleh Fathimah binti Qais tentang siapa di antara dua sahabat tadi yang akan dia terima pinangannya, lalu Nabi Shallallahu’alaihiwasallam menunjukkan kekurangan masing-masing dari keduanya dan menasehatkan Fathimah mau dinikahi Usamah bin Zaid. Seandainya menyebutkan aib dua orang sahabat Nabi Shallallahu’alaihiwasallam untuk kepentingan duniawi seorang wanita diperbolehkan, tentunya menyebutkan aib ahlul bid'ah untuk kepentingan akherat kaum muslimin lebih diperbolehkan. Lihat: Mauqif Ahl as-Sunnah (II/488) dan Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam (XXVIII/230).
[133] Majmu’ Fataawa wa Maqaalaat Mutanawwi’ah (VIII/242). Lihat pula: Ar-Radd ‘ala al-Mukhalif (hal. 60).
[134] Syarh al-Arba’in an-Nawawiyyah (hal. 317).
[135] Sebagaimana dalam kaset beliau yang berjudul "Tsimar Murrah min Ghiras at-Tajrih bi Ghairi Haq".
[136] Al-Hats ‘ala al-Mawaddah (hal. 24).
[137] Op Cit (hal. 25).
[138] Op Cit (hal. 30).
[139] Diringkas dari al-Hats 'ala al-Mawaddah (hal. 24-30). Dalam menerjemahkan kisah ini penulis banyak terbantu dengan edisi Indonesia buku ini "Dakwah Salafiyah Dakwah Penuh Hikmah, Sepenggal Kisah Perjalanan Dakwah asy-Syaikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali" (hal. 36-45) terjemahan ustadz Abu Affan Asasuddin.
CONTOH KEDUA BELAS
CONTOH KEDUA BELAS: Ketika seorang da’i Ahlus Sunnah diundang untuk berdakwah di masjid ahlul bid’ah atau tempat mereka -dan hal tersebut tidak menimbulkan fitnah bagi masyarakat serta diharapkan menghasilkan maslahat- maka hendaknya dia memenuhi undangan tersebut dan memanfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya untuk menyampaikan al-haq dengan penuh hikmah, nasehat dan diskusi yang baik.
Hal ini berlandaskan firman Allah ta'ala,
]وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان[.
Artinya: "Dan saling tolong menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan ketakwaan dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan". QS. Al-Maidah: 2.
Bekerja sama dengan ahlul bid'ah termasuk tolong menolong dalam kebaikan jika memenuhi beberapa syarat:
1. Bekerja sama tersebut dalam perkara yang haq yang bersumber dari syari'at.
2. Mempertimbangkan maslahat dan madharat; jika kerjasama tersebut akan menghasilkan maslahat yang lebih besar daripada bahaya penyimpangan mereka atau bisa menghindarkan bahaya yang lebih besar daripada bahaya bid'ah mereka; maka kita diperintahkan bekerjasama dengan mereka. Namun jika sebaliknya maka tidak boleh.
3. Mereka tidak menjadikan kerjasama ini sebagai jalan untuk menyebarkan bid'ah mereka atau untuk menguatkan kebatilan mereka.
4. Mempertimbangkan norma-norma penerapan metode hajr[140] di samping syarat-syarat tersebut di atas[141].
Oleh karena itu kita dapatkan bahwa Nabi shallallahu’alaihiwasallam pun pernah mendatangi tempat-tempat orang musyrik untuk mendakwahi mereka[142].
Maka merupakan suatu keanehan tatkala ada seorang da’i yang berdakwah di tempat ahlul bid'ah -dan telah memenuhi norma-norma di atas- namun dia tetap ditahdzir gara-gara hal tersebut. Keanehan itu terlihat dari dua sisi:
Sisi pertama: Si da’i itu datang ke tempat ahlul bid’ah bukan untuk didakwahi, tapi untuk mendakwahi mereka dan menyampaikan al-haq.
Sisi kedua: Para ulama Salafiyyin juga mengisi pengajian di tempat-tempat ahlul bid’ah dan orang-orang yang memiliki penyimpangan-penympangan manhaj. Syaikh al-‘Allamah Ibn Baz rahimahullah dan Syaikh al-‘Allamah Ibn Utsaimin rahimahullah pernah menyampaikan pengajian via telpon di yayasan sosial Ihya’ at-Turats Kuwait[143]. Syaikh al-‘Allamah Ibn Utsaimin rahimahullah pernah mengisi kajian di hadapan para pramuka Saudi yang notabene rata-rata dikoordinir oleh orang-orang Ikhwanul Muslimin. Syaikh Rabi’ bin Hadi al-Madkhali hafizhahullah mengisi pengajian di masjid-masjid Tarekat Tijaniyah di Sudan[144].
-----
Footnote
[140] Menghajr ahlul bid’ah adalah ibadah, maka -sebagaimana ibadah-ibadah yang lain- hajr harus memenuhi dua syarat diterimanya suatu amalan, yaitu ikhlas dan mutaba’ah (mengikuti tuntunan Nabi shallallahu’alaihiwasallam). Lihat: Majmu’ Fatawa Syaikh al-Islam (XXVIII/207).
Ikhlas dalam menghajr maksudnya tujuan dia menghajr benar-benar karena mengharap ridha Allah ta’ala, bukan karena kepentingan-kepentingan duniawi; seperti menjatuhkan seseorang yang dikhawatirkan menyaingi dia dalam dakwah, atau karena iri dan hasad dengan kelebihan yang dimiliki orang yang dihajr.
Maksud dari mutaba’ah dalam menghajr adalah: memperhatikan norma-norma yang digariskan para ulama berdasarkan dalil-dalil dari kitab dan sunnah. Di antara norma-norma tersebut: memperhatikan pengaruh orang yang menghajr, memperhatikan kondisi orang yang dihajr, melihat masa hajr dan melihat situasi masyarakat tempat orang yang menghajr dan dihajr.
Syaikh Dr. Ibrahim bin ‘Amir ar-Ruhaily hafizhahullah dalam Nashihah li asy-Syabab (hal.4-6) menjelaskan norma-norma hajr, “Orang yang melihat perkara hajr seyogyanya dia memperhatikan norma-norma syari’at yang disebutkan oleh para ulama muhaqqiqin di dalam bab ini, yang darinya akan terlihat dengan jelas dan penuh ketelitian, pelaku kesalahan manakah yang disyariatkan untuk dihajr dan pelaku kesalahan manakah yang tidak disyariatkan untuk dihajr. Di antara norma-norma tersebut:
1. Berkenaan dengan orang yang menghajr: dia harus kuat dan berpengaruh hajrnya dalam membuat orang yang bersalah jera, adapun jika yang menghajr lemah, niscaya hajrnya tidak mendatangkan manfaat. Hal ini (harus diperhatikan) jika maksud dari hajr adalah pemberian pelajaran bagi orang yang salah. Adapun jika maksud dari hajr adalah untuk mendatangkan maslahat bagi yang menghajr, tatkala dikhawatirkan jika dia berbaur dengan orang yang bersalah akan berdampak buruk bagi agamanya, maka saat itu dia diperbolehkan untuk menghajr siapa saja yang akan berdampak buruk baginya. Hal ini (dibenarkan) karena hajr disyariatkan untuk (1) maslahat yang menghajr; yaitu dengan menghajr siapa saja yang akan berdampak buruk baginya, (2) disyariatkan untuk maslahat orang yang dihajr; yaitu jika ada orang bersalah yang diharapkan akan rujuk jika dia dihajr, (3) hajr disyariatkan untuk maslahat umat; yaitu tatkala sebagian orang yang bersalah jika dia dihajr maka umat akan mengambil pelajaran dari hajr tersebut, sehingga mereka tidak akan mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang tersebut. (Tiga) model hajr ini dilandaskan di atas dalil-dalil.
2. Berkenaan dengan orang yang dihajr: dia harus memetik manfaat dari hajr tersebut; yaitu menjadikan dia rujuk kepada al-haq. Adapun jika hajr tersebut tidak bermanfaat baginya, bahkan terkadang akan menjadikan dia semakin jauh dan menjadi-jadi, maka saat itu tidak disyariatkan bagi dia untuk dihajr.
Hal ini kembali kepada tabiat sebagian orang yang keras dan tidak mau tunduk, apapun yang terjadi. Orang model seperti ini tidak ada manfaatnya untuk dihukum dan dihajr, bahkan terkadang yang bermanfaat baginya adalah metode ta’lif dan kelemah lembutan.
Terkadang pula ‘kemandulan’ hajr kembali kepada pengaruh lain, misalnya orang yang akan dihajr adalah seorang pembesar, orang kaya atau orang yang memiliki kedudukan; orang-orang model seperti ini biasanya jika dihajr tidak akan mendatangkan manfaat baginya; karena mereka tahu bahwa mereka tidak butuh dengan orang yang menghajr.
Oleh karena itu Nabi shallallahu’alaihiwasallam menta’lif para pembesar kabilah-kabilah dan orang-orang yang memiliki kedudukan di kaumnya, seperti Abu Sufyan, ‘Uyainah bin Hishn, al-Aqra’ bin Habis dan yang serupa. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, “Oleh karena itu Nabi shallallahu’alaihiwasallam menta’lif sebagian orang dan menghajr sebagian yang lain, sebagaimana kedudukan tiga orang yang dihajr oleh beliau lebih utama daripada kebanyakan orang yang dita’lif beliau; karena rata-rata sebab dita’lifnya orang-orang tersebut adalah karena mereka termasuk pembesar yang terpandang di kaumnya” (Majmu’ al-Fatawa: XXVIII/206).
3. Berkenaan dengan jenis kesalahan: tidak ada jenis kesalahan tertentu yang jika seseorang terjatuh ke dalamnya berarti dia harus dihajr, atau kesalahan tertentu yang jika seseorang terjatuh ke dalamnya berarti dia tidak boleh dihajr, sebagaimana anggapan sebagian orang; bahwa orang yang terjatuh kepada bid’ah berarti dia harus dihajr adapun maksiyat maka tidak, atau anggapan bahwa jika orang terjatuh kepada bid’ah yang sampai taraf kekufuran berarti dia harus dihajr, sedang yang tidak sampai ke taraf kekufuran berarti dia tidak dihajr, atau anggapan bahwa jika orang terjatuh kepada dosa besar berarti dia harus dihajr, kalau dosa kecil tidak.
Yang benar: hajr disyariatkan atas setiap kesalahan meskipun kecil, jika memang orang yang melakukan kesalahan tersebut disyariatkan untuk dihajr dan dia akan memetik manfaat dari hajr tersebut.
Jadi barometer penilaian dihajr tidaknya seseorang kembali kepada bermanfaat tidaknya hajr tersebut, bukan kembali kepada besar tidaknya kesalahan orang itu. Atas dasar ini, terkadang seorang yang mulia dari Ahlus Sunnah bisa dihajr karena kesalahan kecil yang dia lakukan; sebagaimana tatkala Nabi shallallahu’alaihiwasallam tidak menjawab salam ‘Ammar bin Yasir gara-gara beliau memakai minyak wangi za’faran (minyak wangi khusus wanita). (HR. Abu Dawud: V/8), juga tatkala beliau shallallahu’alaihiwasallam tidak mau menjawab salam orang yang membangun kubah sampai dia menghancurkannya. (HR. Abu Dawud: V/402). Terkadang pula orang yang kemuliaannya di bawah kemuliaan orang yang dihajr nabi shallallahu’alaihiwasallam tetap beliau ta’lif, padahal mereka melakukan kesalahan-kesalahan besar; sebagaimana dita’lifnya al-Aqra’ bin Habis, ‘Uyainah bin Hishn, bahkan beberapa orang munafiq seperti Abdullah bin Ubay dan yang semisal. Ini semua tergantung maslahat dan pertimbangan norma-norma lain dalam masalah hajr.
4. Berkenaan dengan zaman dan daerah terjadinya kesalahan: Harus dibedakan antara zaman dan daerah yang menjamur di dalamnya kemungkaran serta pelakunya memiliki kekuatan, dengan zaman dan daerah yang sedikit kemungkaran di dalamnya serta pelakunya tidak memiliki kekuatan. Jika Ahlus Sunnah merupakan mayoritas penduduk di suatu zaman atau daerah, maka hajr disyariatkan -dengan memperhatikan norma-norma hajr yang lain-, karena posisi orang yang bersalah lemah, niscya dia akan jera dari kesalahannya.
Contoh hal ini adalah apa yang difirmankan Allah ta’ala tatkala menggambarkan kondisi Ka’ab bin Malik dan kedua temannya (ketika mereka dihajr Nabi shallallahu’alaihiwasallam dan seluruh kaum muslimin): “Hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas, dan jiwa merekapun telah sempit (pula terasa) oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari (siksa) Allah melainkan kepada-Nya saja”. QS. At-Taubah: 118. Contoh lain: saat Shabigh bin ‘Asal jera tatkala dihajr oleh Umar dan seluruh kaum muslimin, sebagaimana telah maklum dalam sejarah.
Adapun jika di suatu zaman atau daerah mayoritas penduduknya adalah ahlul batil dan orang-orang yang rusak, maka tidak disyariatkan hajr -kecuali dalam beberapa kondisi tertentu- karena saat itu hajr tidak bisa merealisasikan tujuannya, yakni tidak bisa memberi pelajaran bagi orang yang bersalah, bahkan mungkin akan berdampak buruk bagi ahlul haq.
Syaikhul Islam Ibn Taimiyah menerangkan, “Oleh karena itu dibedakan antara daerah yang menjamur di dalamnya bid’ah -sebagaimana menjamurnya pengingkaran atas takdir di kota Bashrah, perdukunan di kota Khurasan dan ajaran Syi’ah di kota Kufah- dibedakan dengan daerah yang tidak menjamur di dalamnya bid’ah. Juga dibedakan antara para imam yang ditaati dengan yang lain. Jika maksud syari’at telah diketahui, maka ditempuhlah jalan terdekat yang mengantarkan padanya”. (Majmu’ al-Fatawa: XXVIII/206-207).
5. Berkenaan dengan lamanya hajr: seyogyanya lamanya hajr disesuaikan dengan kondisi orang yang bersalah dan jenis kesalahannya. Sebagian orang ada yang jera jika dihajr selama sehari dua hari, atau sebulan dua bulan, sebagian yang lain ada yang kurang atau lebih. Jika tujuan dari hajr telah tercapai maka saat itu hajr wajib untuk dihentikan, jika tidak maka akan menimbulkan keputusasaan, sebagaimana jika lamanya hajr kurang dari masa yang cocok niscaya hajr tersebut tidak bermanfaat.
Ibnul Qayyim tatkala menyebutkan pelajaran-pelajaran yang dapat dipetik dari kisah dihajrnya Ka’ab bin Malik dan dua orang temannya oleh Nabi shallallahu’alaihiwasallam, beliau berkata, “Di dalam kisah ini terdapat dalil disyariatkannya seorang imam, ulama atau tokoh yang ditaati untuk menghajr pelaku perbuatan tercela, dan hajr mereka tersebut merupakan obat baginya, maka jangan sampai dosisnya kurang sehingga tidak mendatangkan kesembuhan, juga jangan sampai over dosis sehingga mengakibatkan dia mati; karena maksud dari hajr adalah pemberian pelajaran bukan pembinasaan”. (Zad al-Ma’ad: III/20)”.
Silahkan rujuk pula referensi-referensi berikut: Mauqif Ahl as-Sunnah (II/553-563 dan Hajr al-Mubtadi’ karya Syaikh Bakr Abu Zaid (hal. 40 dst).
[141] Lihat: Haqiqah al-Bid'ah wa Ahkamuha karya Sa'ad bin Nashir al-Ghamidi dan Da'wah Ahl al-Bida' karya Khalid bin Utsman az-Zahrani dengan kata pengantar Syaikh Shalih al-Fauzan. Mohon maaf kepada para pembaca yang budiman; jilid dan halaman tempat disebutkannya norma-norma ini di dalam kedua buku di atas lupa kami catat. Ketika kami menyelesaikan makalah ini kami sedang berlibur di Indonesia, padahal dua buku tersebut kami tinggal di Madinah. InsyaAllah sekembalinya kami ke Madinah akan kami tambahkan data yang kurang lengkap tersebut.
[142] Lihat beberapa contohnya dalam: Shahih as-Sirah an-Nabawiyah karya Syaikh al-Albani (hal.141-144).
[143] Lihat: Rifqan Ahl as-Sunnah karya Syaikh al-'Allamah Abdul Muhsin al-'Abbad (hal. 45).
[144] Lihat: Al-Hats ‘ala al-Mawaddah (hal. 24 dst) dan silahkan rujuk kembali hal 34-36 dari makalah ini.
Hal ini berlandaskan firman Allah ta'ala,
]وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان[.
Artinya: "Dan saling tolong menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan ketakwaan dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan". QS. Al-Maidah: 2.
Bekerja sama dengan ahlul bid'ah termasuk tolong menolong dalam kebaikan jika memenuhi beberapa syarat:
1. Bekerja sama tersebut dalam perkara yang haq yang bersumber dari syari'at.
2. Mempertimbangkan maslahat dan madharat; jika kerjasama tersebut akan menghasilkan maslahat yang lebih besar daripada bahaya penyimpangan mereka atau bisa menghindarkan bahaya yang lebih besar daripada bahaya bid'ah mereka; maka kita diperintahkan bekerjasama dengan mereka. Namun jika sebaliknya maka tidak boleh.
3. Mereka tidak menjadikan kerjasama ini sebagai jalan untuk menyebarkan bid'ah mereka atau untuk menguatkan kebatilan mereka.
4. Mempertimbangkan norma-norma penerapan metode hajr[140] di samping syarat-syarat tersebut di atas[141].
Oleh karena itu kita dapatkan bahwa Nabi shallallahu’alaihiwasallam pun pernah mendatangi tempat-tempat orang musyrik untuk mendakwahi mereka[142].
Maka merupakan suatu keanehan tatkala ada seorang da’i yang berdakwah di tempat ahlul bid'ah -dan telah memenuhi norma-norma di atas- namun dia tetap ditahdzir gara-gara hal tersebut. Keanehan itu terlihat dari dua sisi:
Sisi pertama: Si da’i itu datang ke tempat ahlul bid’ah bukan untuk didakwahi, tapi untuk mendakwahi mereka dan menyampaikan al-haq.
Sisi kedua: Para ulama Salafiyyin juga mengisi pengajian di tempat-tempat ahlul bid’ah dan orang-orang yang memiliki penyimpangan-penympangan manhaj. Syaikh al-‘Allamah Ibn Baz rahimahullah dan Syaikh al-‘Allamah Ibn Utsaimin rahimahullah pernah menyampaikan pengajian via telpon di yayasan sosial Ihya’ at-Turats Kuwait[143]. Syaikh al-‘Allamah Ibn Utsaimin rahimahullah pernah mengisi kajian di hadapan para pramuka Saudi yang notabene rata-rata dikoordinir oleh orang-orang Ikhwanul Muslimin. Syaikh Rabi’ bin Hadi al-Madkhali hafizhahullah mengisi pengajian di masjid-masjid Tarekat Tijaniyah di Sudan[144].
-----
Footnote
[140] Menghajr ahlul bid’ah adalah ibadah, maka -sebagaimana ibadah-ibadah yang lain- hajr harus memenuhi dua syarat diterimanya suatu amalan, yaitu ikhlas dan mutaba’ah (mengikuti tuntunan Nabi shallallahu’alaihiwasallam). Lihat: Majmu’ Fatawa Syaikh al-Islam (XXVIII/207).
Ikhlas dalam menghajr maksudnya tujuan dia menghajr benar-benar karena mengharap ridha Allah ta’ala, bukan karena kepentingan-kepentingan duniawi; seperti menjatuhkan seseorang yang dikhawatirkan menyaingi dia dalam dakwah, atau karena iri dan hasad dengan kelebihan yang dimiliki orang yang dihajr.
Maksud dari mutaba’ah dalam menghajr adalah: memperhatikan norma-norma yang digariskan para ulama berdasarkan dalil-dalil dari kitab dan sunnah. Di antara norma-norma tersebut: memperhatikan pengaruh orang yang menghajr, memperhatikan kondisi orang yang dihajr, melihat masa hajr dan melihat situasi masyarakat tempat orang yang menghajr dan dihajr.
Syaikh Dr. Ibrahim bin ‘Amir ar-Ruhaily hafizhahullah dalam Nashihah li asy-Syabab (hal.4-6) menjelaskan norma-norma hajr, “Orang yang melihat perkara hajr seyogyanya dia memperhatikan norma-norma syari’at yang disebutkan oleh para ulama muhaqqiqin di dalam bab ini, yang darinya akan terlihat dengan jelas dan penuh ketelitian, pelaku kesalahan manakah yang disyariatkan untuk dihajr dan pelaku kesalahan manakah yang tidak disyariatkan untuk dihajr. Di antara norma-norma tersebut:
1. Berkenaan dengan orang yang menghajr: dia harus kuat dan berpengaruh hajrnya dalam membuat orang yang bersalah jera, adapun jika yang menghajr lemah, niscaya hajrnya tidak mendatangkan manfaat. Hal ini (harus diperhatikan) jika maksud dari hajr adalah pemberian pelajaran bagi orang yang salah. Adapun jika maksud dari hajr adalah untuk mendatangkan maslahat bagi yang menghajr, tatkala dikhawatirkan jika dia berbaur dengan orang yang bersalah akan berdampak buruk bagi agamanya, maka saat itu dia diperbolehkan untuk menghajr siapa saja yang akan berdampak buruk baginya. Hal ini (dibenarkan) karena hajr disyariatkan untuk (1) maslahat yang menghajr; yaitu dengan menghajr siapa saja yang akan berdampak buruk baginya, (2) disyariatkan untuk maslahat orang yang dihajr; yaitu jika ada orang bersalah yang diharapkan akan rujuk jika dia dihajr, (3) hajr disyariatkan untuk maslahat umat; yaitu tatkala sebagian orang yang bersalah jika dia dihajr maka umat akan mengambil pelajaran dari hajr tersebut, sehingga mereka tidak akan mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang tersebut. (Tiga) model hajr ini dilandaskan di atas dalil-dalil.
2. Berkenaan dengan orang yang dihajr: dia harus memetik manfaat dari hajr tersebut; yaitu menjadikan dia rujuk kepada al-haq. Adapun jika hajr tersebut tidak bermanfaat baginya, bahkan terkadang akan menjadikan dia semakin jauh dan menjadi-jadi, maka saat itu tidak disyariatkan bagi dia untuk dihajr.
Hal ini kembali kepada tabiat sebagian orang yang keras dan tidak mau tunduk, apapun yang terjadi. Orang model seperti ini tidak ada manfaatnya untuk dihukum dan dihajr, bahkan terkadang yang bermanfaat baginya adalah metode ta’lif dan kelemah lembutan.
Terkadang pula ‘kemandulan’ hajr kembali kepada pengaruh lain, misalnya orang yang akan dihajr adalah seorang pembesar, orang kaya atau orang yang memiliki kedudukan; orang-orang model seperti ini biasanya jika dihajr tidak akan mendatangkan manfaat baginya; karena mereka tahu bahwa mereka tidak butuh dengan orang yang menghajr.
Oleh karena itu Nabi shallallahu’alaihiwasallam menta’lif para pembesar kabilah-kabilah dan orang-orang yang memiliki kedudukan di kaumnya, seperti Abu Sufyan, ‘Uyainah bin Hishn, al-Aqra’ bin Habis dan yang serupa. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, “Oleh karena itu Nabi shallallahu’alaihiwasallam menta’lif sebagian orang dan menghajr sebagian yang lain, sebagaimana kedudukan tiga orang yang dihajr oleh beliau lebih utama daripada kebanyakan orang yang dita’lif beliau; karena rata-rata sebab dita’lifnya orang-orang tersebut adalah karena mereka termasuk pembesar yang terpandang di kaumnya” (Majmu’ al-Fatawa: XXVIII/206).
3. Berkenaan dengan jenis kesalahan: tidak ada jenis kesalahan tertentu yang jika seseorang terjatuh ke dalamnya berarti dia harus dihajr, atau kesalahan tertentu yang jika seseorang terjatuh ke dalamnya berarti dia tidak boleh dihajr, sebagaimana anggapan sebagian orang; bahwa orang yang terjatuh kepada bid’ah berarti dia harus dihajr adapun maksiyat maka tidak, atau anggapan bahwa jika orang terjatuh kepada bid’ah yang sampai taraf kekufuran berarti dia harus dihajr, sedang yang tidak sampai ke taraf kekufuran berarti dia tidak dihajr, atau anggapan bahwa jika orang terjatuh kepada dosa besar berarti dia harus dihajr, kalau dosa kecil tidak.
Yang benar: hajr disyariatkan atas setiap kesalahan meskipun kecil, jika memang orang yang melakukan kesalahan tersebut disyariatkan untuk dihajr dan dia akan memetik manfaat dari hajr tersebut.
Jadi barometer penilaian dihajr tidaknya seseorang kembali kepada bermanfaat tidaknya hajr tersebut, bukan kembali kepada besar tidaknya kesalahan orang itu. Atas dasar ini, terkadang seorang yang mulia dari Ahlus Sunnah bisa dihajr karena kesalahan kecil yang dia lakukan; sebagaimana tatkala Nabi shallallahu’alaihiwasallam tidak menjawab salam ‘Ammar bin Yasir gara-gara beliau memakai minyak wangi za’faran (minyak wangi khusus wanita). (HR. Abu Dawud: V/8), juga tatkala beliau shallallahu’alaihiwasallam tidak mau menjawab salam orang yang membangun kubah sampai dia menghancurkannya. (HR. Abu Dawud: V/402). Terkadang pula orang yang kemuliaannya di bawah kemuliaan orang yang dihajr nabi shallallahu’alaihiwasallam tetap beliau ta’lif, padahal mereka melakukan kesalahan-kesalahan besar; sebagaimana dita’lifnya al-Aqra’ bin Habis, ‘Uyainah bin Hishn, bahkan beberapa orang munafiq seperti Abdullah bin Ubay dan yang semisal. Ini semua tergantung maslahat dan pertimbangan norma-norma lain dalam masalah hajr.
4. Berkenaan dengan zaman dan daerah terjadinya kesalahan: Harus dibedakan antara zaman dan daerah yang menjamur di dalamnya kemungkaran serta pelakunya memiliki kekuatan, dengan zaman dan daerah yang sedikit kemungkaran di dalamnya serta pelakunya tidak memiliki kekuatan. Jika Ahlus Sunnah merupakan mayoritas penduduk di suatu zaman atau daerah, maka hajr disyariatkan -dengan memperhatikan norma-norma hajr yang lain-, karena posisi orang yang bersalah lemah, niscya dia akan jera dari kesalahannya.
Contoh hal ini adalah apa yang difirmankan Allah ta’ala tatkala menggambarkan kondisi Ka’ab bin Malik dan kedua temannya (ketika mereka dihajr Nabi shallallahu’alaihiwasallam dan seluruh kaum muslimin): “Hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas, dan jiwa merekapun telah sempit (pula terasa) oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari (siksa) Allah melainkan kepada-Nya saja”. QS. At-Taubah: 118. Contoh lain: saat Shabigh bin ‘Asal jera tatkala dihajr oleh Umar dan seluruh kaum muslimin, sebagaimana telah maklum dalam sejarah.
Adapun jika di suatu zaman atau daerah mayoritas penduduknya adalah ahlul batil dan orang-orang yang rusak, maka tidak disyariatkan hajr -kecuali dalam beberapa kondisi tertentu- karena saat itu hajr tidak bisa merealisasikan tujuannya, yakni tidak bisa memberi pelajaran bagi orang yang bersalah, bahkan mungkin akan berdampak buruk bagi ahlul haq.
Syaikhul Islam Ibn Taimiyah menerangkan, “Oleh karena itu dibedakan antara daerah yang menjamur di dalamnya bid’ah -sebagaimana menjamurnya pengingkaran atas takdir di kota Bashrah, perdukunan di kota Khurasan dan ajaran Syi’ah di kota Kufah- dibedakan dengan daerah yang tidak menjamur di dalamnya bid’ah. Juga dibedakan antara para imam yang ditaati dengan yang lain. Jika maksud syari’at telah diketahui, maka ditempuhlah jalan terdekat yang mengantarkan padanya”. (Majmu’ al-Fatawa: XXVIII/206-207).
5. Berkenaan dengan lamanya hajr: seyogyanya lamanya hajr disesuaikan dengan kondisi orang yang bersalah dan jenis kesalahannya. Sebagian orang ada yang jera jika dihajr selama sehari dua hari, atau sebulan dua bulan, sebagian yang lain ada yang kurang atau lebih. Jika tujuan dari hajr telah tercapai maka saat itu hajr wajib untuk dihentikan, jika tidak maka akan menimbulkan keputusasaan, sebagaimana jika lamanya hajr kurang dari masa yang cocok niscaya hajr tersebut tidak bermanfaat.
Ibnul Qayyim tatkala menyebutkan pelajaran-pelajaran yang dapat dipetik dari kisah dihajrnya Ka’ab bin Malik dan dua orang temannya oleh Nabi shallallahu’alaihiwasallam, beliau berkata, “Di dalam kisah ini terdapat dalil disyariatkannya seorang imam, ulama atau tokoh yang ditaati untuk menghajr pelaku perbuatan tercela, dan hajr mereka tersebut merupakan obat baginya, maka jangan sampai dosisnya kurang sehingga tidak mendatangkan kesembuhan, juga jangan sampai over dosis sehingga mengakibatkan dia mati; karena maksud dari hajr adalah pemberian pelajaran bukan pembinasaan”. (Zad al-Ma’ad: III/20)”.
Silahkan rujuk pula referensi-referensi berikut: Mauqif Ahl as-Sunnah (II/553-563 dan Hajr al-Mubtadi’ karya Syaikh Bakr Abu Zaid (hal. 40 dst).
[141] Lihat: Haqiqah al-Bid'ah wa Ahkamuha karya Sa'ad bin Nashir al-Ghamidi dan Da'wah Ahl al-Bida' karya Khalid bin Utsman az-Zahrani dengan kata pengantar Syaikh Shalih al-Fauzan. Mohon maaf kepada para pembaca yang budiman; jilid dan halaman tempat disebutkannya norma-norma ini di dalam kedua buku di atas lupa kami catat. Ketika kami menyelesaikan makalah ini kami sedang berlibur di Indonesia, padahal dua buku tersebut kami tinggal di Madinah. InsyaAllah sekembalinya kami ke Madinah akan kami tambahkan data yang kurang lengkap tersebut.
[142] Lihat beberapa contohnya dalam: Shahih as-Sirah an-Nabawiyah karya Syaikh al-Albani (hal.141-144).
[143] Lihat: Rifqan Ahl as-Sunnah karya Syaikh al-'Allamah Abdul Muhsin al-'Abbad (hal. 45).
[144] Lihat: Al-Hats ‘ala al-Mawaddah (hal. 24 dst) dan silahkan rujuk kembali hal 34-36 dari makalah ini.
Subscribe to:
Posts (Atom)